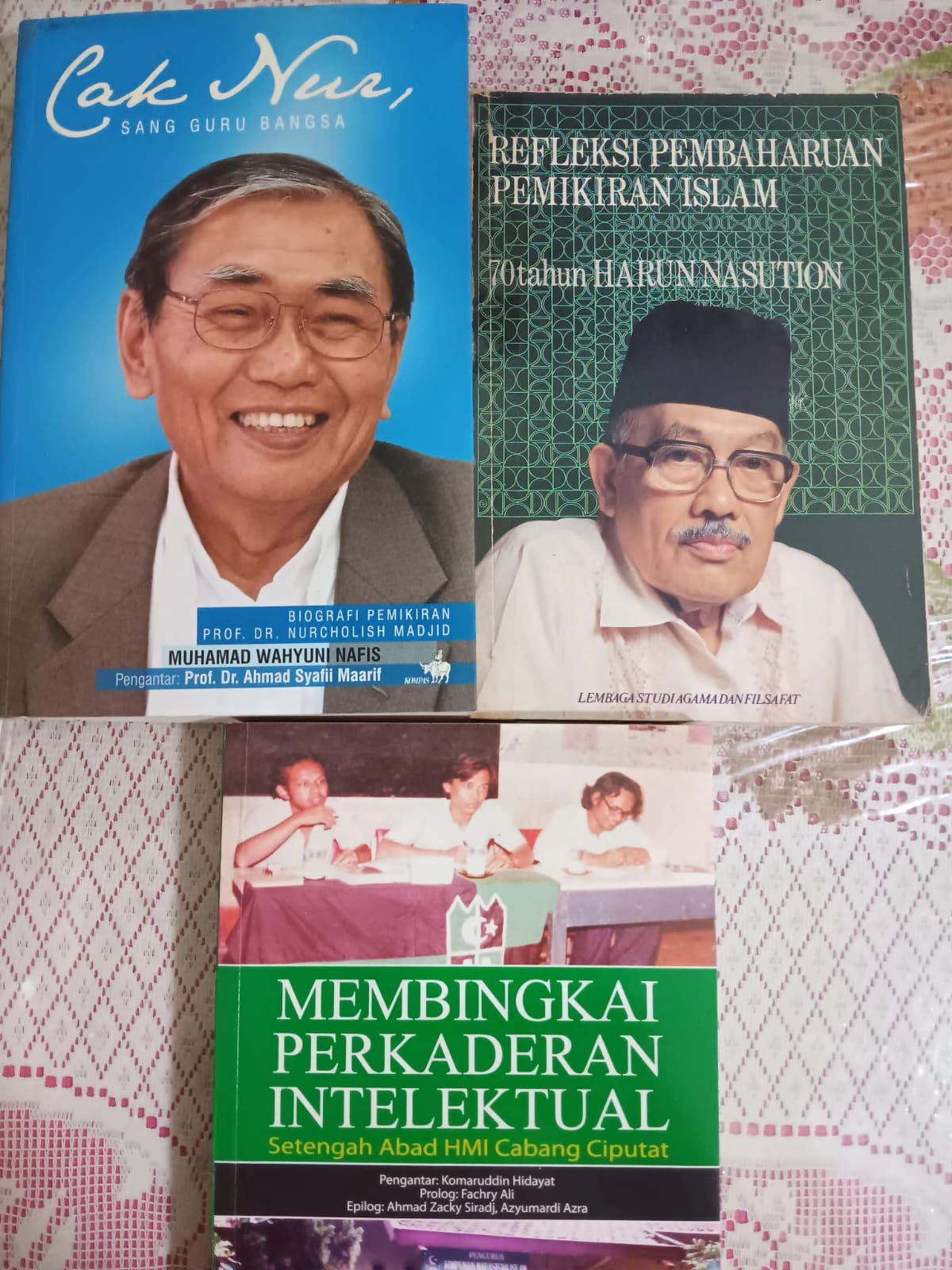Haji Agus Salim (goodnewsfromindonesia.id)
Oleh : Renville Almatsier*
Sabtu lalu saya hadir pada acara Peringatan 70 tahun Wafatnya Haji Agus Salim di aula Universitas YARSI, Jakarta. Pada kesempatan itu juga diluncurkan buku “Hadji Agus Salim, The Grand Old Man: Jurnalis, Ulama, Diplomat”.
Pengetahuannya yang luas mengenai agama Islam, dipadu dengan intelektualitas, kesederhanaan, serta kematangan berpolitik menjadikannya tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penampilannya yang khas, dia kemudian dikenal sebagai The Grand Old Man.
Haji Agus Salim merupakan salah satu dari Bapak Bangsa yang mewariskan tradisi intelektualisme dan moral nasional kepada kita. Sekalipun berlatar ulama, dia adalah anggota Panitia Sembilan yang menghapus tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Piagam Djakarta. Itulah yang menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi moderen hingga sekarang.
Kebetulan saya masih menyimpan buku “Djedjak Langkah Hadji A. Salim”, terbitan Tintamas, 1954, berisi pilihan karangan, termasuk pidatoya di depan Volksraad. Dari buku ini saya mula-mula bisa membaca isi pikirannya tentang berbagai hal, mulai dari persatuan Islam, kemajuan perempuan Bumiputera, pergerakan politik hingga resensi mengenai pementasan Dardanella. Tulisan-tulisan itu pernah dimuat dalam buku, majalah maupun koran-koran antara lain Dunia Islam, Neratja, Het Licht, dan Pergerakan Penjadar.
Pada acara minggu lalu itu, selain Prof. Emil Salim sebagai keynote speaker, ada Prof. Meutia Hatta, Prof. Komaruddin Hidayat, Prof. Fasli Djalal, dan Mohammad Ali dengan moderator Burmalis Ilyas. Referensi yang dikemukan para pembicara itu betul-betul membuka mata kami yang hadir akan multi talentanya Haji Agus Salim, sesuai judul buku yang dibahas.
Prof. Emil Salim menceritakan bagaimana ceramah serta lobi-lobinya di Cornell University telah membuka mata dunia, khususnya orang-orang Barat, tentang Indonesia dan Islam di Indonesia. Dari para pembicara lainnya, saya mendapat pengetahuan luar biasa. Mereka mengungkapkan pandangannya mengenai keterampilan Almarhum dari sisi ilmu mereka masing-masing.
Terlahir dengan nama Masjhudul Haq, putra Sutan Muhammad Salim, dia dipanggil “Gus” oleh seorang pelayan asal Jawa ketika indekos di Jakarta. Selanjutnya dia kemudian dikenal dengan nama Agus Salim. Sepulang merantau dari tanah Arab, di tahun 1912, empat tahun sebelum ayah saya lahir, beliau menikah dengan kakak ayah, Zainatun Nahar Almatsier. Mereka kemudian mempunyai anak-anak dengan nama-nama yang unik, seakan mencerminkan perkembangan pemikirannya: Theodora Atia, Jozef Thewfiq, Violeta Hanifa, Maria Zenobia, Syewket, Mohammad Islam Basyari, Siti Asia (Bibsy), dan Mohammad Ciddiq.
Meskipun sesungguhnya dia setingkat ipar bagi ayah saya, saya memanggilnya Inyik Agus Salim. Sedangkan istrinya kami panggil Maatje, sama seperti bagaimana Bung Karno memanggilnya. Masih saya ingat adalah bila kami berkumpul pada hari Lebaran di rumah Laan Theresia Kerk 20 (kini Jalan Haji Agus Salim), persis di seberang gereja yang kini masih ada. Inyik selalu mengenakan teluk-belanga. Satu-satu persatu kami anak-anak antre menyalaminya dan dicium. Sampai kini saya masih merasakan geli gesekan kumis dan janggutnya yang fenomenal itu.
Jadilah pertemuan di aula YARSI minggu lalu itu merupakan reuni berkumpulnya para keturunan tokoh-tokoh republik ini, antara lain, anak-anak Bung Hatta, Bung Syahrir, Sjafruddin Prawiranegara, dan lain-lain.
* Pengamat Sosial dan Mantan Jurnalus Majalah Tempo
Editor: Jufri Alkatiri