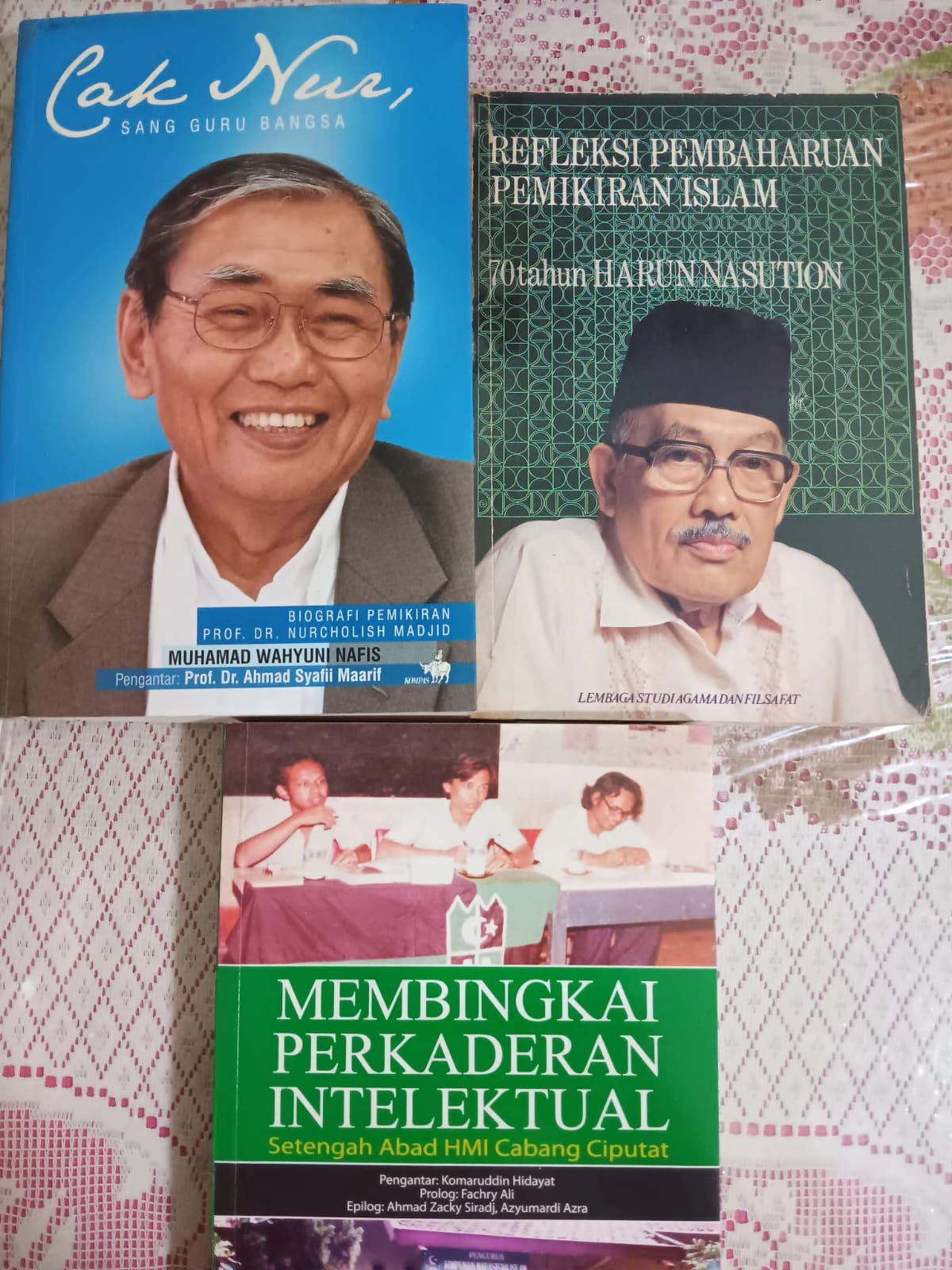Perayaan Imlek (Foto: kiddles.id)
Oleh : Renville Almatsier*
Perayaan Imlek sudah beberapa minggu berlalu. Semua ikut memeriahkannya, tidak terbatas warga negara keturunan Tionghoa. Namun ada perasaan yang setiap kali muncul saat saya merasakan kemeriahan perayaan menyambut tahun baru itu. Perasaan itu, semacam keprihatinan, selalu muncul. Hati saya selalu berbisik, benarkah partisipasi kita ikut merayakan Imlek itu, luhur ?
Saya teringat, Gus Dur pernah menyitir bahwa toleransi di Indonesia masih didominasi oleh toleransi permukaan, dimana orang menoleransi kehadiran kelompok lain tanpa sungguh-sungguh ingin membangun hidup bersama (Udar Rasa, Kompas, Juli 2024). Kita tahu Gus Dur adalah Presiden yang mencabut Inpres Nomor 14/1967 dan menggantinya dengan Keppres Nomor 6/2000 yang mengizinkan penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di tempat umum.
Tahun lalu saya hadir dalam perayaan Imlek bersama warga Cina Benteng di kota Tangerang. Maaf, saya gunakan istilah Cina, tanpa sedikitpun tujuan melecehkan atau merendahkan. Pada malam Imlek kemarin -- saya diundang oleh tetangga anak saya. Keluarga itu, sang suami Cina-Bangka dan istri Cina-Aceh, merayakan malam Imlek tanpa lampion, hio, kembang api, dan barongsai atau angpao. Sekedar acara keluargaan, makan-makan sederhana di pelataran dalam komplek perumahan mereka. Tuan rumah berkaos oblong sedang istrinya memakai housecoat alias daster, menerima kami dengan santai dan hangat. Suasananya sangat bersahabat, terasa sekali ketulusan sang sahibul bait.
Beruntung, saya sejak doeloe bergaul dengan warga keturunan Cina yang baik-baik. Kami berbaur sangat bebas dan terbuka, tidak ada jurang antara pri dan non- pri. Saya yang memang dididik tidak membedakan asal-usul orang, jadi ingat masa kecil sejak zaman komik Si Apiao, Put On dan Sie Djien Koei itu. Masa itu, saya sudah familiar dengan salam Gong Xie Fa Cai atau doeloe orang lebih suka menyebutnya Sin Tjia Kong Hie.
Lingkungan saya pun datang dari “kelas” berbeda. Kawan saya di SMP, Hok San berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Gang Bebek, Angke. Dia suka mengantuk di kelas dan selalu buru-buru pulang sekolah mengayuh sepeda reyotnya karena malam dia menjaga warung keluarga. Yang lain, Ho Shen, anak dokter yang di rumahpun berbahasa Belanda. Lulus SMA -- dia dikirim ayahnya ke Jerman dan tidak kembali lagi.
Sayangnya, “masa damai” itu tercoreng oleh peristiwa rasialis yang sampai kini masih diingat orang. Tidak mau mengusik luka lama, terpaksa saya ungkit fakta sejarah. Peristiwan 10 Mei 1963 di Bandung yang memicu kerusuhan anti-Tionghoa, merupakan lembaran hitam sejarah kita. Peristiwa rasialis ini menunjukkan bahwa sentimen anti Tionghoa dalam masyarakat rentan jadi kuda tunggangan pihak lain. Luka itu lama -- baru sembuh. Lalu ada lagi peristiwa serupa ketika pergantian penguasa di tahun 1998. Demokratisasi dan desentralisasi pasca-reformasi ternyata tidak memperkuat sentimen kebangsaan, tetapi justru membuka ruang bagi munculnya kembali sentimen-sentimen primordial antipluralisme. (Revitalisasi Kebangsaan dan Pluralisme, Kompas, 18 Agustus 2005). Makin terasa ada kesenjangan, warga keturunan dianggap sebagai golongan minoritas.
Sejak itu, merebaknya isu-isu SARA dalam beberapa kompetisi Pilkada menunjukan masih “seksi”nya isu-isu semacam itu untuk dikomodifikasikan dalam tiap kontestasi politik negeri ini. Isu ini juga merupakan refleksi dari masih kentalnya sentimen rasial (social prejudice) dalam masyarakat kita, yang juga bisa berkembang menjadi sentimen agama.
Penting kita ketahui bahwa sentimen rasialis dalam masyarakat nusantara bukanlah ‘sifat alamiah’ kepulauan ini, melainkan pantulan dari strukturasi ketimpangan sistem ekonomi dan politik yang berlaku di berbagai masa.
Kalau ditarik akarnya, Tionghoa di Indonesia terkenal peranannya sebagai minoritas pedagang yang kekuasaan ekonominya tidak disenangi oleh penduduk asli. Akibatnya masalah Tionghoa tidak terbatas pada bidang ekonomi tetapi meluas ke bidang budaya, sosial, dan politik (Pribumi, Minoritas Tionghoa, dan China, Leo Suryadinata, 2022).
Karena itu Cina, Tionghoa, atau kini Cina, baik yang totok maupun peranakan lebih dikaitkan pada tauke, cukong atau taipan yang banyak menguasai perekonomian kita. Padahal, tidak usah jauh-jauh di Tangerang saja kita menjumpai warga keturunan Cina yang hidup di bawah garis kemiskinan, berbaur dengan warga lokal, tinggal maupun berusaha. Konon di Singkawang, di Bagan Siapi-api, atau di utara Jawa banyak keturunan Cina yang menjadi petani atau nelayan. Sudah sulit membedakan mana yang pri atau non-pri.
Setahu saya saudara-saudara keturunan ini sangat kental rasa kedaerahannya. Doeloe di dekat rumah, ada kos-kosan anak-anak keturunan asal Semarang. Mereka berbahasa Jawa medok sekali. Teman yang orang Cina-Padang juga amat totok bahasanya. Begitu yang Cina-Medan, logatnya Medan banget. Saya yakin di antara mereka tidak sedikit pun terbersit perasaan bahwa mereka bukan asal Indonesia. Kakek neneknya mungkin berasal dari negeri leluhur di Tiongkok, tetapi mereka sejak lahir sampai besar menghirup udara dan menginjak tanah air Indonesia. Kita juga banyak mewarisi berbagai jenis makanan dan budaya, mulai dari kweetiau hingga kebaya encim, batik peranakan atau gambang kromong.
Terkait berbagai kerusuhan yang pernah terjadi, sedikit banyak saya merasakan kekhawatiran mereka. Beberapa teman demi masa depan anak-anak mereka memilih pindah dan kini bermukim di luar negeri. Ada yang di AS, Australia, atau Belanda. Teman istri saya memilih Swiss.
Saya peduli bagaimana perasaan mereka yang sudah merasa orang Indonesia, lahir dan batin. Indonesia adalah tanah tumpah darah mereka. Kasihan amat kalau mereka terus dibayang-bayangi kebencian, sementara seumur hidup nenek moyang mereka sudah menetap dan dikubur di sini.
Kita tidak usah menyangsikan kecintaan mereka pada Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan doeloe. Tidak kurang warga Tionghoa berkontribusi. Banyak tokoh-tokoh keturunan Cina yang ikut dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan). Banyak pula pengusaha dan filantropis yang membangun sekolah dan rumah sakit.
Di masa awal Orde Baru -- kita punya aktivis pejuang yang kritis pena maupun aksinya. Saya ingat pada Soe Hok Gie dan abangnya Arief Budiman. Ada lagi Yap Thiam Hien. Kesadaran nasionalisme mereka mungkin lebih tebal daripada kebanyakan kita-kita yang sering disebut pribumi ini.
Saya jadi ingat, Romo Magnis pernah bertanya: ”Apa yang membuat keanekaan etnik, budaya, ras dan agama yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara antara Sabang dan Merauke sampai menjadi satu negara?” (Sketsa, Kompas, 6 Oktober 2024). Arus peradaban global di Nusantara berproses melalui penjelajahan Samudera. Pada arus balik itu, nilai-nilai baru dilakukan internalisasi di bumi Nusantara yang berkeindonesiaan dengan masuknya budaya dan agama, baik dari India, Arab, Persia, Cina, maupun dari Eropa.
Sukurlah ketika minggu lalu berjalan-jalan di mall -- saya menjumpai banyak sekali warga keturunan Cina bersuka-cita dalam masih suasana Imlek. Mudah-mudahan tidak lagi ada rasa khawatir pada mereka dan saya. Perasaan yang bertolak belakang dengan kelakuan Sembilan Naga, terutama yang akhir-akhir ini diramaikan dalam isu pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Jangan akibat kelakuan para dedengkot itu, saudara-saudara kita keturunan Cina lainnya, ikut menderita.
*Pengamat Sosial dan Mantan Jurnalis Majalah Berita Tempo
Editor: Jufri Alkatiri