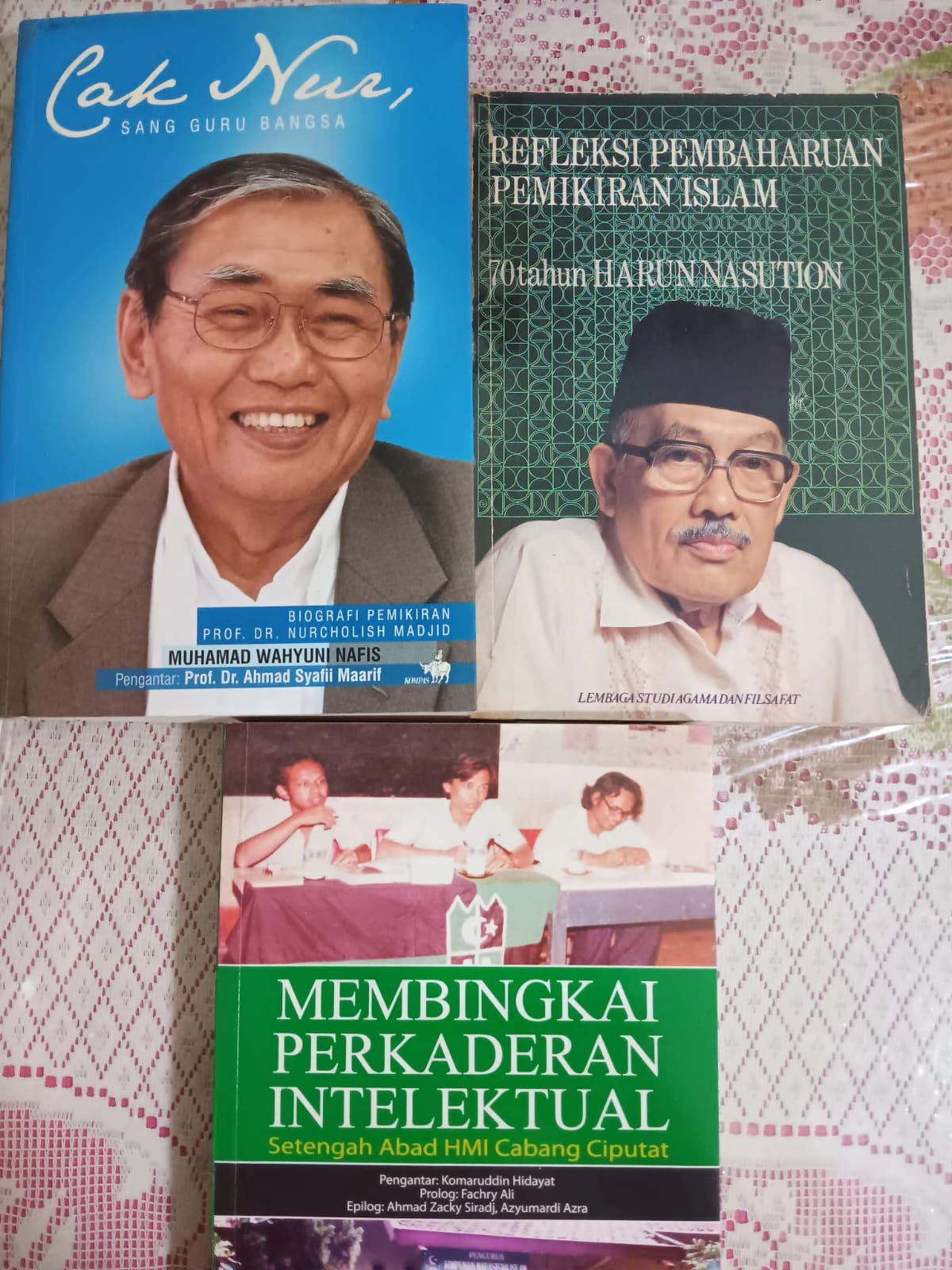Pesantren dan Nilai Kebersamaan (Foto: Times Jatim)
Oleh: Prof. Dr. Murodi al-Batawi, MA*
Pesantren yang ada di Indonesia, merupakan lembaga pendidikan Islam khas Indonesia -- merupakan lembaga pendidikan tertua di tanah air, karena Lembaga tersebut berkembang dari sistem pendidikan Hindu-Budha di daerah Perdikan, suatu daerah yang diberikan oleh kerajaan Majapahit, misalnya, yang dibebaskan dari berbagai pungutan, termasuk pungutan pajak.
Daerah tersebut dihuni oleh para kaum cendekia dan para Mpu tempat bertanya para raja, tentang banyak hal. Lama kelamaan, terutama setelah agama Islam masuk dan berkembang, lembaga semacam ini menjadi tempat pendidikan para pelajar, yang disebut Santri. Pesantren pada awalnya tidak menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Mereka hanya datang untuk berkunjung dan belajar ilmu agama kepada para Kyai. Tetapi lama kelamaan, banyak orang datang dari luar daerah untuk mencari ilmu, dan mereka memerlukan tempat tinggal. Karena begitu besarnya minat mereka untuk belajar dan mencari ilmu, khususnya ilmu agama Islam, akhirnya ada di antara mereka yang membangun pondokan tersendiri dengan usaha dan modal sendiri.
Semakin lama kian banyak yang berdatangan dari luar daerah ke pesantren tersebut, dan mereka memerlukan tempat untuk mondok, akhirnya pesantren lewat Kyai atau Ajengan, menyediakan tempat tinggal berupa Pondok atau Kobong akhirnya di depan kata pesantren, diberi kata Pondok, maka lembaga pendidikan tradisional ini menjadi Pondok Pesantren.
Pesantren pertama, sebagai lembaga pendidikan dan Tafaqquh fi al-Dien, adalah pesantren yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim -- salah seorang wali dari Sembilan Wali atau Walisongo pada abad ke-15 M. Pada awalnya, pesantren pada waktu itu hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Para santri dididik oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Setelah selesai mondok, mereka kembali ke daerah masing-masing dan mendirikan pondok pesantren sebagai media pendidikan dan penyebaran Islam. Salah satu tokoh yang dianggap berhasil memiliki pengetahuan dan mendirikan pesantren pertama di Jawa Timur adalah Sunan Ampel, salah seorang wali dari Walisongo. Dia mendirikan Pesantren pertama kali di Kembang Kuning, Surabaya. Saat itu, hanya ada tiga orang santri yang belajar di pesantren Kembang Kuning. Wiryo Suroyo, Abu Khurairah, dan Kyai Bangkuning.
Kemudian, Sunan Ampel, mendirikan Pesantren di Ampel Denta. Usahanya mendirikan pesantren ini cukup berhasil sebagai media penyebaran Islam di seluruh Jawa Timur. Selanjutnya, para santri dan alumni Pesantren Ampel Denta ini -- mendirikan pesantren-pesantren baru di berbagai tempat, seperti di Giri, Tuban, Lamongan, dan Demak. Keberhasilannya ini membuat dia diizinkan untuk membuka lembaga pendidikan Islam baru di beberapa tempat.
Di antara salah seorang santri Ampel Denta adalah Raden Fatah -- dia mempergiat usaha pendidikan dan pengajaran Islam secara teratur. Maka pada 1476 M, dia membentuk organisasi bernama Bhayangkara Islah. Ini adalah organisasi pendidikan Islam pertama yang dibentuk di Nusantara.
Kemudian, setelah berdirinya Kerajaan Islam Demak pada 1500 M, organisasi Bhayangkara Islah mendirikan masjid di setiap daerah strategis sebagai tempat pendidikan Islam, seperti pondok Pesantren yang dipimpin oleh seorang Badal.
Pada masa pemerintahan Kesultanan Islam Demak (1500-1546 M), pendidikan Masjid dan Pesantren mendapat bantuan dari pemerintah. Kebijakan ini terus dilanjutkan setelah perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang dan seterusnya.
Santri dan Kebersamaan
Para pencari ilmu di pondok pesantren seting disebut sebagai santri. Para santri ini, biasanya datang dari berbagai daerah untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan agama Islam. Mereka mempelajari kitab-kitab dasar pengetahuan agama hingga kitab tingkat tinggi, yang hanya bisa dipelajari oleh para santri senior dan sudah menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut. Mereka inilah yang sudah dipersiapkan untuk menjadi Kyai atau pimpinan pondok pesantren di daerah asalnya.
Para santri ini, saat hendak mengaji kitab Kuning, mereka mengikuti tiga metode, sotogan, wetonan, dan bandongan. Metode sotogan, mereka datang ke Kyai dengan membawa kitab dan menyotog atau menyodorkan kitab untuk dibaca dan dipelajari di depan Kyai. Metode Wetonan, merupakan cara mengajar yang ditentukkan waktunya oleh sang Kyai; seperti mengaji kitab setelah habis shalat wajib atau terserah kesediaan waktu sang Kyai. Dan Metode Bangdongan berbentuk halaqah, para satri yang datang mengaji biasanya membawa satu kitab yang akan diajarkan oleh sang Kyai. Mereka duduk melingkar, di tengah lingkaran duduk sang Kyai mengajarkan satu kitab, sementara para santri menyimak secara bersama-sama. Di situlah terlihat ada kebersamaan antara para santri. Mereka sangat menghormati dan menghargai sang Kyai. Bahkan jika mau bertemu dan mencium tangan sang Kyai, mereka harus antre sambil membungkuk.
Selain ada perasaan kebersamaan pada saat mengaji, para santri juga memelihara nilai kebersamaan pada saat lain -- seperti pada saat menuju masjid untuk shalat berjama’ah, saat makan, saat bermain dan lain sebagainya. Nilai kebersamaan ini mereka jaga hingga mereka menjadi alumni kemudian membentuk organisasi alumni dengan rencana program yang mereka susun. (*)
*Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pengamat Sosial Kemasyarakatan
Editor: Jufri Alkatiri