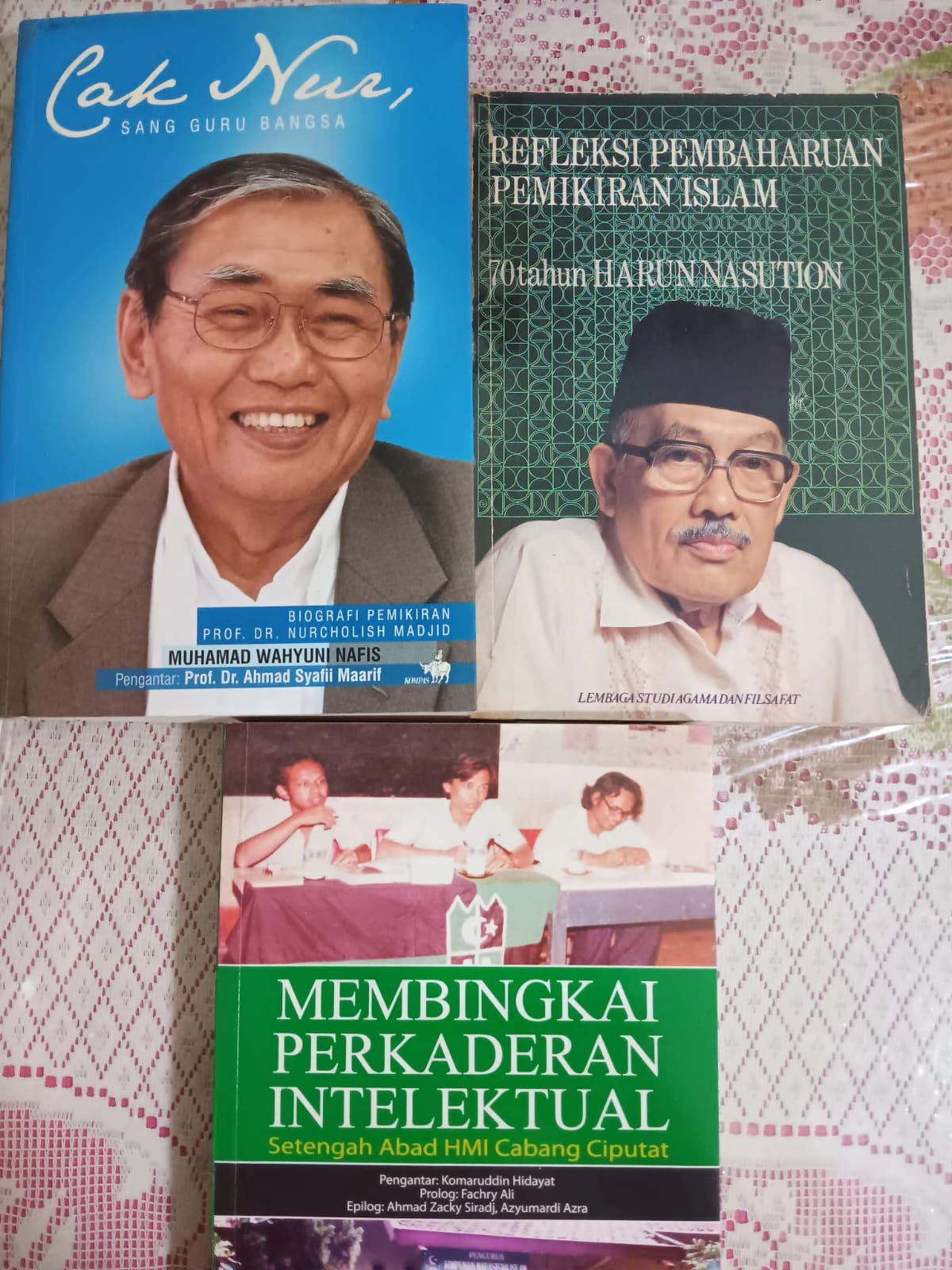Foto : Universitas Erlangga (Google.com)
Dalam Era Digital -- melihat kebenaran, mengalami pergeseran makna mengikuti situasi zaman yang berkembang, saat sekarang ini -- telah memasuki zaman yang disebut dengan era post-truth atau zaman pasca-kebenaran. Di antara pembaca mungkin saja akan bertanya-tanya kenapa ada era setelah kebenaran? padahal jika merujuk pada hakikatnya bahwa kebenaran adalah mutlak, tetap, pasti, dan tidak berubah-ubah. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Penyebab utamanya adalah terjadinya perubahan landasan filosofis -- platform media yang pada wujud riilnya berbentuk konvergensi ke dalam jenis media baru (new media). Berbagai fasilitas dan fitur yang disediakan platform media baru memungkinkan munculnya banyak penafsir kebenaran. Dengan kata lain, kemunculan media baru telah mengubah paradigma lama (media arus utama) mengenai penafsiran kebenaran. Ini karena tidak ada lagi prosedur yang digunakan untuk menentukan makna tentang kebenaran.
Semua hanya dikonstruksi melalui pandangan seseorang siapa saja hanya dengan dianggap bermuatan unsur kebenaran. Jadi tejadi pergeseran dan menjadi berbeda bagaimana memaknai kebenaran; kebenaran ilmu jika teori sains rasional dan terdapat bukti empirisnya, maka teori itu benar. Ukuran kebenaran pengetahuan filsafat yaitu logis. Bila teori filsafat logis, maka teori tersebut benar. Sedangkan kebenaran pengetahuan mistik diukur dengan berbagai ukuran. Bila pengetahuan berasal dari Tuhan, maka ukuran kebenarannya adalah teks dari Tuhan (wahyu).
Kebenaran menjadi tidak obyektif lagi, ketika memahami persoalan “dunia subjektif manusia” maka dengan perspektif subjektif digunakan dalam memandang kebenaran, ukurannya kebenaran adalah likebilitas, viral dan banyaknya folower.
Penggunaan kata post-truth memang tidak secara tiba-tiba. Diawali pada fase ketika terjadinya sebuah praktik manipulasi kebenaran secara besar-besaran. Peristiwa-peristiwa yang menyertai kemunculan era post-truth ini seperti; manipulasi fakta yang dilakukan mantan presiden Amerika Serikat George Bush atas tuduhan dimiliknya senjata pemusnah massal Irak hingga berbuntut terjadinya serbuan pasukan Amerika ke Irak. Berikutnya, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, dan kemenangan presiden Trump dalam pemilihan presiden. (Lee Mc Intyre, 2018).
Peristiwa-peristiwa ini memiliki hubungan tegas yang menunjukkan bahwa dibalik itu semua ada alasan pembenar bagi pihak yang tengah mengaduk-aduk opini publik untuk menyalurkan hasrat kekuasaannya dengan memanipulasi kebenaran melalui teknik tertentu.
Praktik post-truth juga dapat dilakukan dengan mengetengahkan kebohongan, karena bohong maka tidak ada fakta yang mendasarinya. Namun di era post-truth, kebohongan dapat meluncur deras ke seluruh jaringan media. Para pengguna media sadar bahwa yang diperlukan adalah munculnya penafsiran terhadap kebenaran yang bersumber dari perasaan atau emosi.
Menurut J A Liorente, fenomena seperti ini menandakan bahwa iklim sosial politik mengabaikan objektivitas dan rasionalitas dengan membiarkan emosi/hasrat memihak pada keyakinan meski fakta memperlihatkan hal yang berbeda. Terjadi dengan era ini adalah keyakinan pribadi lebih dikedepankan daripada logika dan fakta dalam ruang publik (Wera, 2020).
Subyektif “citra diri” seseorang betul-betul dimainkan, dimanfaatkan dan diwadahi oleh raksasa internet melalui media visual, audio visual dan juga media sosial yang mereka ciptakan seperti Google, Youtube, Facebook, Twitter, Line, Whatapp, IG, TikTok, dan lain-lain yang semakin mengukuhkan imajinasi diri seseorang untuk eksis, merayakan narsisme bahkan pembenaran.
Peran kekuatan media mempengaruhi politik pencitraan, bagaimana media menyusun agenda dan membangun citra publik. Media menjadi pemain utama dalam menentukan isu-isu politik dipresentasikan dan dapat diterima oleh publik.
Anwar Rosyid Soediro/ Pemerhati Filsafat dan Pengamat Sosial
Editor: Jufri Alkatiri