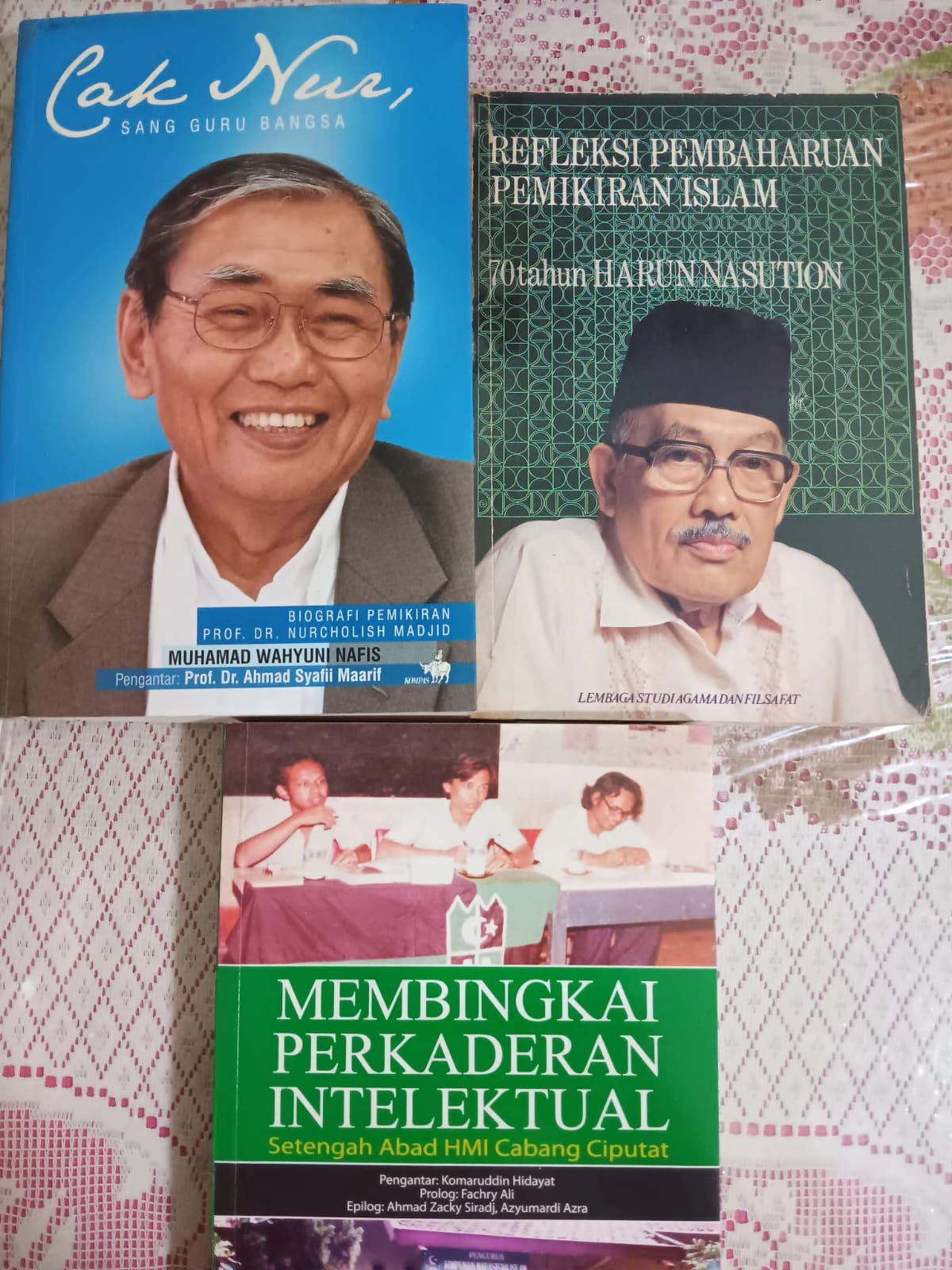Ilustrasi Renville Almatsier
Oleh : Renville Almatsier*
“Pikniknya kurang jauh…”. Ungkapan yang sering kita jumpai di media sosial itu, baru saya ketahui asal usulnya ketika membaca tulisan Alissa Wahid dalam salah satu media. Kalimat ini ditujukan untuk mengomentari individu yang berfikir sempit, terutama terhadap kelompok yang berbeda. Guyonan itu menekankan bahwa kurang piknik menyebabkan kita kurang bergaul dan kurang pengalaman berinteraksi dengan kultur yang beragam, lalu berujung pada pikiran hitam-putih, us versus them. Hal ini sering kita jumpai, baik dalam pergaulan fisik dan nyata maupun dalam grup-grup pertemanan di media sosial. Rasanya cocok kalau saya ungkit lagi hal ini pada saat kita merayakan Sumpah Pemuda, 28 Oktober hari ini.
Migrasi dan mobilitas membuat masyarakat semakin beragam baik dari pedesaan menuju perkotaan. Karena itu perjumpaan lintas iman tak bisa dihindari. Mereka yang dibesarkan di Jakarta, umumnya sudah terbiasa dengan hal ini. “Saya lahir di daerah, di luar Jawa, tetapi besar di Jakarta”, begitu jawab saya kalau ditanya. Saya menghormati adat istiadat orangtua. Saya anak Jakarta.
Apa sih definisi anak Jakarta ? Buat saya, kami adalah anak-anak yang lahir dan atau besar di Jakarta dari orangtua pendatang yang kemudian dalam berinteraksi dengan sesama menghasilkan sebuah subkultur unik dengan kebiasaan logat bicara, kerangka berfikir, dan bahkan mungkin trauma serupa.
Tentu kehidupan kota metropolitan, sebagai melting pot banyak negatifnya. Tetapi dari sisi positifnya, ritme ibu kota membuat kami cenderung tangkas dan pragmatis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.
Saya biasa bertetangga dengan berbagai orang-orang dari berbagai suku dan agama. Sehingga sudah biasa mendengar ceramah, orasi, atau kebaktian umat agama lain. Kawan-kawan saya di masa kecil, sering ikut mendengar saya belajar mengaji. Kami tidak pernah merasa terganggu dengan suara beduk atau pengajian lewat pelantang suara. Dari kecil kami sudah hidup penuh toleransi. Agaknya kami terbawa oleh masyarakat asli Betawi yang memang “dari sononya” sudah penuh toleransi. Sebaliknya, perbedaan itu sangat peka bagi orang yang datang belakangan dan berkecimpung hidup dalam “kuali” Jakarta. Dalam pergaulan di Jakarta, mereka sering baru melek, menganggap Jakarta serba terbaik. Tetapi sebaliknya, mereka juga sering terlalu sensitif terhadap perbedaan. Masih terbuai oleh “sangkar emas” masa lalunya. Mereka ini yang disebut “kurang piknik”, belum terbuka mata dan pikirannya bahwa mereka ada di kota metropolitan. Di luar yang beremigrasi ke ibu kota sesudah dewasa, ada berbagai jejak primordial berbeda dalam “orang Jakarta”. Uniknya, banyak dari mereka yang menabung hidup seterusnya di Jakarta, bukan di kampung orangtuanya.
Dalam pertemanan, saya kagum pada rekan-rekan yang besar di daerah. Mereka umumnya santun dan kuat didikan agamanya. Melalui survei kecil-kecilan di lingkungan pergaulan waktu muda, saya menilai mereka lebih banyak aktif menjadi anggota perkumpulan mahasiswa kedaerahan maupun yang berbasis agama. Kadang-kadang mereka inilah yang terasa berfikiran sempit tadi. Belum biasa menerima perbedaan. Baik perbedaan dalam lintas iman, perbedaan sudut pandang, termasuk dunia politik. Susahnya sikap itu terbawa sampai tua. Kini, hal ini banyak terjadi di kelompok-kelompok grup pertemanan, baik teman lama ex SMA, teman masa kuliah, maupun teman sesama pensiunan.
Sudah sering kita dengar petuah bahwa lahir sebagai bangsa Indonesia, kita ditakdirkan lahir dari ras, suku, agama yang berbeda-beda. Justru kita bersyukur kita dipersatukan menjadi satu bangsa, Indonesia.
Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu generasi yang sempit pemikirannya dan “kurang piknik” akan berangsur hilang dan berganti dengan generasi baru Indonesia yang fresh, benar-benar bersatu. Boleh berbeda pikiran, bahkan ideologi tetapi kita tetap satu Nusa, satu Bangsa, dan satu Bahasa.
*Pengamat Sosial dan Dosen di Salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta
Editor : Jufri Alkatiri