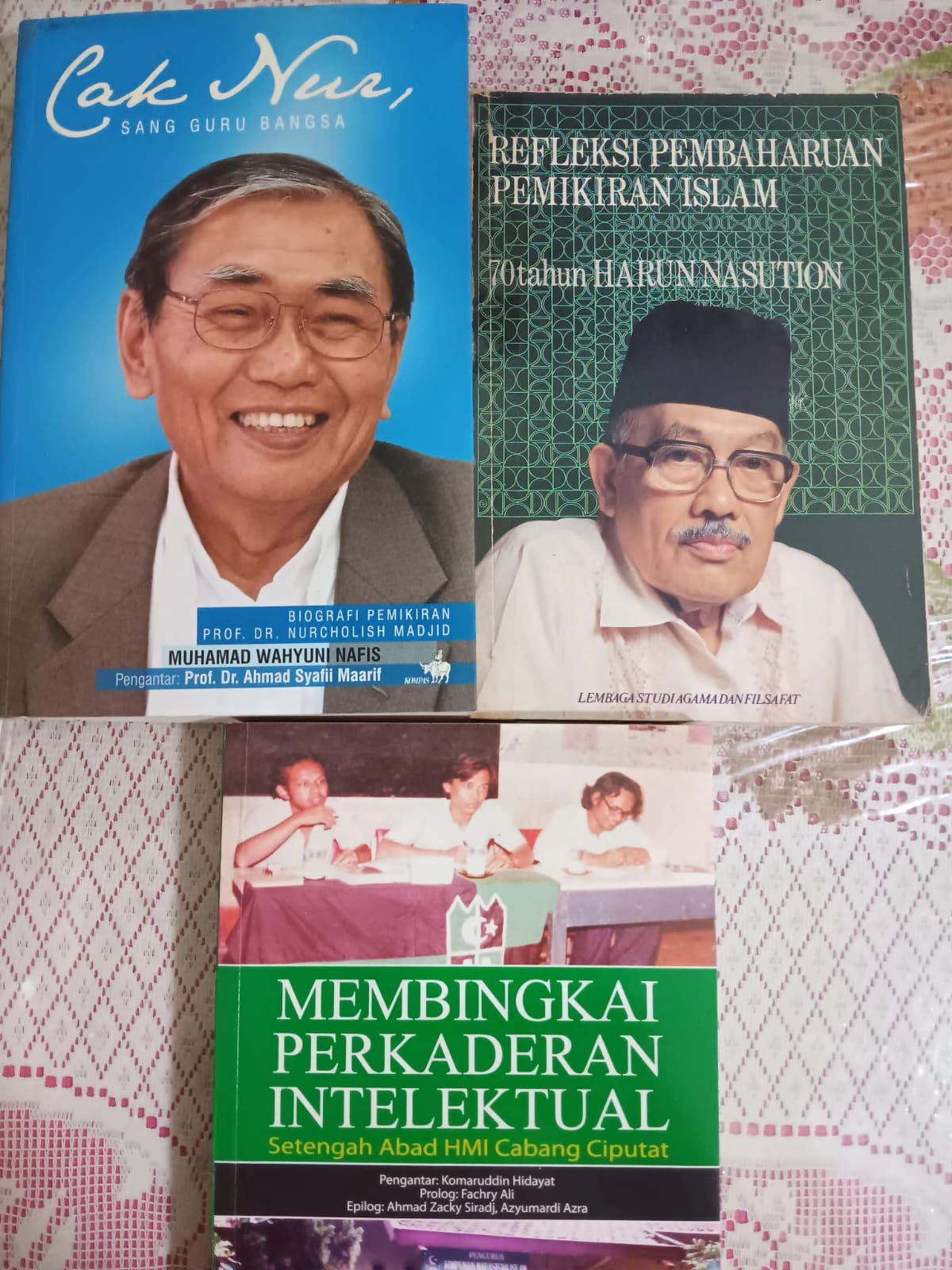Joko Widodo, Presiden RI tahun 2014-2024 (Foto: Google.com)
Oleh : Renville Almatsier*
Beberapa waktu lalu -- menjelang pergantian pemerintahan, media sosial diramaikan oleh derasnya pemberitaan mengenai jejak Presiden Joko Widodo yang lengser. Berbagai sanjung pujian menggempur media sosial X atau Twitter. Tidak itu saja, koran-koran besar seperti Kompas, juga menyediakan berlembar halamannya untuk advertorial. Banyak akun anonim yang mengapresiasi Jokowi karena dianggap berhasil membawa kemajuan bagi Indonesia.Tentu saja kita, netizen merasa risih. What’s going on ? Ada apa ini ?
Beberapa waktu sebelum gejala ini muncul, kondisi amat berbeda. Di awal pemerintahan Jokowi, banyak pihak optimistis demokrasi bakal lebih baik. Terutama ketika Jokowi menggelorakan “revolusi mental”, yang kemudian menghilang tanpa bekas itu. Tetapi, pemberitaan umum tentang Jokowi akhir-akhir ini berbeda lagi nuansanya dengan pada masa bulan madu di tahun 2014. Penyebabnya, terutama terkait suasana menjelang dan sesudah Pilpres 2024. Puncaknya berawal dari kasus putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan presiden-wakil presiden sehingga publik kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Kritik, bahkan cercaan bermunculan.
Inilah yang agaknya membuat Pemerintah cq. Kominfo atau Kantor Kepresidenan atau tim-tim relawan pendukung, grasa-grusu mengangkat keberhasilan pemerintah. Bertubi-tubi muncul tulisan yang mengungkit ulang semua yang sudah dikerjakan Jokowi seolah-olah takut jasanya akan dilupakan orang. Apa yang sudah cantik, dipoles agar lebih cantik lagi. Agaknya pemerintah merasa “kurang pe-de”.
Hiruk-pikuk di ranah publik itu diramaikan oleh influencer, buzzer, doxing, narasi populis, trolling, dan lainnya yang akhirnya membuat partisipasi publik dipertanyakan kejernihannya dan dicurigai sebagai mesin penyebar propaganda. Suasana makin ramai, ketika Majalah TEMPO edisi 13 Oktober 2024 keluar dengan cover story mengenai “keramaian” ini. Dengan judul “Operasi Memoles Citra”, sebagaimana biasanya, majalah berita mingguan itu tampil dengan gambar kulit menggelitik, berupa cartoon menggambarkan “Jokowi” sedang dihias oleh dirinya sendiri.
Liputan TEMPO itu berkebalikan dengan nada tulisan-tulisan para influencer tadi, dan bahkan membongkar asal-usul proses semua yang memenuhi media sosial itu. Belakangan, muncul penjelasan TEMPO bahwa redaksi majalah itu menolak tawaran pihak Istana untuk membuat liputan khusus tentang keberhasilan sang presiden selama 10 tahun, dengan berbagai persyaratan. Mulai terkuak sedikit.
Kampanye citra-baik Jokowi di media sosial itu konon turut disokong oleh akun-akun milik pemerintah serta relawan. Beberapa ditjen di bawah Kementerian Keuangan misalnya, cukup gesit mengangkat kinerja pemerintah di Instagram. Menyebarkan kebijakan atau keberhasilan sebuah lembaga kepada publik dan stake-holder lainnya, pada hakekatnya adalah hal biasa. Itulah tugas mereka di public relations.
Kominfo rupanya juga mengontak tim bisnis TEMPO. Kalau lembaga itu menawarkan iklan berupa berita berbayar yang biasa dikenal sebagai pariwara, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi rupanya pihak pemerintah yang bersedia menyediakan dana besar, ingin mengkampanyekan keberhasilan Jokowi dalam bentuk pemberitaan dengan beberapa instruksi dan larangan. Nah, kalau ini, tunggu dulu.
Di kalangan pers dikenal adanya batasan yang sangat ketat antara pemberitaan dan iklan. Itu yang disebut “garis api”, yang selalu menjadi hal krusial dalam kode etik kewartawanan. Dari sini pula berawal kasus “amplop wartawan” yang sudah lama kita kenal.
Karena bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, tentu saja TEMPO menolak tawaran itu Sebaliknya, Redaksi TEMPO malah menyiapkan liputan tentang operasi ”memoles” Jokowi. Maka terkuaklah semuanya.
Kembali pada “kampanye” keberhasilan Jokowi, berbagai tulisan itu memang bernada menunjukkan prestasi presiden. Tentu wartawan yang baik tidak begitu saja mau menerima informasi yang disodorkan nara sumber, dalam hal ini, agen-agen pemerintah itu. Disiplin, membuat wartawan harus bisa menyaring desas-desus, gosip, manipulasi, kekeliruan guna mendapat informasi akurat. Verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan propaganda, pariwara infotainment, hiburan, fiksi, atau seni. Jurnalisme hendaknya digerakkan oleh verifikasi berdasarkan bukti faktual dan tindakan. Untuk itu perlu pembuktian dengan fakta.
Urusan pembaca, serahkan kepada pembaca. Sebagai konsumen, pembaca tentu bisa memilih, mana berita yang layak dipercaya, mana yang bohong. Kecuali, tentu pembaca-pembaca bodoh yang disasar oleh inisiator kampanye. Siapa penyampai berita yang lebih mendekati fakta dan jujur, siapa pula yang menebar kebohongan, waktu akan membuktikan.
Karena itu, untuk mengimbang ramainya komunikasi subjektif, publik memerlukan kehadiran media konvensional yang dijalankan secara profesional. Kalau apa yang dijelaskan TEMPO itu benar, ya begitulah seharusnya jurnalisme menjaga citranya. Pihak pemerintah, sebetulnya tidak perlu panik. Media yang kredibel pasti akan jujur dan objektif. Kalau prestasi itu nyata, kenapa harus ragu? Contohnya, Kompas cukup fair membeberkan hasil-hasil pembangunan berdasarkan survey bagian litbangnya (Kompas, 20 Juni 2024).
* Pengamat Sosial dan Dosen di Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta
Editor : Jufri Alkatiri