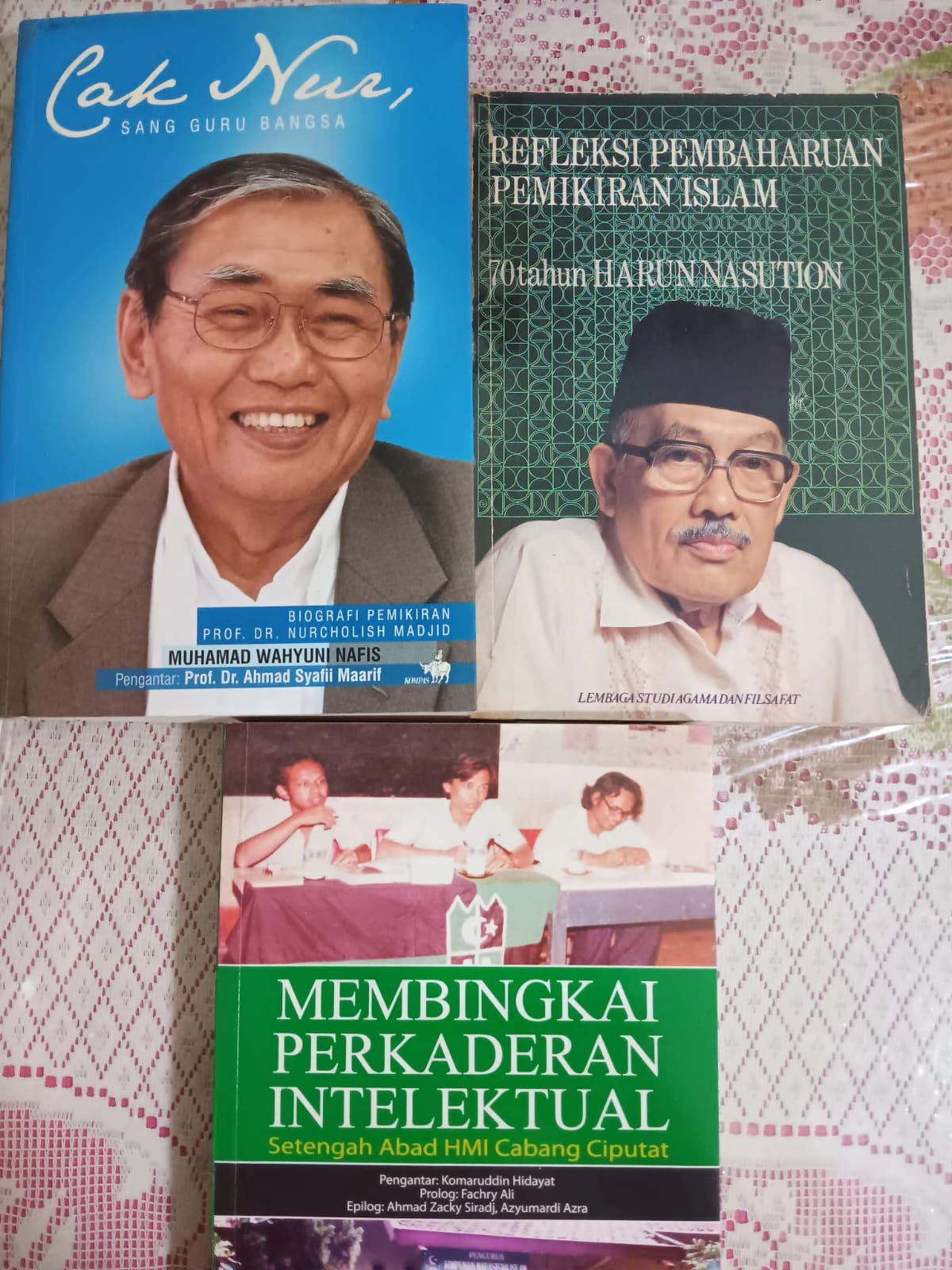Berakhirnya atau game over penjajahan asing di bumi Indonesia -- bukan berarti media pers dapat menikmati kebebasan dari represi fisik, mental, maupun intelektual. Karakater kekuasaan negara yang dihadapi jelas berbeda, tetapi secara substansial tidak berubah. Seusai demokrasi perlementer, Orde Lama di bawah rezim Soekarno yang berkuasa singkat, tapi pers dipaksa sebagai media organik dijadikan kekuatan politik atau institusi negara sebagai ciri totalitarian negara yang ingin diwujudkan presiden.
Selanjutnya selama puluhan tahun Pasca-Soekarno, media pers dibayangi kekuasaan fasis-militeristik Orde Baru di bawah Soeharto, Jika sekarang ada yang merindukan kembalinya orde tersebut, tentulah bukan represinya atau bentuk kekuatan lainnya. Pada masa Presiden Soeharto, media pers harus lihai berkelit dari tekanan dan ancaman, jika tidak ingin dibredel atau dihentikan terbit dengan mencabut Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP.
Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia tentang kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai kebebasan sosial politik yang mengacu pada suatu bangsa atau rakyat. Terbentuknya demokrasi moderen dimana perwakilan rakyat membatasi dan mengontrol kekuasaan pemimpin, karena timbulnya kesadaran bahwa yang berdaulat bukanlah pemimpin saja, melainkan rakyat. Seperti dalam semboyan kebebasan, persamaan, persaudaraan.(Masykuroh and Jannah 2018). Kebebasan pers tetap relevan untuk dibicarakan – karena nilai kebebasan tersebut menjadi landasan bagi kehadiran media pers, apakah itu surat kabar, media penyiaran (televisi, radio, maupun media online), maupun portal berita daring.
Kebebasan pers dan demokrasi memiliki jalinan yang saling berhubungan. Jika demokrasi mengalami kemunduran tentu akan memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media. Banyak negara di dunia, menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis tetapi mempasung kebebasan pers. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang menganut paham negara demokrasi namun sekaligus memberi kebebasan kepada pers.
Indonesia termasuk negara yang berpaham demokratis dan meliberalisasikan pers. Setidaknya paham ini sudah dinikmati sejak Era Reformasi atau setelah terbitnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Nelson Mandela pernah mengeluarkan kata-kata bijak tentang pers: Pers kritis, independent, dan investigatif adalah sumber kehidupan demokrasi. Pers harus bebas dari gangguan negara. Pers harus memiliki kekuatan ekonomi untuk bertahan. Itu harus memiliki independensi yang cukup dari kepentingan pribadi untuk berani dan bertanya tanpa rasa takut. Pers harus menikmati perlindungan konstitusi sehingga dapat melindungi hak-hak manusia sebagai warga negara.
Dalam ilmu filsafat kebebasan didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk menentukan individu itu sendiri, bisa diartikan sebagai kebebasan yang lebih bermakna positif, dan lebih kepada konsekuensi dari potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Kebebasan yang berdasarkan dari segi individu mempunyai kesewenang-wenangan, yaitu kebebasan yang diartikan sebagai segala kewajiban dan batasan, atau kesempatan untuk berbuat sesuka hati. Contoh makna ini digunakan ketika berbicara tentang pergaulan bebas. Bebas berlaku terlepas dari peraturan atau aturan. Kebebasan dalam konteks ini adalah suasana toleransi. Makna ini juga menjadi akar dari liberalisme abad ke-19. Menurut penganut liberalisme, free enterprise adalah bisnis sebagai perusahaan yang bebas, tanpa aturan, ketentuan, atau campur tangan pihak luar, terutama pemerintah.
Friedrich Schiller, seorang penyair Jerman pada akhir abad ke-18, mengatakan manusia diciptakan bebas, dan meskipun dilahirkan dalam keadaan terbelenggu – namun dia tetap bebas. Masalah-masalah yang didapatkan dari kebebasan berpendapat dapat bernilai positif dan juga negatif. Kebebasan positif adalah tersedianya kesempatan untuk menjadi penentu atas kehidupan dan untuk membuatnya menjadi lebih bermakna dan signifikan. Kebebasan positif adalah poros konseptual berkembangnya tanggung jawab sosial. Implikasi hukum dari kebebasan positif dikembangkan oleh Zechariah Chafee dalam karya dua jilidnya, Government and Mass Communication (1947). Kebebasan negatif adalah bebas dari hambatan dan diperintah oleh orang lain, jadi kebebasan negatif ini adalah kebebasan yang menyatakan definisi kebebasan yang digunakan liberalisme klasik, yaitu kebebasan negatif berarti tidak adanya batasan. Kebebasan berekspresi berkaitan erat dengan pesan yang disampaikan dan tanggung jawab setiap individu, seringkali seseorang ingin menampilkan dirinya yang merasa penting sehingga, sehingga terbesit dipikirannya untuk menampilkan karya dan ide melalui media massa.
Profesi sebagai seorang jurnalis adalah profesi menyediakan informasi untuk masyarakat atau publik. Loyalitas pertama jurnalisme adalah pada masyarakat, karena itu jurnalis harus menjaga independensi sumber berita. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, jurnalis harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan, Selain itu, jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional serta para praktisi diperbolehkan mengikuti hati nurani. Sembilan Elemen Jurnalisme tersebut ada dalam 11 pasal dalam Kode Etik Junalisti (KEJ).
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers – pers diartikan sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, termasuk kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik, menggunakan berbagai media seperti cetak, elektronik, dan saluran komunikasi lainnya (Kusmadi & Samsuri, 2010). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pers, menyebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers mempunyai kebebasan berekspresi untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Namun kebebasan ini tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas untuk melanggar hak orang lain. Ada pula pasal yang mengatur kebebasan tersebut. Salah satu pasal dalam Kode Etik Jurnalistik.
Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 mengenai Kode Etik Jurnalistik yang berisi untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan yang ada di seluruh Indonesia perlu berlandaskan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan intergritas, kredibilitas, serta profesionalisme. Wartawan Indonesia harus menaati Kode Etik Jurnalistik.
Jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas profesi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Jurnalis berpotensi besar untuk dapat mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya melalui media massa. Tidak heran jika media massa saat ini seolah-olah menjadi candu akan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi media massa. Berbicara mengenai media massa maka tak lepas dari kaitannya dengan dunia pers di mana jurnalistik merupakan aktivitasnya.
Adapun tanggung jawab jurnalis berdasarkan Kode Etik Jurnalis sebagaimana dijelaskan Bekti Nugroho dan Samsuri (2013) bahwa: 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 2. Wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan pornografi. 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Wartawan Indoneisa tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7.Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi, latar belakang, dan off record sesuai dengan kesepakatan. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminatif terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita keliru, dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak korelasi secara proporsional. Berdasarkan penjelasan mengenai Kode Etik Jurnalistik sehingga dapat dipahami bahwa seorang jurnalis memiliki nilai-nilai tanggung jawab yang harus dijaga dalam sistem kerjanya dengan profesi sebagai seorang jurnalis.
Etika menjadi pegangan pokok oleh jurnalis karena dipandang sebagai sarana orientasi bagi manusia untuk menjawab suatu pertanyaan fundamental.7 Dalam situasi ini, etika mau membantu kita dalam mencari nilai dan orientasi menyangkut tujuan dan pilihan tindakan agar kita dapat mengerti setiap keputusan tindakan yang kita ambil dan mampu bertanggungjawab terhadap keputusan itu.
Seorang jurnalis dituntut untuk menghormati nilai-nilai dan etika yang berlaku karena kaedah etika diperlukan dalam menghadapi suatu kasus yang tidak etis seperti korupsi. Keputusan etis dalam profesi jurnalis investigasi sebenarnya telah dihadapkan pilihan etika, terutama saat berada dalam situasi diantara pilihan-pilihan sulit yang harus diambil ketika menghadapi kasus yang merugikan kepentingan publik, yakni apakah akan diberitakan atau sebaliknya dengan konsekuensi yang akhirnya kembali pada moral dan prinsip jurnalis tersebut.
Seorang jurnalis harus menjaga kredibilitas untuk meraih kepercayaan publik atau masyarakat. Jika seorang jurnalis tidak mempunyai integritas dan kredibilitas yang baik, maka publik atau masyarakat banyak meragukan karya-karya jurnalisme yang dibuat.
Pentingnya menjaga kredibilitas sebagai seorang jurnalis secara langsung terkait dengan kegiatan jurnalisme. Kegiatan jurnalisme melibatkan penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Integritas dan kredibilitas yang baik merupakan aspek kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik. (Hjelm: 2019) Jika seorang jurnalis kehilangan kredibilitasnya, hal ini dapat menyebabkan publik meragukan informasi yang disampaikan, pada gilirannya dapat merusak citra profesi jurnalis dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media, maka menjaga kredibilitas dan integritas merupakan bagian integral dari kegiatan jurnalisme yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dampak buruk yang akan terjadi jika seorang jurnalis membuat karya tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi jurnalisme. Salah satu dampak buruk tersebut adalah informasi yang disampaikan menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya, maka kegiatan jurnalisme sangat terkait dengan etika deontologi etis dan Kode Etik Jurnalistik, yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh jurnalis akurat, objektif, dan dapat dipercaya.
Pentingnya memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi etis dalam kegiatan jurnalisme. Hal ini menekankan bahwa kegiatan jurnalisme sangat terkait dengan etika deontology etis dan Kode Etik Jurnalistik, yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan jurnalis secara akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, jurnalis diharapkan dapat menghindari dampak buruk seperti informasi yang menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya, sehingga dapat menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi jurnalisme menjadi pedoman yang penting dalam menjalankan kegiatan jurnalisme secara etis dan bertanggung jawab.
Profesionalisme dalam Jurnalis berfungsi sebagai bertugas menjaga arus informasi menuju khalayak (Gatekeeper) bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat oleh jurnalis. Ketika media tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka informasi yang disampaikan dapat menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Oleh karena itu, kegiatan jurnalisme sangat terkait dengan etika deontologi jurnalisme dan kode etik jurnalistik, yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh jurnalis akurat, objektif, dan dapat dipercaya.
Seorang jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan hukum pers, agar tidak terjebak dalam pelanggaran etika Jurnalistik. Hal ini terkait dengan kebutuhan seorang jurnalis akan kepercayaan dari publik atau masyarakat. Dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, seorang jurnalis dapat memastikan bahwa konten yang dibuatnya dapat bermanfaat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak menjadi sia-sia. Penekanan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dalam jurnalisme yang menekankan pentingnya kejujuran, akurasi, dan kewajiban jurnalis untuk melayani kepentingan publik (Mufid, 2017).
Menerapkan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik merupakan bagian integral dari praktik jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis. Dalam praktik jurnalisme, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik membantu menjaga integritas profesi, memastikan akurasi dan kejujuran dalam penyampaian informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap media.
Profesi jurnalis bukan yang menghasilkan uang yang besar dan melimpah, tetapi lebih ke dalam tujuan jurnalis adalah untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi mengenai informasi yang beredar di masyarkat. Ia juga menyebutkan bahwa jika masyarakat di sajikan dengan data yang valid, maka mereka akan otomatis tertarik dengan sendirinya ke konten kita (jurnalis), sehingga ini akan mengakibatkan engagement yang tinggi dan meningkat kepada khalayak public atau masyarakat.
Prinsip-prinsip jurnalisme dikenal sebagai sembilan elemen jurnalistik yang fokus pada kebenaran (fact) dan loyalitas kepada masyarakat. Jurnalis diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Namun, seorang jurnalis juga seringkali menemukan tantangan yang tidak ringan, dimana ada tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika jurnalistik. Prinsip-prinsip jurnalistik umumnya mencakup nilai-nilai seperti kebenaran, objektivitas, kemerdekaan, dan keadilan. Prinsip-prinsip jurnalis tersebut adalah kebenaran (Fact). Jurnalis diharapkan memberikan informasi yang akurat dan berkomitmen untuk menyampaikan berita yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat. Tantangan dalam Dunia Jurnalistik yang akan dihadapi sangat tidak ringan. Tantangan ini bisa berasal dari tekanan politik, ekonomi, atau bahkan tekanan internal dalam redaksi. Jurnalis perlu mempertahankan integritas mereka di tengah-tengah tekanan tersebut. Godaan bagi jurnalis untuk melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan etika jurnalistik. Hal ini bisa mencakup penyelewengan fakta, sensationalisme, atau bahkan keterlibatan dalam praktik-praktik yang tidak etis untuk mendapatkan berita.
Kebebasan merupakan nilai esensial seorang individual. Bebas artinya sama dengan independent, otonomi dan liberal. Dalam prinsip jurnalistik, usaha jurnalis untuk bebas bertindak dan beraksi dalam setiap asosiasi, ideologi, kelompok atau personal tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu dalam mencari berita. Menurut Franz Magnis Suseno kebebasan dibedakan antara Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial. Kebebasan Eksistensial merupakan kemampuan manusia (dalam hal ini jurnalis) untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan jurnalis untuk berpikir dan berkehendak dapat terwujud dalam tindakan ‘bebas untuk apa’. Sedangkan Kebebasan Sosial dimaknai sebagai kebebasan ruang gerak yaitu ‘bebas dari apa’ yang diberikan masyarakat kepada jurnalis yang berhubungan dengan orang lain atau faktor eksternal yaitu lingkungan, masyarakat dan sebagainya.
Mencermati pernyataan Ashadi Siregar, Dosen Ilm Komunikasi FISIP UGM Yogyakarta, berkah reformnasi Pasca-Orde Baru adalah lenyapnya ancaman pembredelan. Karena itu media pers sepenuhnyan dapat menjalankan orientasi dalam operasi jurnalisme yaitru menyampoaikan informasi factual yang penting dan menarik dalam kerangka kaedah jurnalisme demi obyektivitas-kebnenaran. Fakta dapat bersifat eksplisit dan nkhalayak tidak perlu menafsir-menafsir berita.
Media pers memang tidak lago menghadapi kekuasaaan fasis-militeristik, tetapi kini harus mempertahankan kehiduoan dari ancaman yang dating dari factor obyektif pasar. Masalah besar yang harus dihadapi adalah perubahan pola kmunikasi dalam arua besar Revolusi 4.0 yang membawa disruosi dari kemajuan teknologoi digital.
Media digital daring menjadi competitor bagi media pers konvesional. Pers konvensional tidak pelak ikut menghadirkan diri sebagai media daring. Ada yang berhasil mengambil kemanfaatan dari bisnis media baru ini, tetapi tidak kurajng yang hiodup segan mati tidak mau. Persoalan bukan sekedar disrupsi bisnis pasar media, melainkan juga dari aspek sosial. Tumbuh oesatnya teknologi digital berbasis internet melahirkan produsen informasi individual lewat media sosial. Informasoi lahir darei ujung jari setiap orang, tikdak lagi melalui gerbang yang dijaga ketat dengan kebvijakann keredaksian yang dijalankan kaum profesionbal demi kebenaran dan obyektivitas factual.
Sejalan dengan itu, bertumbuhnya bidaya baru dengan alammpikiran yang dibentuk oleh infomasi digital, yairu nilai pasca-kebenaran (post-truth). Bagi khalayak, komunikasi bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kebanran factual, melainkan sebagai pembenaran keyakinan. Dua ranah bertarung, satu sisi faktualitas dan rasionalisme yang dikembangkan dengan jurnalisme, dan sisi lain keyakinan yang dipupuk melalui eksklusivisme dalam interaksi di media sosial. Khalayak cerdas yang rela bersusah payah mencari kebenaran factual telah sirna. Khalayak bisa mengkritisi bagaimana kaum terdidik ,bahkan dari kalangan kamopus semskin banyak dengan alam fikiran yang dipenuhi doktrin.
Media menjadi ajang untuk mengaktualisasikan posisi dalam politik identitas eksklusif. Sikap partisan terbentuk atas dasar kedekatan emosiobnal, bukan dari penilaian rasional atas fakta. Dengan begitu media pers orientasi kebenaran obyektif kehilangan peranan sebab public hidup dengan media sosialyang eksklusif bagi subyektivitas kelompok masing-masing. Begitu pun menuntut agar media pers konvesnional bersikap partisan sesuai dengan preferensi kelompoknya. Menghadapi faktor eksternal dengan media sosial dan nilai pascakebenaran, mungkin kaum prpofesional jurnalisme sedia untuk memeranginya. Berbeda halnya jika harus berperang dengan diri sendiri, yaitu terdistorsinya bebas untuk bagi jurnalis akibat orientasi partisan yang didiktekan kekuasaan di lingkungan sendiri.
Jufri Alkatiri/Periset dan Penguji Kompetensi Wartawan (UKW) LPDS Jakaarta
Editor : Jufri Alkatiri