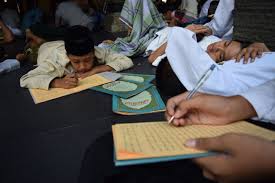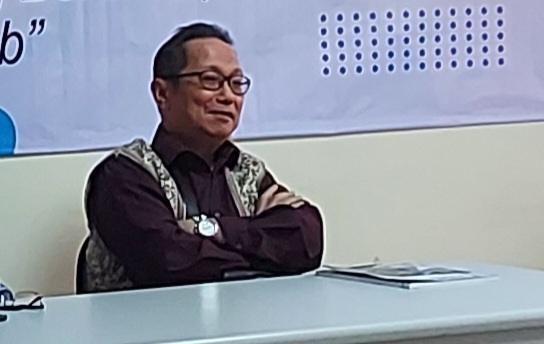Oleh: Kurniawan Zulkarnain*
Pada bulan Juni 2025, Bank Dunia atau World Bank (WB) merilis laporan data terbaru tentang kemiskinan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, jumlah orang miskin sebanyak 194,6 Juta dari 281,5 Juta atau 68,25 persen berdasarkan garis kemiskinan UMIC (Upper Middle Income Countries) line. Sedangkan berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) per September 2024 jumlah penduduk hidup dibawah garis kemiskinan 8,57 persen atau sekitar 24 Juta orang. Jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,01 juta — sementara di perkotaan sebesar 11,05 juta orang.
Perbedaan jumlah tersebut, karena definisi yang digunakan berbeda. BPS menggunakan metode kebutuhan riil lokal–rumah tangga,distribusi, urban/rural –.Sedangkan WB memakai garis kemiskinan internasional menggunakan PPP (Purchasing Power Parities) untuk perbandingan global,yang cenderung lebih tinggi terutama di garis UMIC, dimana Indonesia ada didalamnya dengan standar atau garis kemiskinan mereka yang berpendapatan US $ 8.3/kapita/hari.
Terdapat dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik dalam struktur sosial,ekonomi dan politik yang mengakibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Adapun ciri-cirinya antara lain adalah keterbatan akses pada pendidikan dan kesehatan, ketimpangan distribusi kekayaan dan sumber daya. Sistem upah murah dan ketidakadilan pasar kerja dan kebijakan pembangunan yang tidak pro-rakyat miskin.
Sementara kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh nilai-nilai yang dianutnya yang bersikap menyerah dan fatalistik. Adanya pola pikir dan kebiasaan hidup dalam suatu komunitas yang dipandang tidak mendukung perubahan. Ciri-cirinya adalah rendahnya motivasi untuk keluar dari kemiskinan, kurangnya semangat wirausaha dan inovasi. Selanjutnya, memanang pendidikan tidak penting dan ketergantungan pada bantuan luar terutama dari pemerintah dan pihak lainnya.
Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Terlepas dari perbedaan ukuran kemiskinan antara BPS dan WB, pemerintah kita telah dan sedang melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Program tersebut mencakup berbagai kebijakan dan langkah strategis dan regulasi lintas sektor untuk mengurangi angka kemiskinan struktural secara berkelanjutan. Pada intinya program kemiskinan bertumpu pada mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
Dimasa lalu, terdapat program Inpres Desa Tertinggal (IDT) Era Orde Baru tahun 1994, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 1998 sampai dengan 2000 untuk atasi krisis ekonomi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2007 sampai dengan 2014. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Regional Khusus, dan PNPM Mandiri Respek (Papua dan Papua Barat). Adapun jenis bantuan pada umumnya dalam bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukan kegiatan sosial,ekonomi dan lingkungan (infrastruktur berupa jalan dan jembatan di permukiman).
Program Perlindungan sosial (Social Safety Net) yang dilakukan dengan memberikan berbagai bantuan langsung, guna mengurangi beban masyarakat miskin.Program tersebut meliputi antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program yang lainnya adalah mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP,), Kartu Pintar Kuliah (PIP-K).
Program kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat meliputi program dana desa, penguatan UMKM, dan Ekonomi Desa berupa bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembinaan koperasi dan program digitalisasi UMKM. Selanjutnya, terdapat program pendidikan vokasi, beasiswa dan pelatihan kerja berupa link and match pendidikan dunia kerja.
Model Program Kemiskinan Berbasis Pondok Pesantren
Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional didirikan oleh seorang tokoh Agama Islam yang kemudian didukung oleh masyarakat. Perkembangan zaman dan tuntutan akan perlunya pendidikan, Pondok Pesantren menjadi dua kategori Tradisional (Salafiah) yang mengajarkan kitab kuning dan Pondok Pesantren Kholafiah (Islamic Boarding School) yang mengajarkan Ilmu Agama dan Ilmu Umum.
Eksistensi Pondok Pesantren semakin kokoh dengan terbitnya Undang-undang nomor 18 Tahun 2009. Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat disekitar, Pondok Pesantren menyelenggarakan kegiatan pendidikan Agama tetapi juga kegiatan ketrampilan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengentasan kemiskinan seperti kegiatan ekonomi dan pertanian. Menurut data Kementrian Agama (Kemenag) jumlah Ponpes pada tahun 2024 ini sebanyak 42.433 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sekurang-kurang terdapat 2 Pondok Pesantren yang telah berhasil dalam penyelenggaraan program kemiskinan. Ponpes tersebut adalah Pondok Pesantren Al-Ittifak di Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Pondok Pesantren Sidogiri di Sidogiri Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.
Pondok Pesantren Ciwidey didirikan pada tahun 1934 oleh KH Mansur, sejak tahun 1970-an diasuh oleh Drs KH.A. Mudrik Qori MA (Generasi Keempat). Kegiatan Ponpes ini menggabungkan Pendidikan Agama dengan Agribisnis mengoptimalkan ketinggian 1.200 meter. Model kegiatan Agribisnis dilakukan melalui penanaman berbagai sayuran dataran tinggi : wortel,kentang, tomat, buncis, cabe bahkan ciplukan (golden berry), disamping sayuran juga mengelola peternakan sapi, kambing, dan kelinci.
Lahan yang dikelola seluas 14 ha yang dimiliki oleh Ponpes dan 130 ha yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar Ponpes, pengelolaan melibatkan santri dan petani lokal. Hasilnya sebanyak 3 sampai 4 ton sayuran per-pengiriman — tiga kali seminggu ke pasar tradisional,beragam Supermarket di Bandung dan Jakarta, serta sejumlah Rumah Sakit. Ponpes juga mengelola Koperasi (Kopontren) bermitra dengan ribuan petani, unit produksi pupuk organik (20 ton/hari) dan pemasaran lewat Alif Mart dan Online. Ponpes ini terpilih sebagai role model sebagai Ponpes juara oleh Pemprov Jabar (2018) dan diakui oleh Menteri Koperasi atas progran ketahanan pangan dan ekosistem pasokan moderen.
Pengentasan Kemiskinan di Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri tahun tahun 1745 M, yang dikelola secara turun temurun, kini Ponpes ini diasuh oleh KH A. Fuad Nurhasan. Berdiri di atas lahan sekitar 8 ha. Jumlah sekitar 11.000 pada tahun 2002. Ponpes ini dengan Organisasi Nahdlatul Ulama. Program Pengentasan Kemiskinan yang dipandang berhasil adalah pengelolaan BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Produk Simpanan dan Pembiyaan, Mudharabah, Murabahah, Qord al-hasah, talangan haji, gadai emas, dana investasi berbasis hibah. Unit usaha pendukung berupa swalayan, toko busana muslim, distro, percetakan, mini market, apotek, pabrik AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) hingga fintech e-maal.)
Aset dan anggota BMT per Desember 2019 mencapai Rp.2,2 Trilyun dengan jumlah anggota sebanyak 800.000 yang tersebar di 10 Provinsi dan 221 kantor cabang. Omzet tahunan mencapai Rp 66 trilyun dan menjadikan model Ponpes Mandiri dan Santripreuneurship. BMT Sidogiri adalah contoh nyata dimana Santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Dari modal kecil dan berkembang jadi lembaga keuangan dan bisnis besar yang menciptakan dampak luas–baik bagi santri maupun masyarakat. Walahu ‘Alam Bi Sowab. (*)
*Konsultan Pemberdayaan Masyarakat dan Dewan Pembina Pembangunan Mahasiswa Islam Insan Cita (YAPMIC) Ciputat
Editor : Jufri Alkatiri