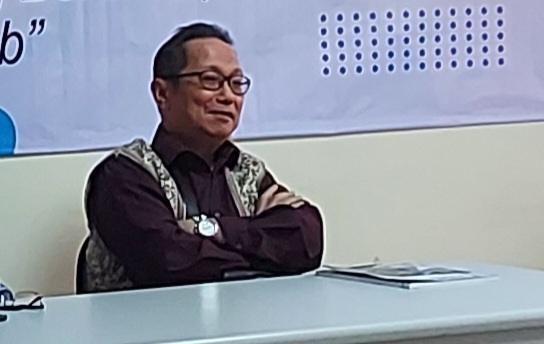Oleh: Kurniawan Zulkarnain*
Karir Profesional dan Politik Sudewo
Sudewo dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1968 di Pati, Jawa Tengah. Pendidikannya ditempuh di SMAN 1 Pati, Sarjana Strata-1 (S1) diperoleh pada tahun 1991 dari Faskultas Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret (UNS). Sarjana Strate-2 Teknik Pembangunan (S2) diraih dari Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2001. Karier profesional Sudewo, diawali dengan bekerja di PT Jaya Construction (1993–1994) , tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) di Bali (1994–1995). Menjadi CPNS dan kemudian PNS di Kanwil PU Jawa Timur (1996–1999) dan kemudian menjabat di Kepala Dinas PU Kabupaten Karanganyar (1999–2006).
Jejak langkah politik Sudewo berawal dari mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karanganyar (2002) bersama Juliyatmono, namun belum berhasil. Sudewo terpilih menjadi anggota DPR RI, untuk periode 2009–2014 dari Partai Demokrat (Dapil Jateng VII). Dan,setelah berpindah ke Gerindra pada 2013, Sudewo kembali terpilih 2019–2024 (Dapil Jateng III). Sudewo dan terpilih menjadi Bupati Pati untuk periode 2024–2029, bersama Risma Ardhi Chandra dari Pertai Kebangsaan Bangsa (PKB) dengan perolehan 53,53% suara, resmi menjabat sejak Februari 2025. Organisasi yang ikut membesarkan Sudewo adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991), Ketua Keluarga Besar Marhaenis, Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia dan koordinator Tim sukses beberapa Pilkada dan sekarang menjabat Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan .
Kontroversi dan sorotan publik pada Sudewo terkait dengan menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen, menimbulkan protes besar dari masyarakat Pati. Sudewo sempat menyatakan dirinya siap menghadapi puluhan ribu demonstran. Namanya disebut terkait kasus suap proyek jalur kereta (DJKA) muncul dalam persidangan dan disebut menerima uang Rp.3 miliar, yang kemudian dibantah Sudewo. Partai Gerindra memberikan teguran keras kepada Sudewo, kemudian dia mengembalikan uang Rp720 juta yang diduga terkait kasus tersebut, meski demikian KPK menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut tidak membebaskan diri dari proses hukum. Kekayaan Sudewo (menurut-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara–LHKPN), total harta mencapai Rp31,5 miliar (April 2025). Rinciannya meliputi 31 properti bernilai sekitar Rp17 miliar, kendaraan (6 mobil dan 2 motor) senilai Rp6,3 miliar (termasuk BMW X5 2023, Toyota Land Cruiser 2019, dan Alphard 2024), surat berharga Rp5,39 miliar, dan dana cash sekitar Rp1,96 miliar serta tidak ada utang terlapor.
Protes Penolakan Kenaikan Pajak Dalam Lintasan Sejarah
Gerakan protes rakyat Pati tanggal 13 Agustus 2025 merupakan pengulangan sejarah dari masa lalu. Pada tahun 2009, warga menolak rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) di Pegunungan Kendheng — dengan isu yang sama, April 2011– ribuan petani dan warga dari sejumlah Kecamatan (Sukolilo, Tambakromo, Kayen) melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Pati menentang pendirian pabrik. Selanjutnya,pada 2014 terdapat aksi besar dilakukan sekitar 3.000 orang menentang pendirian pabrik, bersamaan dengan sidang AMDAL berlangsung. Pada Desember 2017, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Pengunungan Kendheng (JMPPK) melakukan aksi di Kantor Bupati mendesak agar izin PT SMS, tidak diperpanjang. Perlawanan mereka berkembang menjadi narasi lingkungan, ekonomi lokal, sosial, budaya, hingga politik — mengusung konsep ekopopulisme. Kekuatan gerakan terbangun dari solidaritas antara komunitas Samin dan petani Kendheng, didukung jejaring akademisi, LSM dan komunitas pemuda.
Penolakan terhadap kebijakan pajak bukan fenomena baru—sejarah mencatat sejumlah momen penting di mana rakyat bergabung untuk protes karena merasa terbebani dan diperlakukan tidak adil. Pada 1908, terjadi Perang Belasting (1908) di Sumatera Barat yang dipicu oleh penerapan pajak langsung (belasting) oleh kolonial Belanda, rakyat Minangkabau melakukan perlawanan besar. Tokoh seperti Haji Abdul Manan dan Kari Mudo menjadi simbol perlawanan. Bentrokan terjadi pada 15–16 Juni 1908, yang menewaskan banyak rakyat, termasuk pemimpin mereka. Pajak ini dipungut langsung per orang, bukan berdasarkan hasil bumi atau tanah. Hal ini dianggap tidak adil dan memberatkan masyarakat. Pajak dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau dan syariat Islam. Masyarakat menilai belasting hanyalah bentuk perampasan terselubung oleh kolonial.
Di Blora, Jawa Tengah, Samin Surosentiko memimpin perlawanan moral dan spiritual terhadap pajak kolonial. Rakyat diajak untuk menolak membayar pajak sebagai bentuk sikap ketidakadilan sekaligus sebagai bentuk pembelaan terhadap kesejahteraan bersama. Penolakan pajak oleh Ki Samin Surosentiko (atau Surontiko Samin) adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat desa terhadap kebijakan kolonial Belanda di Jawa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gerakan ini dikenal dengan sebutan Gerakan Samin atau Sedulur Sikep untuk tidak membayar pajak tanah dan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Penolakan dilakukan bukan dengan senjata, tetapi dengan ajaran moral dan sikap pasif. Hidup jujur, tidak iri dengki, tidak merugikan orang lain merupakan ajaran Samin. Harta benda milik bersama, tidak boleh dirampas oleh negara. Tanah dan alam adalah titipan, bukan untuk dijadikan beban pajak,menjalani hidup dengan mengutamakan kebersamaan dan kemandirian.
Pada Mei-Juli 1960, terdapat penolakan masyarakat Desa Bo’a-Rote Ndao-Nusa Tenggara Timur (NTT), karena pemerintah menaikkan pajak.Perlawanan Pajak yang dikenal sebagai Delha Affair di Rote Ndao, juga disebut Nusak Delha Affair — satu bentuk protes masyarakat terhadap pungutan pajak yang dianggap tidak adil. Pada sekitar tahun 1950, tokoh seperti pensiunan KNIL bernama Matheos Petrus (beberapa sumber menyebut sebagai Matheus Feo) muncul sebagai pemimpin protes. Dia menggalang dukungan masyarakat Delha untuk membayar pajak hanya sebesar Rp 3,75 per orang per tahun, jauh di bawah ketetapan resmi pemerintah yaitu 2,50 Gulden. Pemerintah daerah melakukan operasi penagihan mulai Oktober 1959, mendapatkan respons keras dari masyarakat yang menolak membayar sesuai ketetapan pemerintah. Pada 1960 terjadi bentrokan antara petugas (termasuk polisi) dan warga, yang menyebabkan tewasnya dua polisi dan dua warga. Beberapa rumah dibakar oleh warga karena takut mendapat tindakan balasan.
Etika Subsisten dan Protes Rakyat Kenaikan Pajak
James C. Scott, dalam karya klasiknya ‘’Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistesi di Asia Tenggara” (LP3ES, 1981) banyak membahas hubungan antara negara, pajak, dan etika subsistensi petani. Scott berangkat dari pandangan bahwa petani subsisten hidup dalam ekonomi dengan margin tipis—mereka bekerja terutama untuk bertahan hidup, bukan mencari keuntungan maksimal. Prinsip utama yang ia sebut sebagai subsistence ethic. Petani dapat menerima eksploitasi tertentu (seperti upeti atau pajak), selama kebutuhan dasar hidup mereka tidak terganggu. Jika pungutan (pajak, sewa tanah, dan tenaga kerja wajib) mengancam “garis subsistensi” (minimum kebutuhan hidup), maka resistensi atau pemberontakan sangat mungkin muncul. Pajak bagi petani bukan sekadar kewajiban fiskal, melainkan simbol relasi kekuasaan antara penguasa (negara, bangsawan, atau tuan tanah) dengan rakyat kecil.
Dalam etika subsistensi,pajak dianggap absah jika tidak merampas kebutuhan dasar pangan. Pajak dianggap tidak sah bila menyebabkan kelaparan, penggusuran, atau menurunkan daya hidup petani. Scott menekankan bahwa dalam masyarakat agraris Asia Tenggara, negara tradisional bertahan lama karena mampu menjaga “tawar-menawar moral”. Petani menyerahkan sebagian surplus, negara tidak memaksa hingga titik kelaparan. Pajak tidak semata-mata soal ekonomi, tapi terkait legitimasi moral dan politik. Negara yang tidak peka terhadap “etika subsistensi” akan menghadapi resistensi rakyat. Relevansi hingga kini,gerakan rakyat menolak kenaikan pajak (misalnya kasus Pati 2025 atau protes PPN) bisa dipahami melalui kacamata Scott sebagai respon moral—masyarakat merasa beban fiskal mengancam “garis aman hidup” mereka. Ketika negara atau elit menekan lebih dari batas wajar (misalnya menaikkan pajak berlebihan saat gagal panen), petani menafsirkan itu sebagai pelanggaran etika subsistensi.
Ilmuwan lainnya, Prof. Sartono Kartodirdjo, penulis buku Pemberontakan Petani di Banten tahun 1888, pertama kali terbit tahun 1966 oleh Cornell University (disertasi doktornya), kemudian diterjemahkan serta diterbitkan di Indonesia oleh PT Pustaka Jaya Tahun 1984. Sartono membahas pemberontakan petani di Banten,yang dipimpin oleh tokoh-tokoh keagamaan lokal (Kiyai dan Jawara). Sartono menggunakan pendekatan sejarah sosial (social history), yang pada saat itu masih baru di Indonesia, berbeda dengan sejarah politik arus utama. Pemberontakan petani Banten,dipicu oleh kehidupan petani yang penuh penderitaan akibat eksploitasi kolonial Belanda (cultuurstelsel, pajak, dan kerja paksa). Penindasan oleh elite lokal (Bupati dan Pejabat pribumi). Masyarakat Banten dilanda krisis ekonomi dan sosial (kemiskinan, beban utang dan ketidakadilan). Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan sosial yang melahirkan potensi pemberontakan.
Kiyai dan Guru Agama memobilisasi rakyat melalui moralitas ajaran Islam. Pemberontakan diwarnai dengan konsep mesianisme yaitu keyakinan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi yang membawa pesan dan menegakkan keadilan. Pesantren menjadi pusat penyebaran gagasan perlawanan. Jaringan Sosial Rakyat kecil, petani, buruh, dan jawara menjadi basis gerakan. Hubungan patron-klien antara kyai dan pengikutnya memperkuat mobilisasi massa. Kronologi pemberontakan meletus pertama kali di Cilegon, Banten, 1888.
Serangan terhadap pejabat Belanda dan aparat pribumi dilakukan. Pemberontakan dapat dipadamkan dengan cepat oleh pemerintah kolonial karena perlawanan rakyat bersifat spontan, lokal, dan tidak terkoordinasi luas. Analisis Sartono, pemberontakan bukan sekadar gerakan keagamaan fanatik, tetapi manifestasi perlawanan sosial-ekonomi terhadap ketidakadilan kolonial. Analisisnya menggunakan pendekatan multi-dimensional: ekonomi, sosial, politik, dan budaya.Gerakan rakyat kecil di Indonesia sering muncul dari ketidakadilan struktural, bukan semata-mata agitasi politik.
Pelajaran penting dari sejarah gerakan penolakan pajak di Kabupaten Pati menjadi indikator meningkatnya kesadaran kolektif rakyat, penolakan pajak lahir dari rasa ketidakadilan dan membentuk solidaritas sosial komunitas lokal sangat kuat sebagai basis perlawanan. Pajak tidak sekadar pungutan ekonomi, melainkan simbol legitimasi pemerintah. Ini terlihat sejak era perlawanan Ki Samin Surosentiko (abad ke-19) sampai gerakan rakyat modern, di mana pajak menjadi alat ukur keadilan sosial. Petani Pati, seperti yang dijelaskan James C. Scott dalam konsep moral ekonomi petani, menempatkan kelangsungan hidup (subsistensi) di atas kepentingan negara atau elite. Pajak yang dianggap mengganggu keseimbangan hidup subsisten akan ditolak, bahkan dengan risiko konflik. Sartono Kartonodirjo memandang kombinasi antara ketidak-adilan dan pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap mitos dapat menjadi landasan etis melakukan perlawanan sipil (Civil Disobendience). Wallahu ‘Alam Bi Sowab. (habis)
*Konsultan Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Pembina Yayasan Pembangunan Mahasiswa Islam Insan Cita (YAPMIC) Ciputat
Editor: Jufri Alkatiri