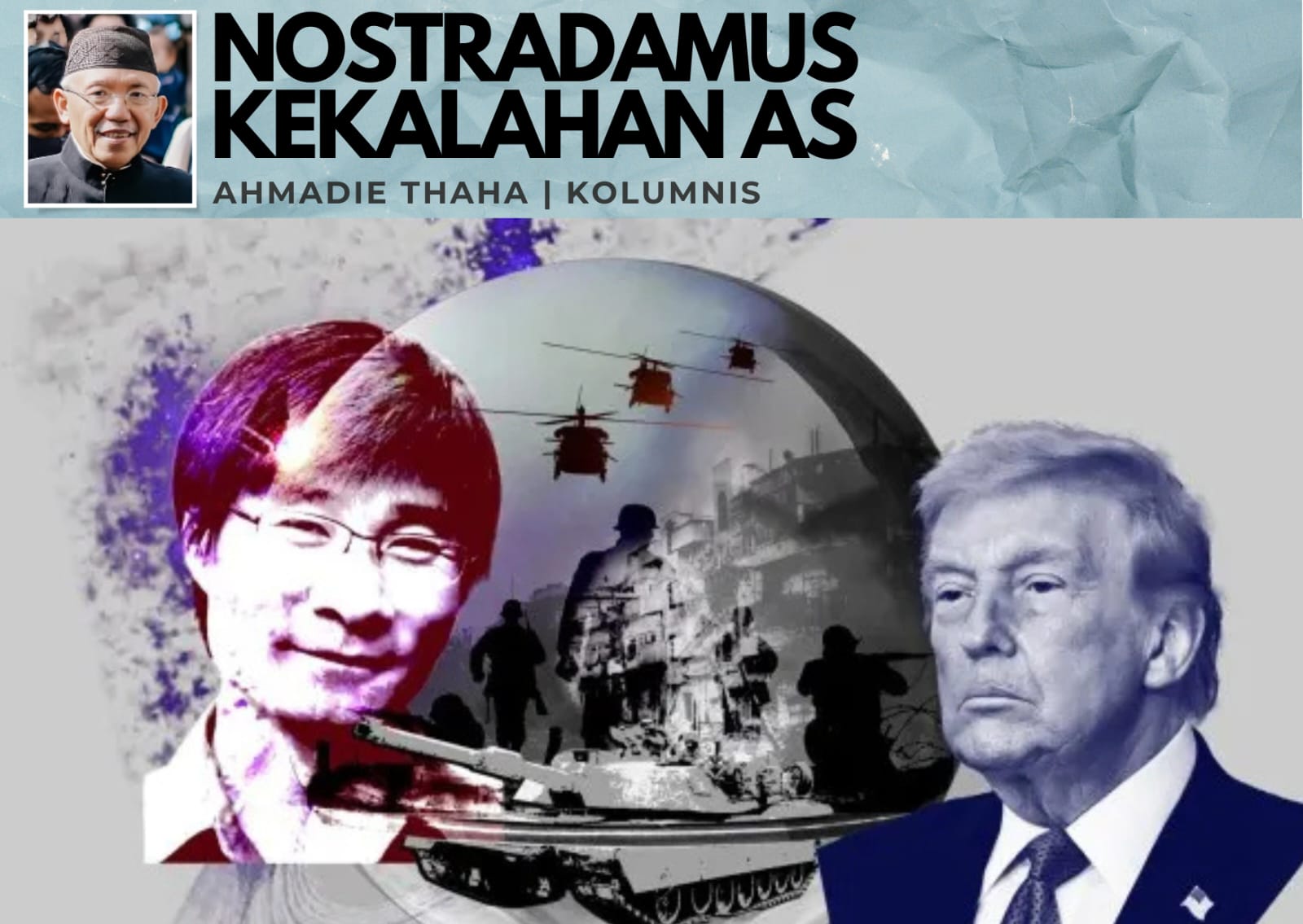Oleh: Prof. DR. Ahmad Humam Hamid*
Di tengah gaduh pencabutan empat pulau dari Aceh Singkil ke Sumatera Utara, narasi yang mengemuka masih sebatas persoalan administratif dan birokrasi batas wilayah. Nyaris tidak ada suara yang menggali kedalaman sejarah, kebudayaan, dan spiritualitas tanah kecil di barat daya Aceh itu. Padahal Singkil bukan sembarang titik koordinat.
Singki adalah denyut awal bagi lahirnya kebesaran Aceh, bahasa Indonesia, dan jejaring budaya Nusantara. Jika negeri ini sedang mencari akar, maka dia harus menoleh ke Singkil–bukan untuk romantisme semata, tetapi karena di sanalah ruh Indonesia pertama-tama dirintis.
Adalah Hamzah Fansuri, tokoh besar abad ke-16, penyair sufistik pertama dalam sejarah Melayu yang menulis syair dalam bahasa yang kelak akan menjadi fondasi bahasa Indonesia. Dia tidak sekadar penulis puisi, tapi juga pemikir lintas batas yang meramu tasawuf, filsafat, dan geografi spiritual.
Fansuri menuliskan Tuhan dalam bentuk yang dalam namun membumi, menyatu antara kata dan makna, antara Melayu dan semesta. Dari Singkil, da membangun bahasa sebagai jalan iman dan intelektual.
Tidak lama setelahnya, dari lingkungan keilmuan yang sama, muncul turidnya yang sangat kondang, Syamsuddin As-Sumatrani dan Abdurrauf As-Singkili. Keduanya menulis, mengajar, dan membentuk dasar intelektual Islam Nusantara. Mereka mendiskusikan relasi antara syariat dan hakikat, antara akal dan ilham, bahkan antara lokalitas dan universalitas.
Abdurrauf, yang kemudian menjadi Mufti Kesultanan Aceh, juga penerjemah tafsir Qur’an pertama dalam bahasa Melayu. Bahasa ini, kelak, adalah bahasa Sumpah Pemuda 1928, dan bahasa Proklamasi 1945– yang disusun dan dibacakan dalam ruh Melayu yang dirintis dari tanah Singkil.
Singkil bukan sekadar tempat lahir tokoh. Dia adalah episentrum awal di mana ide tentang kebangsaan, spiritualitas, dan bahasa menyatu jauh sebelum negara ini bernama Indonesia. Maka menjadi aneh dan tragis bila hari ini tanah itu nyaris tak dikenang, bahkan wilayahnya dipotong tanpa narasi, tanpa penghormatan sejarah, seolah ia hanyalah angka dan peta.
Harapan untuk Prabowo dan Fadhli Zon
Amerika punya Philadelphia–tempat konstitusi dan semangat revolusi ditulis. Turki punya Konya–tanah Maulana Rumi yang disucikan sebagai pelabuhan batin bangsa. Jepang menjaga Kyoto sebagai akar tradisinya, dan Iran membanggakan Isfahan sebagai simbol keagungan peradaban.
Lalu Indonesia? Kita punya Singkil, namun kita melupakannya. Kita sibuk membangun Ibu Kota Nusantara, tapi lupa pada titik mula bahasa, iman, dan sastra yang menyatukan kita. Di sinilah peran Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi penting dan strategis.
Beliau bukan hanya politisi, tetapi penyair dan pembaca sejarah. Dalam tangannya kini terbuka peluang untuk menebus kelalaian kolektif kita. Jika Kementerian Kebudayaan mau dan bisa menginisiasi penetapan Singkil sebagai kawasan budaya nasional, atau bahkan lebih: sebagai ikon bahasa dan spiritualitas Indonesia, maka bangsa ini akan menunjukkan bahwa dia tidak melupakan tanah-tanah tempat dia tumbuh.
Tidak berlebihan bila kita membayangkan lahirnya Pusat Studi Hamzah Fansuri di Singkil, atau penyelenggaraan Festival Bahasa dan Sufi Melayu Nusantara yang merayakan warisan tiga tokoh besar itu setiap tahun. Bahkan buku pelajaran sejarah nasional perlu memuat mereka sebagai pelopor, bukan hanya dalam konteks Aceh atau Islam, tetapi dalam konteks nasional Indonesia. Sebab bangsa yang sehat adalah bangsa yang tahu siapa yang menanamkan akar kata dan makna pertama bagi rumah kebangsaan yang ditempati hari ini.
Presiden Prabowo, yang banyak bicara tentang ketahanan nasional dan kebangkitan peradaban, mestinya melihat proyek kebudayaan ini sebagai bagian dari strategi besar kebangsaan. Di tengah dunia yang semakin cair dan pasca-hegemonik, ketika kekuatan tidak lagi semata soal senjata atau uang, tetapi tentang narasi dan jati diri, maka mengangkat kembali Singkil adalah langkah geopolitik kultural yang penting.
Kita hidup di era globalisasi gelombang baru, di mana pusat-pusat lama melemah dan kekuatan baru bermunculan. Dunia tidak lagi tersusun secara bipolar. Kita menyaksikan Tiongkok yang kuat tetapi tidak hegemonik, Rusia yang memecah konsensus, dan Amerika yang–terutama setelah era Trump–menjadi makin inward-looking.
Dalam dunia tanpa pusat ini, bangsa-bangsa hanya bisa bertahan jika punya memori kolektif dan simbol kuat yang menyatukan rakyatnya. Singkil, jika dihidupkan ulang secara simbolik dan budaya, bisa menjadi jangkar ruhani dan historis Indonesia. Dan dalam konteks polemik pemindahan empat pulau itu, pertanyaannya kini bukan lagi sekadar di provinsi mana pulau itu berada, tetapi “di ingatan siapa pulau dan tanah itu hidup.”
Ketika wilayah dipindahkan tanpa penghormatan sejarah, maka yang terpotong bukan hanya batas peta, tetapi urat nadi kebangsaan.
Pak Fadli Zon, melalui tulisan ini kami mengingatkan: Singkil bukan sekadar wilayah. Dia adalah ruang sakral kebudayaan nasional, tempat bahasa Indonesia bertunas dalam bentuk Melayu tinggi, tempat Islam Nusantara meletakkan kerangka pemikiran pertamanya, dan tempat ruh bangsa ini mulai mengendap menjadi identitas.
Jika kita terus membiarkan tanah ini dilupakan, maka kita sedang mencabut akar yang menopang batang pohon kebangsaan. Tetapi jika kita berani menjadikannya ikon budaya nasional, maka kita sedang meneguhkan bahwa Indonesia tidak hanya besar karena tanah dan lautnya, tetapi karena ingatan dan maknanya.
Sudah waktunya Singkil dibaca kembali, bukan sebagai kasus administratif, tetapi sebagai kisah panjang tentang siapa kita sebagai bangsa. Sejarah bangsa yang besar selalu dimulai dengan keberanian untuk mengingat.
*) Penulis adalah Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Editor: Jufri Alkatiri