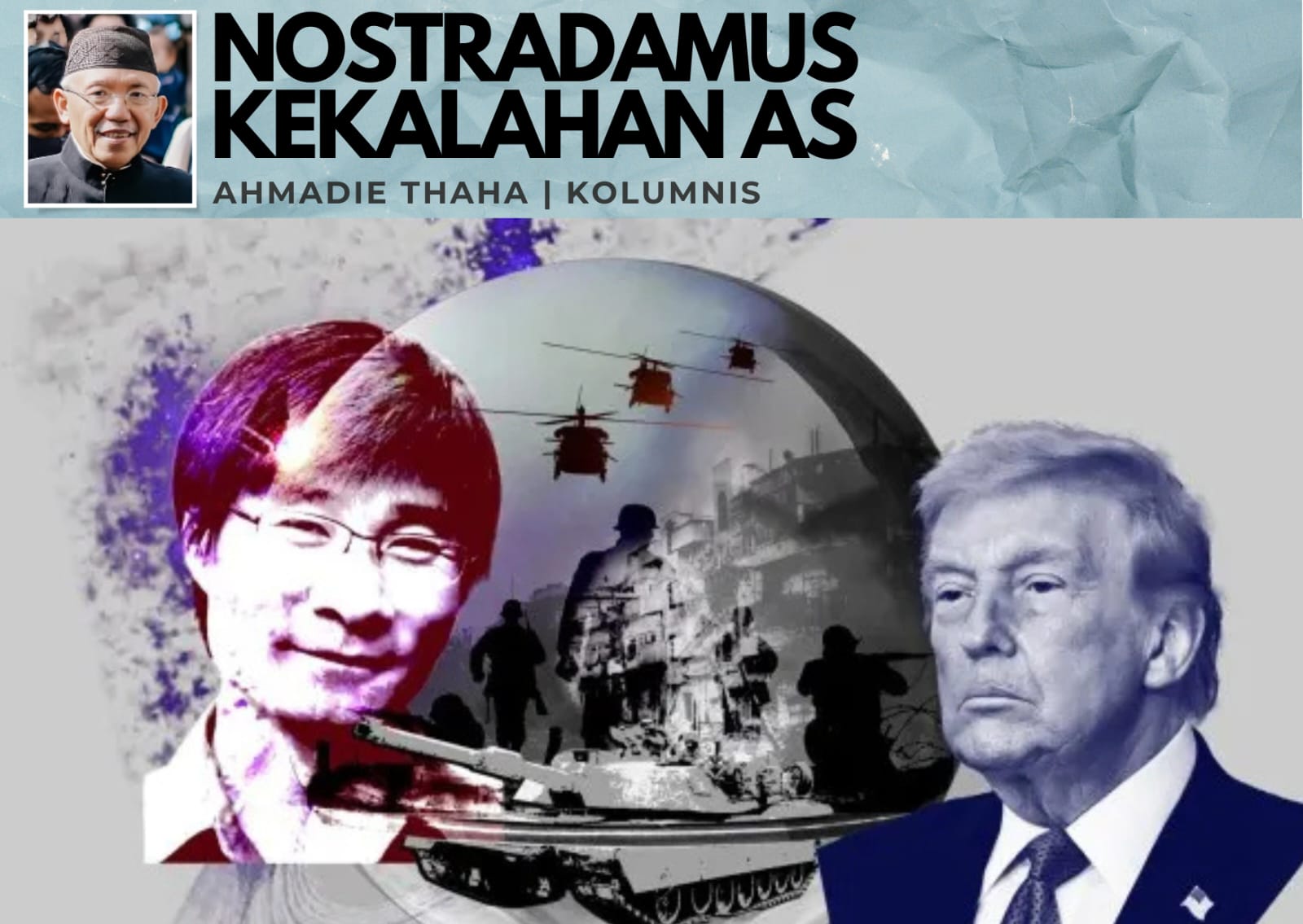Oleh: Renville Almatsier*
Dalam upacara di Taman Ismail Marzuki (TIM) Senin malam 13 Oktober 2025 — Martin Aleida menerima Penghargaan Akademi Jakarta 2025. Dia bersama komunitas mama-mama masyarakat adat Malind Anim di Papua dinilai konsisten memperjuangkan dan mengembangkan visinya dalam seni dan kebudayaan.
Dalam sambutannya Ketua Akademi Jakarta Seno Gumira Ajidarma mengungkapkan bahwa pemberian penghargaan ini sesungguhnya merupakan bagian dari pemberian suatu penanda. Penanda apa? Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Penanda tentang siapa yang harus dibela. Penanda tentang siapa yang harus dipedulikan. Penanda tentang siapa yang harus diperjuangkan. Penanda tentang siapa yang harus diberi perhatian sepenuhnya. Penanda tentang siapa yang sudah semestinya dimenangkan!
Salah satu penerima penghargaan adalah Komunitas Mama-mama Suku Marind Anim dari masyarakat adat di Papua bagian selatan yang mendiami wilayah pesisir dari Komodo hingga Sungai Digul. Masyarakat ini berupaya keras melindungi wilayah adat mereka yang sejak zaman kolonial Belanda tahun 1902 hingga dekade terakhir ini, terus menerus dipaksa menerima berbagai megaproyek.
Proyek-proyek ini, di antaranya Mega Proyek Merauke Integrated Rice Estate dan, yang terakhir Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate, telah merampas sekitar enam juta hektar lahan dan hutan adat mereka. Hutan adalah rumah kaum perempuan mencari bahan bakar, hasil hutan, dan sumber air. Akademi Jakarta memberikan penghargaan kepada Komunitas Mama-Mama atas kegigihan mereka memperjuangkan keadilan budaya dan keadilan ekologis yang tidak terpisahkan dari keadian sosial dan hak asasi manusia. Melalui video conference Ibu Yasinta Moiwend tampil mengharukan di layar besar menerima penghargaan itu secara daring.
Kita yang mengenal karya-karya Martin tentu menerima berita tentang penghargaan ini dengan rasa bangga. Dia yang konsisten menulis tentang peristiwa 1965 layak untuk penghargaan itu. “Saya menulis semua kenangan yang berujung di usiaku yang lebih tiga perempat abad, sekedar untuk mencatat takdir yang telah saya lalui. Yang getir. Juga yang membuat hidup berbunga-bunga, tidak hanya untuk saya, juga bagi yang lain”, tulisnya dalam Memoar Romantika Tahun Kekerasan.
Berderet-deret buku dan cerpen sudah ditulisnya. Di antaranya Dendam Perempuan; Leontin Dewangga; Mati Baik-baik, Kawan; Ritus Panjang untuk Simon; Tuhan Menangis Terluka; Malam Kelabu; Kata-kata Membasuh Luka; dan Tanah Air yang Hilang. Semua bercerita seolah perlawanan atau kontra narasi terhadap praktik kebenaran tunggal yang diproduksi dan direproduksi otoritas yang telah membentuk pendapat selaras dengan kepentingan rezim. Melalui tulisan-tulisannya Martin mendekonstruksi ingatan kita — dia melawan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Kemarin, di TIM Martin mengawali sambutannya dengan kecap tentang suka-dukanya sejak remaja, ditangkap oleh Operasi Kalong, menyaksikan berbagai penyiksaan hingga kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.
Dia mencatat korban pembersihan pada masa Orde Baru saja setengah juta orang terbunuh, 12.000 diasingkan ke Pulau Buru, sekitar 3.000 dipenjarakan. Semua distigmasi sebagai musuh negara tanpa proses peradilan. Mereka itu, rakyat kecil, termasuk petani buta huruf yang diperlakukan tidak adil oleh penguasa, karyawan yang kehilangan nafkah akibat ketidak-tahuan mereka, serta para eksil yang tidak bisa pulang ke tanah airnya sendiri itulah yang menjadi subjek tulisan-tulisan Martin.
Ketika pada sesi tanya jawab, seorang yang hadir bertanya dimana sebenarnya posisi Martin berdiri? Dia berpihak pada kejujuran. Kejujuran pada akhirnya adalah keberpihakan. Pertanyaannya, keberpihakan kepada siapa? Jawabnya terangkum dalam sambutan Ketua Akademi Jakarta di atas.
Dalam skop Indonesia, penghargaan untuk Martin ini mungkin bisa disandingkan dengan Aleksandr Solzhenitsyn yang menerima penghargaan Nobel Sastra pada berkat karya-karyanya temasuk The Gulag Archipelago pada 1970.
Saya bersimpati pada Komunitas Mama-mama di Papua. Mungkin juga karena sering membaca bagaimana saudara-saudara kita di sana selalu tertinggal dalam aspek sosial ekonomi, Pendidikan, dan pembangunan dibanding daerah-daerah lain di negeri kita.
Akan halnya Martin, saya kenal sejak kami sama berkerja di Majalah EKSPRES dan TEMPO. Dia yang doeloe sering berlari dari rumahnya di Pasar Minggu ke kantor di Senen Raya, kini terpaksa bergerak di atas kursi roda. Saya mendoakan semoga dia terus menulis dan mengilas-balik kisah-kisah di tabir sejarah masa lalu.
*Pengamat Sosial dan Mantan Jurnalis Majalah Berita Tempo
Editor: Jufri Alkatiri