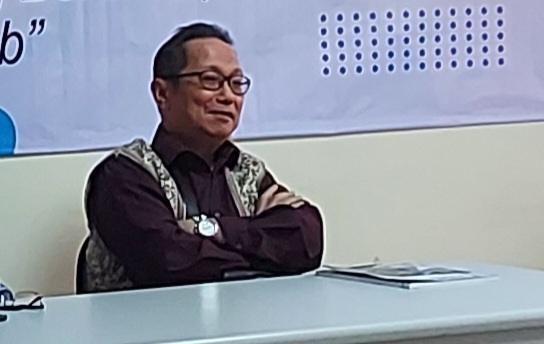Oleh: Renville Almatsier*
“Apa nama ibu kota Provinsi Sumatera Utara?” Pertanyaan sederhana itu diajukan kepada sekelompok anak sekolah, tampaknya setingkat SMA atau malah ada yang bertampang mahasiswa, dalam tayangan video yang beredar luas di media sosial belum lama ini.
Secara bergantian anak-anak, dalam tayangan itu menjawab. Ada yang menyebut Malaysia. Ada yang menjawab Maluku. Yang lain menebak Kalimantan” Masya Allah. Banyak juga yang menjawab, tidak tahu. Kita, penonton mungkin tertawa melihat kebodohan generasi muda ini. Tetapi lebih dari sekedar lucu, saya justru merasa miris. Apalagi mereka itu menjawab tanpa terkesan ada rasa bersalah atau malu.
Mungkin di tempat lain banyak anak kita yang pintar dan jago dalam berbagai hal. Terbukti anak-anak Indonesia yang cerdas sering diberitakan memenangkan berbagai lomba di luar negeri. Tetapi, bahwa di sekitar kita ada anak-anak sekolah yang tidak tahu ibukota Provinsi Sumatera Utara, yah… sudah keterlaluan!
Ironisnya kejadian itu sangat berdekatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 2025. Saat mana pemuda zaman kini bukan lagi melawan penjajah kolonial, melainkan beradaptasi dengan Teknologi Digital termasuk AI (Kompas, 29 Oktober 2025).
Tayangan itu jelas sekali menunjukkan betapa rendahnya pengetahuan umum anak-anak kita. Saya menghubungkannya dengan rendahnya minat baca generasi muda kita. Rendahnya minat baca jelas mempengaruhi kemampuan literasi. Literasi adalah kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan teks tertulis sebagai medium komunikasi di masyarakat dan mengembangkan pengetahuan. Dari pembahasan di berbagai media, kita harus mengakui bahwa minat baca bangsa kita sangat ketinggalan.
Terpaksa saya ulang-kutip data berikut. Menurut Catatan Iptek, tulisan Ahmad Arif (Kompas, 18/9/16), data UNESCO 2012 menunjukkan bahwa index minat baca di Indonesia 0,001. Artinya setiap 1.000 penduduk hanya satu yang memiliki minat baca. Dalam World’s Most Literate Nations, yang dikutip penulisnya, Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Hanya di atas Botswana, negara kecil di Afrika.
Tulisan lain dari Idi Subandy Ibrahim (Kompas, 14/5/22) mengutip Prof Denys Lombard — seorang pakar sejarah Indonesia asal Perancis yang mencatat, secara umum orang Indonesia sedikit sekali membaca. Sebaliknya, data dari tulisan yang sama juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara pengguna aktif Facebook nomor 4 dunia (60,3 juta pengguna), nomor 3 untuk Twitter (50 juta), dan minimal 4,1 juta tweet per hari. Internet sebagai ujung tombak dari teknologi digital memang menyediakan kemudahan mengakses informasi dan pengetahuan. Tetapi menurut peneliti sosial Sherry Turkle (2011), teknologi ini juga melahirkan pendangkalan kemampuan bernalar.
Tulisan Sri Haldoko, seorang guru di Brebes, memprihatinkan kemampuan anak-anak menyerap cerita-cerita sastra (Kompas, 21 Juli 2025). Dunia hari ini memang terlalu instan. Semua ingin cepat. Anak-anak dalam tayangan video itu – dan mungkin banyak lagi kawan-kawan segenerasi mereka, tentu berfikir buat apa menghafal “tetek-bengek” nama kota segala. Kini, toh semua bisa tinggal klik mesin pencari data.
Saya sering menjumpai orang yang, saking malas berfikir, bertanya: hari ini hari apa ya? Buat apa repot? Tanyakan saja lewat gawai. Begitu juga untuk mencari jalan dalam kota saja, orang kini mengandalkan Waze atau Google dari pada susah menghafal lokasi, arah dan nama jalan. Mereka mungkin merasa nyaman dengan keadaan sehari-hari yang cukup untuk bertahan hidup secara sosial. Namun tugas kita untuk mengingatkan bahwa di tengah laju informasi yang menggila, jiwa juga harus punya kedalaman. Apa jawaban yang muncul dari mesin-mesin itu hanya berupa kata yang mudah hilang. Kalau semua mengandalkan gawai, hubungan antar manusia pun akan kehilangan keterkaitan emosional.
Kembali ke tayangan video yang jadi topik pembahasan kita itu, saya kira Depdikdasmen harus melihat kebodohan anak-anak itu dengan lebih serius. Sesuatu harus dilakukan agar generasi muda kita bisa bersaing di dunia! Sesuatu itu harus bisa mendorong kemampuan siswa berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berempati. (*)
*Pengamat Sosial dan Mantan Jurnalis Majalah Berita Tempo
Editor: Jufri Alkatiri