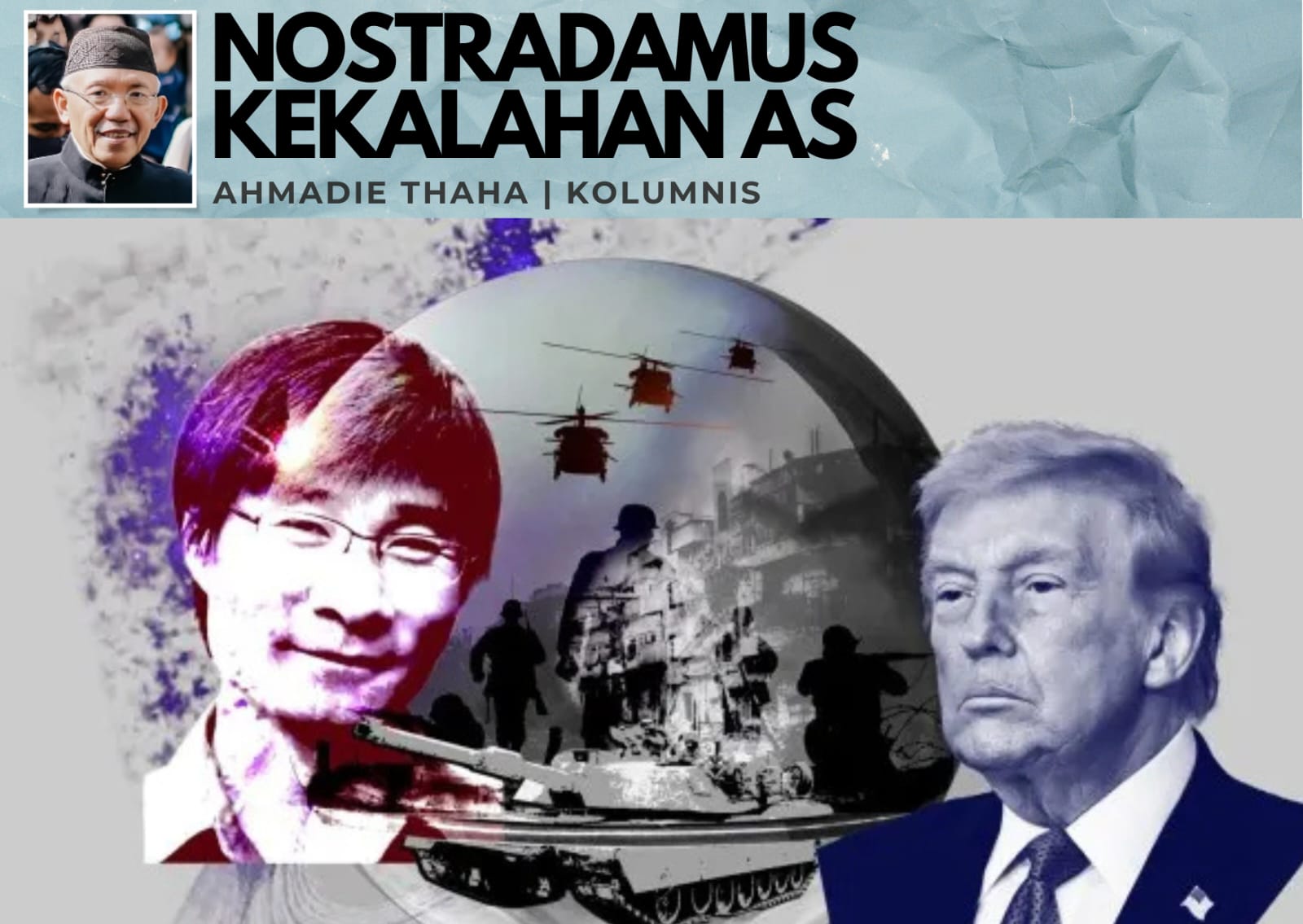Oleh: Benz Jono Hartono*
Kilasan awal bahasan — bagaimana Presiden Soeharto menjalankan kekuasaan selama 32 tahun dengan teknik yang dalam terminologi ilmiah—dapat disebut sebagai soft authoritarian choreography: menari bersama elite sambil memastikan tidak ada penari lain yang mencuri spotlight.
Kasus salah seorang Jenderal — menjadi contoh klasik bagaimana penguasa Orde Baru mampu menggeser figur paling berpengaruh di militer tanpa perlu memecahkan satu pun kaca Gedung Merdeka Utara — dengan pendekatan sinis-teoretik, kajian ini menempatkan Soeharto bukan hanya sebagai pemimpin otoriter, tetapi sebagai kurator seni instalasi politik paling halus di Asia Tenggara.
Ketika kekuasaan dioperasikan seperti listrik diam, tetapi menyetrum — dalam studi politik moderen, kekuasaan biasanya diasosiasikan dengan konflik terbuka, demonstrasi, atau minimal debat panas di ruang parlemen, namun, Orde Baru bekerja dengan logika berbeda: “yang ribut rakyatnya, yang tenang elitnya.” Dalam ketenangan itu, Soeharto membangun sistem kekuasaan yang begitu hening, sehingga banyak orang tidak sadar telah digeser kursinya saat sadar kursinya sudah hilang.
Seorang Jenderal kharismatik — sosok yang paling monumental dari seni instalasi kekuasaan Soeharto Teori Elite: tidak semua elite sama—ada elite yang bisa dipindah seperti pot tanaman. Menurut teori elite klasik, ada dua jenis elite: 1. Elite yang loyal, yaitu mereka yang tahu tempat duduk dan tidak bertanya siapa yang menentukan tata letak ruangan. 2. Elite yang kompeten, yaitu mereka yang terlalu pintar sehingga berbahaya.
Sang Jenderal berada di kategori kedua — dan dalam rezim otoriter birokratis, kategori kedua biasanya tidak masuk rencana anggaran jangka panjang. Mosa dan Pareto (dua filsuf Italia) — mungkin tidak pernah bertemu Soeharto, tetapi jika bertemu, mereka pasti akan menulis bab tambahan: “Cara Mengelola Elite: Panduan Tenang Tanpa Drama.”
Soeharto dan Filsafat kekuasaan politik sebagai seni merawat Bonsai. Soeharto sering digambarkan sebagai “Lurah Nasional”— tetapi itu meremehkan. Dia lebih mirip seniman Bonsai: memotong sedikit cabang, mengikat pelan batang yang keliru, menyiram bagian tertentu, lalu membiarkan seluruh tanaman tampak natural seolah tumbuh begitu saja.
Sang Jenderal adalah cabang Bonsai yang tumbuh terlalu tinggi. Dalam Estetika Soeharto, Bonsai tidak boleh menantang matahari. Maka dipangkas… perlahan… sistematis… elegan… dan tetap sopan. Anatomi penggeseran Sang Jenderal: Sebuah Bedah Politik Tanpa Bius, Tanpa Darah 1. Memuji Kompetensi Lawan. Langkah awal Soeharto bukan memarahi. Dia memuji: “Jenderal tesebut pintar, tapi…” Dalam politik Orde Baru, kata “tetapi” lebih mematikan dibanding pedang Samurai. 2. Mengubah Struktur, Bukan Mengusir Orang. Soeharto tidak menyingkirkan. Dia hanya menata ulang ruangan. Kalau dalam versi akademiknya: institutional restructuring. Dalam versi lainya adalah: “memindahkan kursi tanpa memberi tahu pemiliknya.” 3. Mengeringkan Sumber Daya Informasi. Sang Jenderal adalah Raja Intelijen. Langkah Soeharto cukup mengalirkan sungai intelijen ke sawah lain. Tiba-tiba, Sang Jenderal menjadi petani di ladang yang kekurangan air. 4. Menciptakan kompetitor baru munculnya, Try Sutrisno, Feisal Tanjung, Edi Sudrajat, dan beberapa jenderal lainya, “lumayan-loyal-tidak-terlalu-kritis” dipromosikan. Secara teori elite: “fragmentation of power blocs.” Maka ada istilah: “Kalau satu singa terlalu kuat, ciptakan tiga singa baru, lalu buat mereka bingung siapa sebenarnya pemimpin padang rumput.” 5. Sanksi Moral—Teknik Mistik Jawa dalam Birokrasi Moderen Soeharto tidak mencaci. Dia hanya menggumam: “ABRI harus netral.” Dalam budaya birokrasi Orde Baru, gumaman Soeharto setara dengan hukuman administratif tingkat akhir.
Elegansi Kekuasaan: “Mengapa Soeharto Tidak Butuh Kekerasan untuk Menang?” Soeharto tidak suka konfrontasi terbuka. Bukan karena dia lemah—tetapi karena baginya, konflik adalah pengganggu suasana batin. Oleh karena itu, strategi Soeharto bersifat: -sunyi (tidak menciptakan martir), halus (menggeser, bukan melabrak), efektif (tokoh kuat kehilangan pengaruh tanpa kehilangan jabatan secara brutal), -teaterikal (semuanya tampak wajar, seperti proses alam).
Dalam bahasa akademik: “authoritarian resilience via elite pacification.”. Dalam bahasa lain: Soeharto menang tanpa harus menaikkan volume suara. Sang Jenderal yang tersingkir tanpa ditembak. Ironisnya, Sang Jenderal bukan “dipecat”—dia diposisikan ulang. Itu istilah halus. Seperti memindahkan Harimau dari hutan ke kebun binatang sambil mengatakan; “Ini demi kenyamanan bersama.” Pada akhirnya, tidak dihancurkan, hanya dijauhkan dari pusat gravitasi.
Kekuasaan Soeharto tidak kasar—justru terlalu halus. Jika ada pelajaran akademik dari gaya politik Soeharto, maka itu adalah: “Dalam otoritarianisme moderen, kekuasaan terbaik adalah yang bekerja tanpa terlihat bekerja.” Soeharto berhasil: Tidak membuat konflik elite, tidak menggunakan kekerasan pada internal militer, tidak menciptakan martir, tetapi tetap mempertahankan dominasinya selama tiga dekade. Sementara Sang Jenderal menjadi contoh ilmiah—dan sedikit tragis—tentang bagaimana aktor paling kuat pun bisa ditarik dari panggung tanpa perlu tepuk tangan, tanpa tirai, bahkan tanpa musik latar.
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director Hiawatha Institute
Editor: Jufri Alkatiri