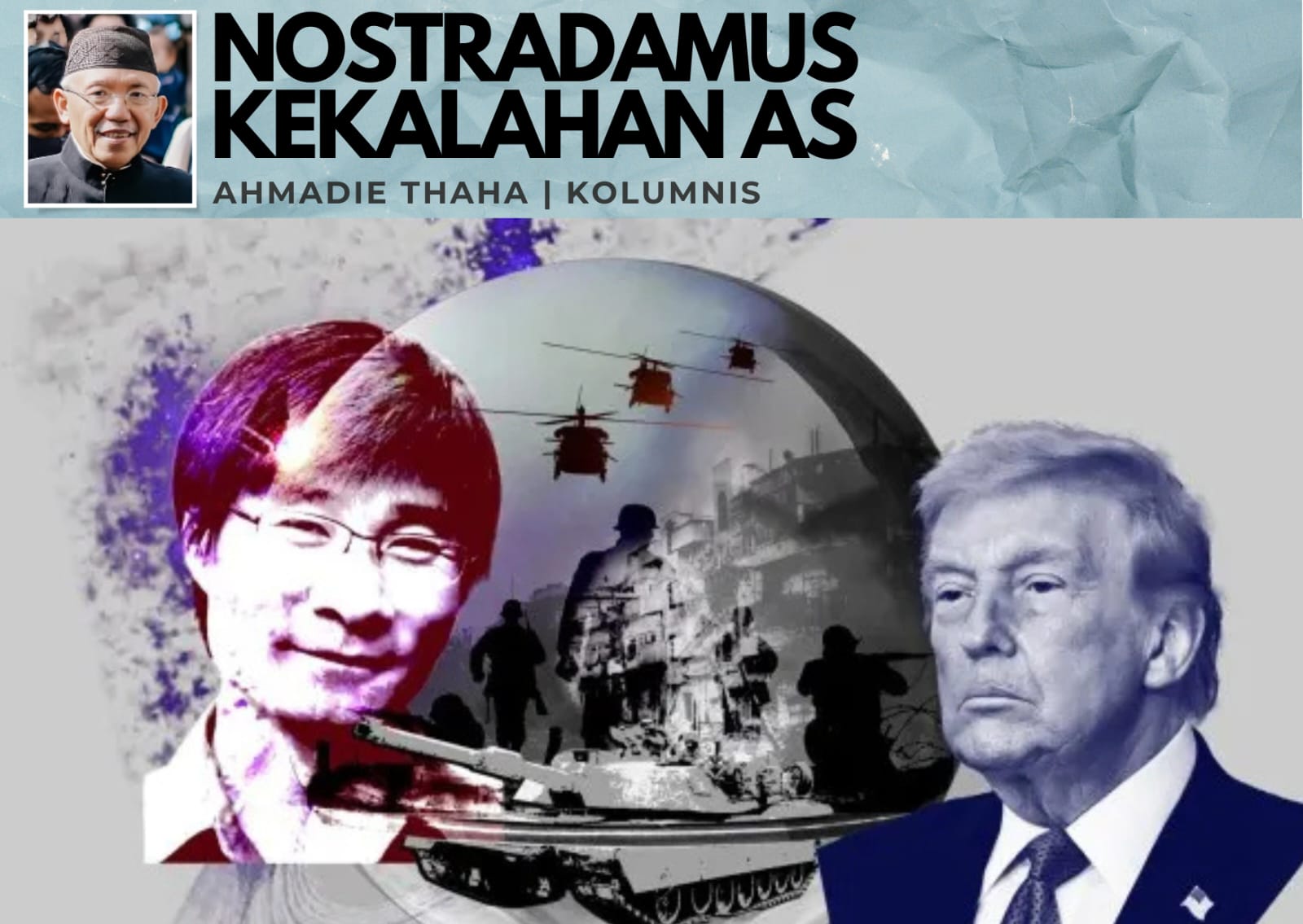Oleh: Benz Jono Hartono*
Bencana alam di Sumatera, entah gempa besar, Tsunami, banjir bandang, atau letusan gunung, selalu menghadirkan dua tragedi sekaligus, tragedi alam dan tragedi tata kelola negara. Mak bagaimana bila almarhum Jenderal Besar Purnawirawan TNI Soeharto masih hidup dan menjabat Presiden Republik Indonesia saat bencana besar melanda Sumatera hari ini? Pertanyaan ini bukan nostalgia, melainkan alat bedah sejarah. Dia memaksa kita membandingkan dua rezim, Orde Baru yang otoriter namun terpusat, dan era Pasca-reformasi yang demokratis namun terfragmentasi.
Dalam imajinasi ini, begitu laporan awal masuk bencana alam Sumatera, Soeharto tidak akan memulai dengan konferensi pers panjang, klarifikasi narasi, atau debat istilah — yang terjadi kemungkinan besar adalah instruksi satu arah: ABRI turun. Gubernur tanggung jawab. Menteri PU berangkat hari ini.Tidak ada alasan. Pada era Orde Baru, bencana diperlakukan sebagai ancaman stabilitas nasional, bukan sekadar urusan kemanusiaan. Karena itu, penanganannya bersifat militeristik, cepat, rapi, dan bila perlu keras. Bandingkan dengan Pasca-reformasi, rapat lintas kementerian, koordinasi pusat daerah yang tersendat, ego sektoral, kepala daerah menunggu anggaran, menteri menunggu sorotan kamera. Bencana hari ini sering kali lebih dulu viral sebelum benar-benar ditangani.
Di bawah Soeharto, ABRI bukan hanya alat pertahanan, tetapi alat negara itu sendiri. Dalam imajinasi ini, Sumatera akan dibagi ke dalam sektor-sektor operasi: Koramil sebagai pusat logistik, Kodam sebagai komando distribusi, Pangdam bertanggung jawab langsung ke Presiden, tidak ada debat tentang pelanggaran HAM dalam konteks darurat. Tidak ada tarik-uluran kewenangan sipil militer. Negara hadir secara fisik, massif, dan mendominasi. Di era Pasca-reformasi, sering: menunggu permintaan resmi kepala daerah, terikat prosedur, dipuji di media, tetapi dibatasi secara struktural, akibatnya, negara terlihat hadir tetapi tidak selalu berdaulat penuh atas situasi daruratnya sendiri.
Logistik Negara Menguasai Distribusi vs Negara Mengelola Proposal. Dalam Orde Baru: Gudang Bulog dibuka, beras didistribusikan tanpa tender, truk militer bergerak tanpa birokrasi, korban mungkin tidak diberi pilihan, tetapi mereka diberi makan. Pasca-reformasi: Bantuan datang dari NGO, proposal beredar, donasi dikumpulkan, distribusi sering tidak merata. Ironinya, negara justru menjadi koordinator bantuan swasta, bukan aktor utama. Negara hadir sebagai panitia, bukan sebagai pemilik otoritas.
Media dikendalikan Negara vs Negara dikendalikan opini. Jika Soeharto masih hidup, pemberitaan bencana Sumatera akan: dibatasi, disederhanakan, difokuskan pada “kehadiran negara”. Tidak ada tayangan korban berhari-hari menangis di televisi. Bukan karena negara lebih manusiawi, tetapi karena negara tidak mau terlihat lemah. Hari ini, negara justru: reaktif terhadap opini public, takut viral, takut diserang buzzer oposisi, takut dicap gagal. Akibatnya, kebijakan sering dibuat bukan untuk korban, tetapi untuk persepsi.
Jangan keliru — Orde Baru bukan tanpa korupsi, tetapi dalam konteks bencana: Korupsi cenderung terpusat, tidak gaduh, tidak saling bongkar. Pasca-reformasi:dana bencana dikorupsi berjamaah, pejabat saling lapor, KPK turun setelah korban lama menderita. Korupsi hari ini bukan hanya merugikan negara, tetapi memperpanjang penderitaan korban secara struktural.
Pembangunan Pasca-bencana cepat dan seragam vs lambat dan berdebat. Dalam Orde Baru: Rumah dibangun cepat, seragam, minim partisipasi warga Tapi selesai. Pasca-reformasi: artisipasi publik, diskusi desain, sengketa lahan, anggaran direvisi. Hasilnya jauh lebih lambat, sementara korban tidak bisa menunggu matang. Antara Efektivitas Otoriter dan Demokrasi yang Belum Dewasa ini adalah cermin terhadap Orde Baru, apalagi legitimasi otoritarianisme. Ini adalah cermin keras bagi Indonesia pasca Reformasi.
Soeharto, dalam imajinasi ini: cepat, tegas, tidak banyak bicara, tidak peduli citra, sebaliknya, Indonesia hari ini: bebas, demokratis, transparan — namun sering gagap saat negara dituntut bertindak cepat dan tegas. Mengapa setelah Reformasi, negara justru sering kehilangan daya komando ketika rakyatnya sangat membutuhkan? Dan mungkin, di situlah ironi terbesar republik ini.
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director Hiawatha Institute
Editor: Jufri Alkatiri