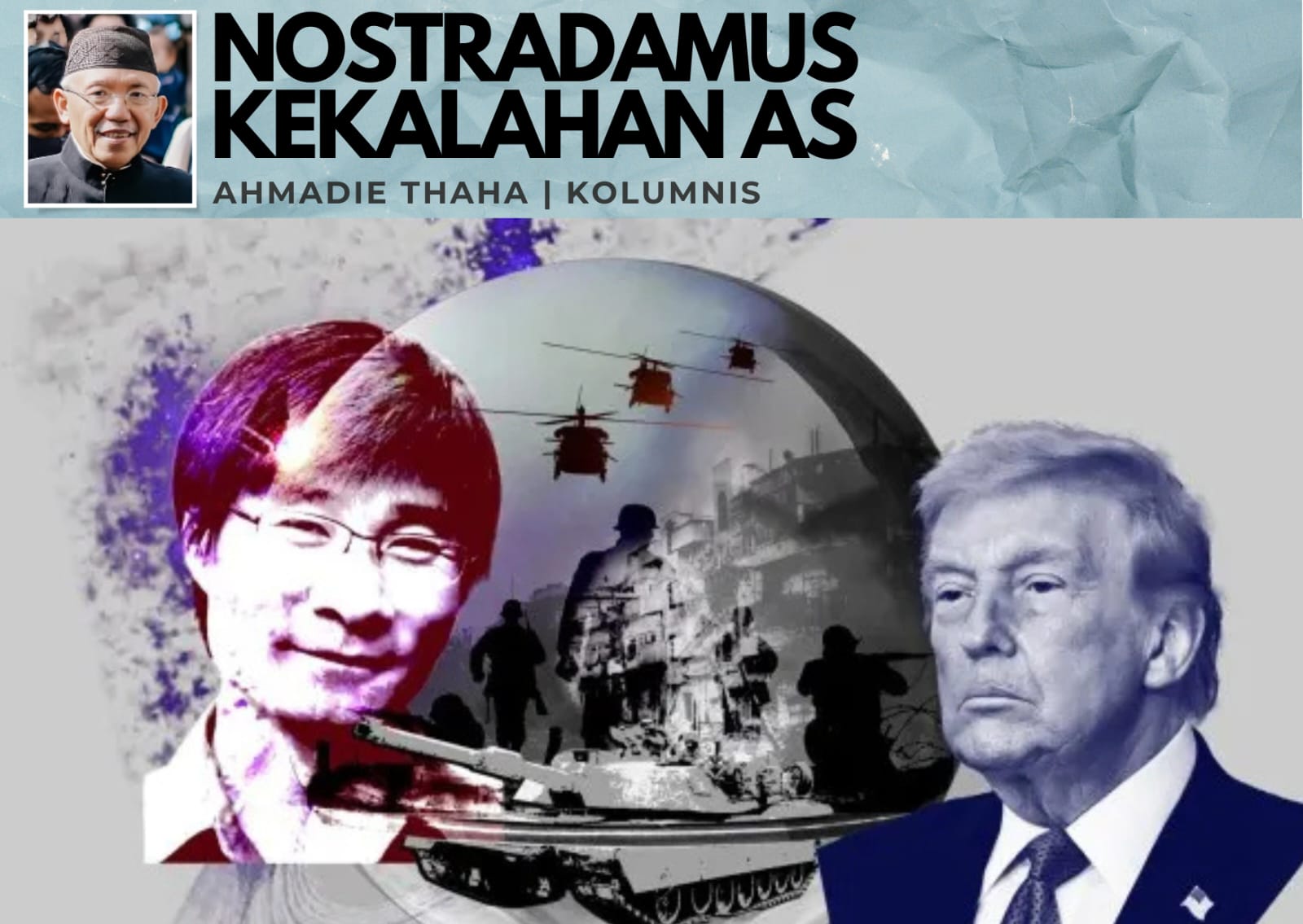Oleh: Merdy Sofansyah*
Agaknya ada sesuatu yang janggal ketika urusan yang biasanya disampaikan lewat memo, rapat tertutup, dan kalimat yang hemat — justru harus lahir sebagai video di media sosial. Seolah negara sedang mengetuk pintunya sendiri, lalu tidak ada yang membukakan.
Dino Patti Djalal berbicara dan menahan diri dengan cara seorang alumnus rumah besar diplomasi. Menlu Sugiono disapa dengan sopan, posisi diri ditegaskan sebagai orang yang lama berkubang di lumpur perundingan, lalu kritik disampaikan dengan bungkus dukungan. Ada metafora yang dipilih agar tidak melukai, ada peringatan yang dibuat terdengar seperti nasihat. Kemlu, katanya, seperti Ferrari. Mesin hebat, talenta banyak. Tapi Ferrari tidak berjalan sendiri. Ia butuh pengemudi yang hadir, fokus, dan mengarahkan.
Kalimat yang paling membuat dahi mengernyit bukan soal Ferrari. Melainkan alasan mengapa pesan itu harus dikirim lewat media sosial. Dino bilang jalur komunikasi efektif buntu. Sudah dicoba surat, telepon, WhatsApp, permohonan pertemuan. Tidak ada respons. Maka dipilih jalan paling vulgar dalam negara modern: jalan yang tidak memerlukan protokoler, tidak memerlukan sekretariat, tidak memerlukan disposisi. Bantuan publik diminta. Lampu dinyalakan di ruang gelap, berharap ada yang merasa silau dan akhirnya menoleh.
Di titik itulah cerita berubah. Kritik yang pada awalnya tampak seperti urusan internal lembaga, mendadak menjadi persoalan tata kelola negara. Karena jika seorang yang merasa bagian dari ekosistem diplomasi, dengan segala kesantunan dan jejaringnya, sampai harus berteriak di alun-alun digital, pertanyaannya tidak lagi “kritiknya benar atau tidak.” Pertanyaannya lebih dasar, lebih menakutkan: mengapa pintu yang semestinya ada, pintu yang semestinya bekerja, pintu yang semestinya menjadi jalur koreksi, bisa terasa tertutup rapat.
Lalu datang tanggapan Natalius Pigai di X. Bukan Menlu, bukan juru bicara Kemlu, melainkan menteri lain yang memilih ikut masuk ke gelanggang. Ia menulis bahwa kritik Dino “zonk.” Ia menambahkan kisah perjumpaan di luar negeri, tentang diplomat dan duta besar yang ditemui, yang memuji bahwa Indonesia kini dipandang lebih tinggi. Kesimpulannya tegas: Menlu Sugiono berprestasi dan luar biasa, bahkan lebih baik dibanding masa ketika Dino pernah memimpin (Wamen). Setelah itu nada berubah jadi lebih tajam. Dino dituding menunjukkan arogansi elit. Diplomasi disebutnya sekadar permainan.
Di situ terasa dua jenis bahasa negara yang saling bertabrakan. Yang satu bahasa institusi, yang memilih rapi, memilih tertib, memilih menahan diri. Yang satu lagi bahasa medan sosial media, yang cepat, yang memukul dengan label, yang membangun kemenangan bukan dari data melainkan dari suasana. Kemurkaan publik wajar muncul bukan karena tokoh ini atau tokoh itu. Kemurkaan muncul karena kebiasaan yang diam-diam dinormalisasi: negara yang urusan seriusnya dikelola seperti perang komentar.
Bayangkan sebentar apa yang sedang terjadi. Di satu sisi ada kritik yang, secara implisit, menyatakan mesin koordinasi di dalam organisasi tidak berjalan. Ada cerita tentang kurangnya arahan strategis, rapat yang tertunda, semangat yang menurun, komunikasi yang macet. Setuju atau tidak, bentuk kritik itu, jika ingin dibantah, harus dibantah dengan sesuatu yang setara: penjelasan yang terang, indikator yang jelas, bantahan yang bisa diuji. Karena inti kritik itu bukan soal selera, melainkan soal tata kelola.
Namun yang muncul justru testimoni dan cap. “Sedang di Qatar,” “bertemu dubes,” “mereka bilang begini.” Lalu selesai. Padahal negara bukan grup chat keluarga yang cukup ditenangkan dengan kalimat, “tenang, semuanya baik.” Negara adalah mesin besar yang perlu bukti kerja, bukan sekadar kesaksian yang tak bisa diverifikasi.
Bisa saja cerita itu benar. Bisa juga kekhawatiran Dino akurat. Namun persoalan utamanya bukan memilih siapa yang benar. Persoalan utamanya adalah cara negara menata ruang koreksi. Ketika kritik diubah menjadi urusan loyalitas, ketika argumen diganti label “elit arogan,” publik akhirnya dipaksa memilih kubu, bukan menilai substansi. Dan ketika publik dipaksa memilih kubu, yang menang bukan kebenaran. Yang menang adalah kebisingan.
Masalah pertama dalam kisah ini adalah soal katup. Dalam sistem yang sehat, katup itu ada. Ia mengatur tekanan. Ia memberi jalan keluar sebelum ledakan. Di pemerintahan, katup itu berbentuk mekanisme umpan balik yang nyata, bukan sekadar bagan organisasi. Ada jadwal koordinasi yang pasti, ada kanal masukan yang direspons, ada ritme kepemimpinan yang terukur, ada ruang dialog dengan pemangku kepentingan yang tidak bergantung mood, tidak bergantung viral.
Begitu katup itu macet, tekanan mencari jalan sendiri. Ia keluar lewat Instagram, lewat X, lewat potongan video, lewat narasi yang liar. Dan pada saat itu, diplomasi yang seharusnya berjalan dengan presisi, mulai berjalan dengan emosi. Satu kalimat bisa dibaca negara lain. Satu label bisa menjadi bahan framing. Satu miskomunikasi bisa melahirkan kebijakan yang salah arah.
Masalah kedua adalah soal bahasa negara. Terdengar remeh, tetapi dalam politik, bahasa adalah kebijakan versi awal. Cara menteri bicara adalah cara negara memandang dirinya sendiri. Jika seorang menteri merasa wajar menutup kritik dengan kata “zonk,” lalu menambahkan tuduhan arogansi elit, itu tanda standar diskursus sedang turun. Dan ironisnya, yang paling dirugikan bukan tokoh yang dikritik atau yang mengkritik. Yang dirugikan adalah publik, karena publik kehilangan pembeda antara klarifikasi resmi dan opini pribadi yang memakai seragam negara.
Ada ironi lain. Pigai ingin membela martabat diplomasi Indonesia, ingin menunjukkan Indonesia kini “dipandang.” Tetapi cara membelanya justru meminjam gaya yang membuat kita tampak kecil. Diplomasi bukan pertandingan teriak paling kencang. Diplomasi bukan permainan. Diplomasi adalah kerja sunyi yang dampaknya nyata: perlindungan warga di luar negeri, negosiasi ekonomi, mitigasi krisis, posisi Indonesia di forum multilateral. Menyebutnya permainan mungkin terasa berani di lini masa, tetapi di dunia nyata, kalimat seperti itu mengecilkan makna pekerjaan yang sedang dibela.
Kalau benar-benar berpihak pada publik, pertanyaannya sederhana. Mengapa kanal komunikasi bisa dianggap buntu sampai kritik harus diumumkan di ruang publik. Mengapa urusan strategis dijawab dengan label dan testimoni, bukan dengan penjelasan dan data. Mengapa kabinet tampak seperti saling membela lewat postingan, bukan menyelesaikan problem lewat mekanisme. Solusi harus ditarik ke sistem, bukan ke karakter. Karakter mudah disalahkan, besok berganti orang, drama yang sama terulang.
Negara butuh disiplin yang bisa diuji. Kemlu butuh ritme koordinasi yang jelas dan konsisten, sehingga perwakilan tahu arah dan publik tahu garis besar kebijakan tanpa membocorkan rahasia. Pemerintah butuh etika komunikasi lintas kementerian, agar pembelaan pada kolega kabinet tidak berubah menjadi perkelahian narasi yang membakar kepercayaan. Publik butuh penjelasan rutin, bukan hanya foto kegiatan, bukan hanya klip tanpa substansi, melainkan penalaran mengapa Indonesia mengambil posisi A, mengapa menolak B, dan apa konsekuensinya bagi warga.
Kalau semua itu ada, kritik tidak perlu mengemis perhatian lewat viral. Jika ada kesalahan, ia dikoreksi di dalam, dengan cepat. Jika ada fitnah, ia dibantah di luar, dengan rapi. Jika ada kebijakan, ia dijelaskan, dengan hormat. Publik tidak perlu memilih tokoh. Publik cukup menuntut mekanisme.
Karena pada akhirnya, publik tidak butuh tontonan siapa yang lebih senior atau siapa yang lebih keras membela. Publik butuh kepastian bahwa negara punya telinga yang bekerja, mulut yang bertanggung jawab, dan tangan yang mampu memperbaiki. Kalau tidak, negeri ini akan terus bergerak hanya setelah ramai. Dan negara yang hanya bergerak setelah ramai bukan negara yang kuat. Itu negara yang ketergantungan pada algoritma.
*Wakil Ketua I Bidang Multimedia dan IT PWI Pusat, Jurnalis Senior, dan Alumnus Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya
Editor: Jufri Alkatiri