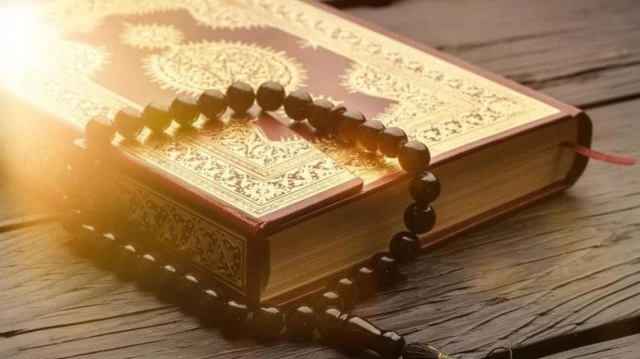Oleh: Anwar Rosyid Soediro*
2. Para Pemikiran Penerus Hanbali
Para ulama Hanbali pada abad-abad berikutnya mengambil pendekatan yang agak berbeda dalam menyikapi antropomorfisme — yang tampak ketika mencoba mengartikulasikan tauhid. Ungkapan yang paling sering ditemui dalam wacana Hanbali adalah bi-lā kayf (tanpa modalitas), di mana seseorang menegaskan realitas sifat-sifat ilahi tanpa menentukan “bagaimana” atau “modalitasnya” sebuah pendekatan yang dapat disebut “afirmasi amodal”.
a. Qādī Abū Yaʿlā b. al-Farrāʾ (w. 458/1066)
Abu Ya’la mengadopsi terminologi Kalām untuk mengartikulasikan akidah Hanbali dengan cara afirmasi amodal. Sebagaimana kaum Asy’ari dan Māturīdī, Abū Ya’lā menegaskan bahwa Tuhan memiliki “sifat-sifat entitas” (ṣifāt ma’nawīya) yang kekal: “’Dia, Maha Suci Allah, Maha Mengetahui melalui satu pengetahuan, Maha Kuasa melalui satu daya, Maha Hidup melalui satu kehidupan, Maha Berkehendak melalui satu kehendak, dan Maha Berfirman melalui satu ucapan”; semua sifat-sifat kekal ini saling berbeda dan berada dalam Zat-Nya (Abū Ya’lā 1974: 49–50).
Tuhan juga memiliki sifat-sifat tindakan, seperti menyediakan, menciptakan, atau menganugerahkan nikmat, yang kekal meskipun tindakan-tindakan itu sendiri bersifat temporal (Abū Ya’lā 1974: 44–45). Abū Ya’lā juga mendukung rumusan Kullābī: “Sifat-sifat Tuhan bukanlah Sang Pencipta dan bukan pula yang lain selain Dia” (1974: 46). Abū Yaʿlā menegaskan realitas amodal dari dua mata Tuhan, wajah-Nya, dua tangan-Nya, tulang kering-Nya, kaki-Nya, tungkai-Nya, duduk-Nya di atas Singgasana, turun-Nya, arah-Nya, dan wujud atau konfigurasi-Nya.
Dalam pandangannya, dua mata Tuhan adalah atribut ilahi (ṣifatān) yang ditambahkan (zāʾida) pada penglihatan dan penglihatan Tuhan, tetapi bukan organ atau anggota tubuh. Demikian pula, wajah Tuhan adalah atribut yang ditambahkan pada Esensi Tuhan.
Dua tangan Tuhan tidak secara metaforis merujuk pada karunia atau kekuatan Tuhan, melainkan, keduanya merupakan dua atribut ilahi yang esensial. Tulang kering, kaki, dan tungkai Tuhan semuanya merupakan atribut ilahi yang ditambahkan dan tidak merujuk pada anggota tubuh fisik.
Duduknya Tuhan adalah atribut dari Esensi Ilahi yang dengannya Tuhan secara kekal menggambarkan Diri-Nya; tetapi itu tidak merujuk pada duduk jasmani atau kontak fisik. Turunnya Tuhan setiap malam tidak melibatkan gerakan fisik apa pun dan harus dianggap serupa dengan manifestasi diri-Nya (tajallī) kepada Musa (Mūsā) di Gunung Sinai.
Tuhan dapat digambarkan dengan “keberadaan” (aynīya), yang merupakan arah di atas langit. Tuhan juga memiliki wujud (ṣūra) yang disaksikan Nabi dalam sebuah penglihatan, tetapi wujud tersebut berbeda dari wujud lainnya (Abū Yaʿlā 1974: 51–58). Secara keseluruhan, Abū Yaʿlā mengambil pendekatan amodal (ithbāt bi-lā kayf) yang afirmatif terhadap atribut-atribut Tuhan, termasuk deskripsi antropomorfik-Nya.
b. Ibnu Qudāma
Ibnu Qudama ulama Hambali mengambil pendekatan yang agak berbeda terhadap sifat-sifat Tuhan. Dia melarang Ilmu Kalam sepenuhnya, dan justru mengikuti metode yang dia anggap sebagai jalan para leluhur saleh (al-salaf): Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang telah Dia jelaskan dalam ayat-ayat-Nya, wahyu-Nya, atau melalui lisan Rasul-Nya, tanpa menambahi, mengurangi, melampaui, menjelaskan, dan menafsirkannya secara kiasan dengan sesuatu yang bertentangan dengan maknanya yang tampak (ẓāhirihā). Sifat-sifat-Nya tidak ada kemiripan (tashbīh) dengan makhluk, dan tidak ada pula deskripsi tentang makhluk-makhluk yang diciptakan secara temporal. (Ibn Qudāma 2002: 11–12).
Ibn Qudāma mendekati deskripsi kitab suci tentang hal-hal seperti tangan, mata, turunnya Tuhan, dll. melalui metode yang dikenal sebagai tafwīḍ al-maʿnā (menyerahkan makna kepada Tuhan). Dalam pendekatan ini, seseorang hanya menegaskan firman-firman Tuhan yang diwahyukan dalam bahasa Arab, tetapi mengaku tidak mengetahui makna sebenarnya, menyerahkan pengetahuan tentang makna yang dimaksudkan kepada Tuhan: “Adapun iman kita kepada ayat-ayat dan riwayat-riwayat kenabian tentang sifat-sifat [ilahi], adalah beriman murni kepada ungkapan-ungkapan lisan yang tidak ada keraguan dalam kesahihan dan kebenarannya, dan Dia yang menyampaikannya lebih mengetahui maknanya. Maka, kita beriman kepada mereka sesuai dengan makna yang telah dimaksudkan oleh Tuhan kita, Yang Maha Agung” (Ibn Qudāma 1990: 59).
Pendekatan Ibn Qudāma adalah apophatisisme amodal (Kars 2019) di mana penanya mengakui ketidaktahuannya tentang makna sejati dari banyak sifat ilahi, sementara pengetahuannya terbatas pada nama dan kata: Adalah mungkin untuk beriman kepada sifat-sifat tersebut tanpa mengetahui maknanya, karena iman dengan ketidaktahuan adalah benar (Ibn Qudāma 1990: 52).
c. Ibnu Taimiyah
Tradisi Pergerakan Hanbali menampilkan perkembangan lebih lanjut untuk mengartikulasikan dan mengonseptualisasikan doktrin tauhid mereka. Mungkin yang paling terkenal di antara Hanbali pasca-klasik adalah Ibnu Taimiyyah (w. 728/1328) (lihat Hoover 2007). Meskipun analisis lengkap tentang kontribusinya masih di luar cakupan artikel ini, cukuplah untuk mengatakan bahwa pengaruhnya terhadap gerakan Hanbali dan Salafi selanjutnya tidak dapat diremehkan.
Ibnu Taimiyyah menggunakan Teologi Kalām dan wacana-wacana filsafat untuk mendukung versi teologi Hanbalī-nya sendiri. Mengenai sifat-sifat Tuhan, Ibnu Taimiyyah menolak taʾwīl dan tafwīḍ al-maʿnā (menyerahkan makna kepada Tuhan); sebaliknya, dia menjunjung tinggi penegasan amodal (ithbāt bi-lā kayf) tentang sifat-sifat antropomorfik Tuhan, termasuk kedua tangan-Nya, mata, wajah, duduk di atas Singgasana, dan turun-Nya.
Berbeda dengan tradisi Kalām, Ibnu Taimiyyah membedakan antara sifat-sifat esensial Tuhan (hidup, pengetahuan, kekuasaan, dan kehendak-Nya) dan sifat-sifat sukarela Tuhan; yang terakhir adalah tindakan-tindakan ilahi yang tidak diciptakan namun bersifat temporal yang dilakukan Tuhan dengan kekuasaan dan kehendak-Nya, seperti tindakan-Nya berbicara, mendengar, melihat, mencintai, mengasihi, menciptakan, marah, duduk, datang, dan turun.
Sifat atau tindakan sukarela Tuhan terjadi secara temporal (ḥādith), tetapi tetap berada dalam Dzat Tuhan setelah terjadi, artinya tindakan Tuhan bersifat temporal, bergantung pada Tuhan namun tidak diciptakan (Hoover 2010).
Ibnu Taimiyyah memahami Tuhan sebagai entitas yang meluas secara spasial yang mengelilingi Kosmos dengan secara harfiah berada “di atas” dunia secara spasial; hal ini berbeda dengan konsepsi Kalām tentang Tuhan yang melampaui segala arah spasial (Hoover 2022). Akhirnya, Ibnu Taimiyyah menolak praktik Muslim yang popular yang mengarahkan permohonan syafaat (istighātsah) kepada Nabi dan para wali. (bersambung)
*Pemerhati Keagamaan, Filosof, dan Alumni Fakultas Teknik Pertanian UGM Yogyakarta
Editor: Jufri Alkatiri