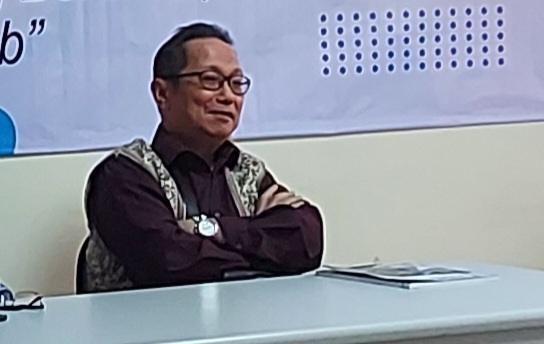Oleh: Benz Jono Hartono*
I. Peristiwa Awal (abad 14 – 15). Tahun 1357 — Peristiwa Bubat (versi naskah lokal). Sumber awal yang menyebut Bubat hanya dua: 1. Kidung Sunda (Puisi Jawa era Majapahit akhir – abad 15/16). 2. Pararaton (pertengahan abad 15/16). Keduanya, sangat singkat, tidak seragam, tidak menyebut konflik etnis, tidak menggambarkan kebencian Sunda–Jawa, hanya mencatat peristiwa politik: Rombongan Sunda datang ke Majapahit → terjadi konflik di Bubat → tewasnya keluarga Sunda. Tidak ada dokumen Sunda yang mencatat tragedi ini secara lengkap. Tidak ada bukti permusuhan setelahnya.
II. Sebelum Kolonial Narasi Bubat tidak menjadi isu besar — 1500–1700 Kerajaan Sunda runtuh 1579. Sunda masuk wilayah Mataram, lalu VOC (abad 17). Tidak ada pemberontakan atau larangan adat terkait Jawa karena Bubat. Hubungan Sunda–Jawa normal dan stabil. Kesimpulan:Tidak ada bukti luka sejarah antar etnis sebelum Belanda membingkai ulang narasi Bubat.
III. Awal Masa Kolonial — pengumpulan naskah (1770–1850). Awal abad kolonial, ilmuwan VOC mulai tertarik pada naskah Jawa. 1778 — Bataviaasch Genootschap didirikan. Lembaga inilah yang mengumpulkan ribuan naskah Nusantara untuk diteliti dan diseleksi sesuai kepentingan kolonial. Tahun 1800–1850 — VOC/BH mendata manuskrip terkait Majapahit. Nama-nama awal: 1. Nicolaus Engelhard, 2. Raffles (1811–1816), dan 3. J.F.G. Brumund. Raffles hanya menyebut Majapahit secara umum; tidak menyoroti Bubat sebagai konflik Sunda–Jawa. Ini menunjukkan Bubat belum dianggap isu pada masa itu.
IV. Era Filologi Kolonial — Naskah Diterjemahkan dan Dibingkai Ulang (1850–1920). Inilah periode terpenting dalam “penciptaan” tragedi Bubat sebagai trauma yang dibesar-besarkan. 1850–1890 — Pleyte, Holle, & Brandes menyusun filologi Sunda–Jawa K.F. Holle (ahli bahasa Belanda) dan C.M. Pleyte (kurator Museum Batavia) mulai mengumpulkan naskah Sunda dan Jawa, termasuk: 1. Kidung Sunda, 2. Pararaton, 3. naskah babad Jawa. Mereka menerjemahkan dan menulis komentar panjang yang: 1. membingkai Bubat sebagai konflik etnis. 2. menonjolkan Jawa sebagai agresor, Sunda sebagai korban. 3. memberi narasi emosi (penghinaan, dendam, kehormatan)
Sumber asli Nusantara tidak pernah menulis sedramatis itu. 1881 — Brandes mempublikasikan terjemahan Pararaton. Brandes memberi catatan bahwa: Gajah Mada menjadi “akar permusuhan Sunda–Jawa.” Tragedi itu “titik hitam hubungan dua bangsa.” Pendapat ini murni interpretasi kolonial, tidak berasal dari naskah Nusantara.
1890–1910 — Kern dan Knebel memperkuat narasi Bubat. P.J. Knebel menafsirkan Kidung Sunda dengan dramatis. H. Kern menekankan unsur “pengkhianatan Jawa.” Keduanya memperluas narasi sehingga masuk ke kajian sejarah kolonial.
V. Kolonial Menyebarkan “Sejarah Resmi” ke Masyarakat (1900–1942)
Tahun 1900–1930 — Pendidikan Hindia Belanda. Melalui sekolah HIS, MULO, dan AMS: 1. Sejarah versi Belanda diajarkan ke pribumi. 2. Narasi Bubat versi kolonial masuk buku pelajaran, etnografi, dan bacaan populer. Dampaknya: 1. Generasi terdidik Sunda mulai memandang Bubat sebagai kehinaan budaya. 2. Generasi Jawa melihatnya sebagai “kontroversi sejarah.” 3. Pecah belah halus mulai bekerja. 1920–1940 — Novel dan publikasi kolonial mempopulerkan narasi Bubat. Banyak buku yang menulis Bubat memakai pola “tragis–etnis,” misalnya: 1. kumpulan cerita Sunda (Balai Poestaka). 2. roman berlatar Majapahit. 3. Publikasi etnografi colonial. Narasi inilah yang paling berpengaruh hingga era modern.
VI. Pasca-kemerdekaan — Narasi Kolonial Tetap Digunakan (1945–1990). 1. 1950–1980 — Buku sejarah Indonesia mewarisi versi Belanda. 2. Sejarawan awal Indonesia masih mengacu pada: a. terjemahan kolonial. b. kerangka filologis Belanda. c. interpretasi Brandes–Kern–Knebel. Akhirnya, versi kolonial menjadi mainstream, karena dianggap “ilmiah.” 1985 — Novel & film populer mengulang narasi konflik Sunda–Jawa. Cerita rakyat Sunda versi Balai Pustaka. Kisah-kisah “Dayang Sumbi–Siliwangi–Pitaloka”. Narasi ini mempopulerkan stereotip etnis (warisan kolonial).
VII. Era Moderen — Bubat Menjadi Alat Propaganda Identitas (2000–Sekarang). 1. 2000–2020 — Media sosial menghidupkan kembali konflik Sunda–Jawa. 2. Perdebatan online banyak menggunakan: a. kutipan naskah kolonial. b. interpretasi sejarah Belanda. c. dramatisasi novel abad 20. Padahal: Sumber asli Nusantara tidak pernah menunjukkan dendam etnis. a. 2014 — Film “Gajah Mada” dan kontroversi antar etnis. b. Kontroversi publik sebagian disulut oleh perbedaan versi sejarah yang berakar pada tafsir kolonial.
1. Peristiwa Bubat (1357) terjadi secara politik, bukan konflik etnis. 2. Tidak ada permusuhan Sunda–Jawa selama 400 tahun sesudahnya (1357–1750). Tidak ada bukti sejarah dendam etnis. 3. Filolog kolonial Belanda (1850–1920) merekayasa, membesar-besarkan, dan membingkai ulang tragedi Bubat. 4. Narasi kolonial disebarkan melalui pendidikan dan buku sekolah (1900–1940) sehingga melekat dalam pikiran pribumi. 5. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sejarah versi Belanda karena dianggap “ilmiah” dan tanpa verifikasi ulang sumber asli. 6. Konflik Sunda–Jawa modern adalah efek panjang dari rekayasa kolonial.
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Director Executive Hiawatha Institute
Editor: Jufri Alkatiri