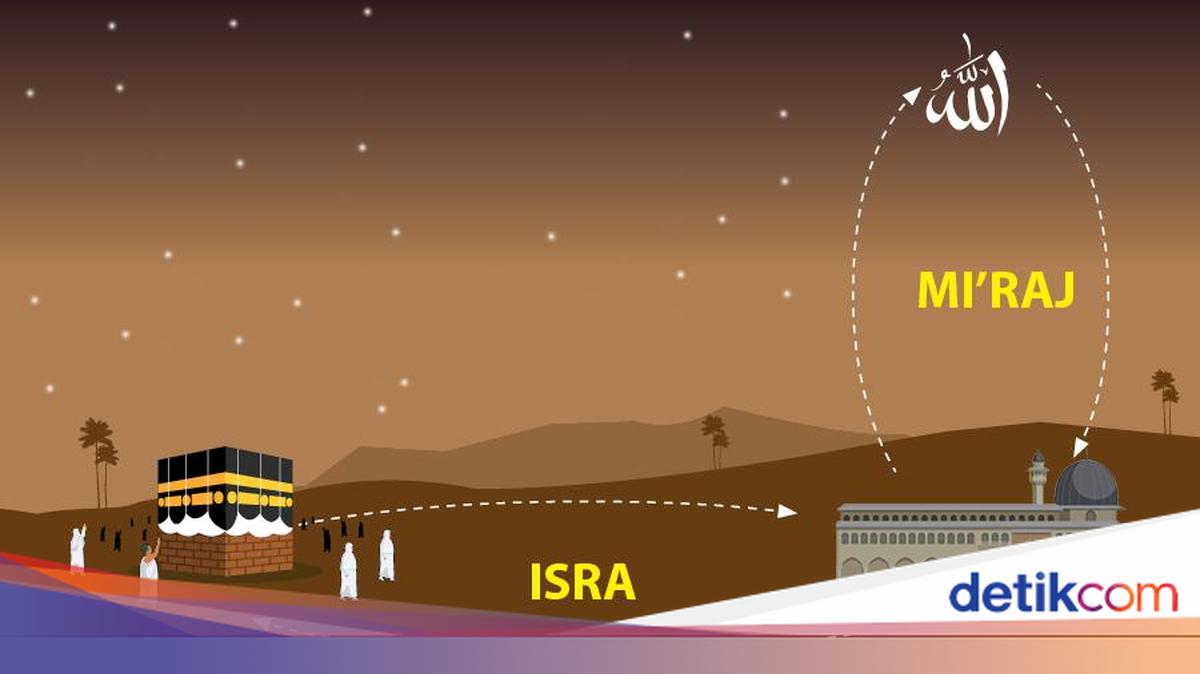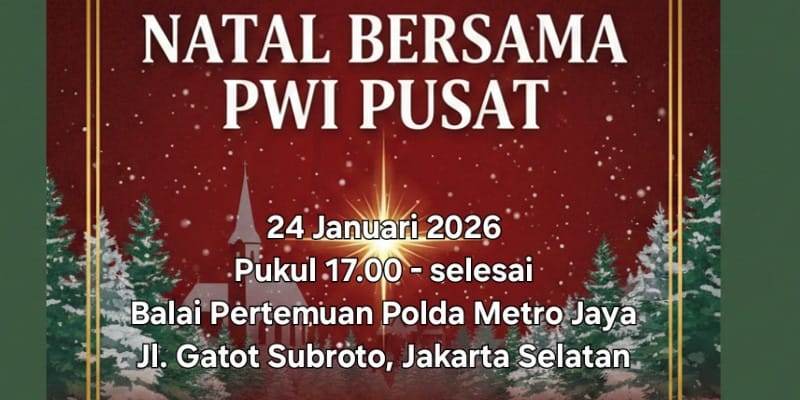Oleh: Prof. Dr. Murodi al-Batawi, MA*
Tulisan ini mencoba berusaha menganalisis Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati setiap 22 Oktober di Indonesia melalui pendekatan sosio-historis filosofis. HSN bukan hanya sekadar penanda tanggal, tetapi merupakan konstruksi sosial yang merepresentasikan narasi historis, nilai filosofis, dan identitas keagamaan dalam konteks nation-building. Melalui pendekatan sosio-historis. Selain itu, tulisan ini mencoba menelusuri akar historis penetapan HSN yang merujuk pada Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama tahun 1945.
Sementara melalui pendekatan filosofis, tulisan ini mengkaji makna mendalam di balik konsep santri dan relevansinya dengan filosofi kebangsaan Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa HSN berfungsi sebagai medium reaktualisasi peran santri sebagai agent of change, peneguh identitas keislaman yang moderat, serta penyatu relasi antara Islam dan nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22 Oktober Sebagai Hari Santri Nasional
Hari Santri Nasional (HSN), yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo, merupakan sebuah kebijakan negara yang memiliki muatan makna yang dalam dan kompleks. Secara permukaan, HSN merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi kaum santri dalam perjalanan sejarah bangsa. Namun, di balik itu, HSN adalah sebuah fenomena sosial-budaya yang dapat dibaca sebagai sebuah teks besar tentang relasi agama dan negara, rekonstruksi memori kolektif, dan formasi identitas keindonesiaan.
Tulisan ini berusaha mengurai lapisan-lapisan makna HSN dengan menggunakan pisau analisis sosio-historis dan filosofis. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk melacak akar peristiwa sejarah yang melatarbelakangi penetapan tanggal 22 Oktober, serta dampak sosial dari dikembangkannya narasi tersebut dalam kesadaran masyarakat kontemporer. Sementara pendekatan filosofis dipakai untuk menyelami esensi konsep santri dan nilai-nilai filsafat apa yang terkandung dalam peringatan HSN, khususnya dalam kaitannya dengan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Konstruksi Sosio-Historis: Dari Resolusi Jihad 1945 ke Hari Santri Nasional 2015
Latar belakang historis penetapan HSN pada 22 Oktober tidak dapat dilepaskan dari peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya. Resolusi ini merupakan seruan religius yang mewajibkan umat Islam, khususnya santri, untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajah Belanda yang membonceng Sekutu.
Resolusi Jihad menjadi pemicu spiritual dan moral bagi meletusnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pidato Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo tidak dapat dipisahkan dari atmosfer religius yang diciptakan oleh Resolusi Jihad tersebut.
Dengan demikian, narasi historis ini membangun sebuah historical claim bahwa kaum santri memiliki andil yang absolut dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia yang masih muda. Namun, selama puluhan tahun, narasi heroik ini cenderung terpinggirkan dalam historiografi nasional yang lebih dominan diwarnai oleh perspektif militer-sekuler. Penetapan HSN pada 2015, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai sebuah proses rekonstruksi dan reaktualisasi memori kolektif Negara, melalui kebijakannya, secara resmi mengakui dan mengintegrasikan peran sejarah kaum santri ke dalam narasi besar sejarah nasional. Ini adalah sebuah bentuk nation-building yang inklusif, di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya merasa terpinggirkan mendapatkan pengakuan simbolis.
Dari perspektif sosiologis, HSN juga menjadi alat konsolidasi identitas santri yang lebih luas. Istilah santri tidak lagi hanya merujuk pada siswa yang belajar di pesantren tradisional (salaf), tetapi juga meliputi muslim Indonesia yang mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, Islam yang moderat (wasathiyah), dan berkontribusi untuk bangsa. HSN dengan demikian menjadi medium untuk memperkuat identitas keislaman yang sejalan dengan cita-cita nasional.
Esensi Santri dan Filsafat Kebangsaan
Secara filosofis, konsep santri melampaui makna sosiologisnya sebagai sebuah kelompok masyarakat. Santri adalah sebuah entitas yang mengandung nilai-nilai filsafat hidup yang relevan dengan bangsa Indonesia.
Pertama Filsafat Ilmu Pengetahuan: Pesantren sebagai institusi utama kaum santri memiliki tradisi keilmuan (sanad ilmu) yang kuat. Dalam tradisi Turats ada proses pembelajaran Kitab Ta’lim Muta’allim seorang santri diajarkan untuk menghormati pengetahuan, guru (ta’dzim al-ustadz), dan proses pembelajaran sepanjang hayat (long life education). Nilai ini sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Kedua Filsafat Moral dan Etika: Dunia pesantren menekankan pada pembentukan akhlakul karimah (budi pekerti yang luhur). Seorang santri tidak hanya dinilai dari kepintarannya, tetapi dari integritas moral dan karakternya. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan (zuhud), tanggung jawab, dan sikap menghormati perbedaan (tawasuth, tawazun, tasamuh) merupakan fondasi karakter bangsa yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan modernitas.
Ketiga Filsafat Politik dan Kebangsaan: Sumpah setia kaum santri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila memiliki dasar teologis yang kuat. Frasa hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman) yang digaungkan oleh KH. Hasyim Asy’ari telah menjadi filosofi politik kaum santri.
Frasa ini memadukan secara dialektis antara nasionalisme dan religiositas. Cinta tanah air bukan sekadar emosi semata, tetapi merupakan ekspresi dari keimanan. Dalam perspektif ini, membela Indonesia sama halnya dengan membela agama. Ini adalah landasan filosofis yang sangat kokoh untuk menjaga keutuhan NKRI.
Hari Santri Nasional, dengan demikian, merupakan penegasan kembali (reaffirmation) dari filosofi hubbul wathan minal iman. Peringatan ini adalah momentum untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur kepesantrenan—seperti ketawadhuan, keilmuan, dan patriotisme—dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di abad ke-21.
Berdasarkan analisis sosio-historis filosofis, dapat disimpulkan bahwa Hari Santri Nasional adalah sebuah konstruksi sosial yang memiliki legitimasi historis yang kuat, berakar pada peristiwa Resolusi Jihad 1945. HSN bukanlah penciptaan sejarah baru, melainkan pengakuan negara terhadap narasi sejarah yang telah hidup di kalangan masyarakat santri.
Secara filosofis, HSN mengandung makna yang mendalam sebagai peneguh identitas keindonesiaan yang religius. Konsep santri membawa nilai-nilai filsafat yang esensial bagi pembangunan karakter bangsa, yaitu filsafat ilmu, moral, dan kebangsaan. Filsafat hubbul wathan minal iman menjadi jembatan yang menyatukan komitmen keagamaan dan nasionalisme, menjadikan santri sebagai pilar penting dalam menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan.
*Profesor Sejarah dan Peradaban. Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Jufri Alkatiri