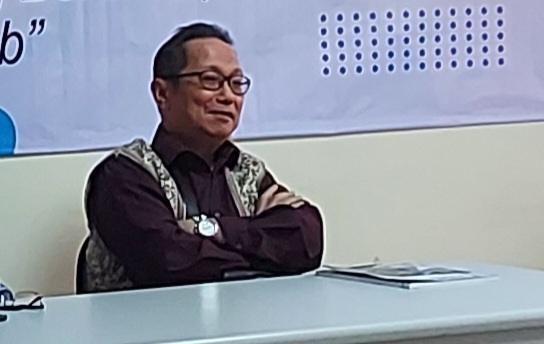Oleh: Kurniawan Zulkarnain*
Demokrasi, bagi Indonesia — bukan sekadar sistem politik, melainkan eksperimen sejarah yang masih terus belajar berdiri tegak di atas kaki sendiri. Demokrasi berjalan tertatih-tatih mengiringi perjalanan bangsa menuju usia dewasa. Demokrasi adalah tamu muda yang baru belajar sopan santun dalam rumah besar bernama Republik, karena kebaruannya, demokrasi sering kali disambut dengan rasa canggung, dianggap asing oleh sebagian, diterima setengah hati oleh yang lainnya
Dalam pergulatan panjang itulah, kita sering lupa bahwa demokrasi sesungguhnya tidak datang dari Barat semata, melainkan telah berakar dalam nilai-nilai musyawarah dan keadilan yang hidup di desa-desa Nusantara jauh sebelum Republik ini berdiri.
Cak Nur, Sang pembaharu pemikiran Islam, pernah menegaskan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dia melihat jiwanya dalam Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad Saw merumuskan kontrak sosial yang memberi ruang bagi perbedaan, menegakkan keadilan, dan menempatkan manusia setara di hadapan hukum.
Sementara Bung Hatta, Bapak bangsa yang menemukan ruh demokrasi bukan di gedung parlemen, melainkan di balai desa. Di sanalah rakyat berkumpul, berbicara, dan mengambil keputusan tanpa sekat kuasa. Dalam bukunya “Demokrasi Kita”, Hatta menulis demokrasi bukan untuk memuja kekuasaan, tetapi untuk mengawalnya agar tetap berpihak kepada rakyat kecil yang tidak punya suara.
Keharusan Reformasi Demokrasi
Perjalanan demokrasi Indonesia kemudian berliku, dari demokrasi liberal yang bising namun bebas, menuju demokrasi terpimpin yang teratur tetapi membungkam, hingga demokrasi Pancasila yang mencoba menyeimbangkan harmoni dan kebebasan seiring dengan perjalanan bangsa.
Setiap fase lahir dari koreksi terhadap yang sebelumnya, sebuah siklus yang menandai bagaimana bangsa ini terus mencari format dan bentuk terbaik bagi dirinya sendiri. Tahun 1966, rakyat menegur kekuasaan yang tersesat. Tahun 1998, generasi muda mengguncang rezim yang menindas yang membuahkan ketidak-adilan yang berkepanjangan.
Saat ini, di tahun 2025, sejarah kembali mengetuk. Gerakan rakyat di akhir Agustus lalu mengajukan Petisi 17+8, sebuah panggilan hati nurani yang meminta dua hal, 17 koreksi untuk perilaku anggota parlemen yang lupa siapa tuannya, dan 8 tuntutan untuk menata ulang sistem demokrasi agar tidak lagi menjadi milik segelintir elit, melainkan milik bersama seluruh rakyat.
Keharusan reformasi demokrasi bukan semata tuntutan politik, melainkan kebutuhan moral bangsa ini. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang terbuka kini terasa sesak oleh dominasi kekuasaan. Presiden terlalu kuat tanpa imbangan yang sepadan.Sehingga melenggang nafsu kuasanya.
Konstitusi yang multitafsir kerap menjadi tameng, bukan penuntun. Literasi politik yang rendah menjadikan rakyat mudah dibujuk oleh janji, bukan visi. Budaya transaksional menukar suara dengan sembako, mengganti idealisme dengan pragmatisme. Demokrasi kita berjalan, tetapi pincang, bernafas, tetapi tersengal.
Reformasi yang dibutuhkan kini bukan sekadar menambal-sulam prosedur, melainkan merawat kembali jiwa yang telah retak dan terkoyak. Demokrasi harus menjadi media transformatif, bukan sekadar prosedural tetapi subtantif yang berkelanjutan.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara lima tahunan, melainkan harus menjelma menjadi kebiasaan berpikir, berbicara, dan bertindak. Demokrasi yang sejati bukan hanya memberi hak untuk memilih, tapi juga menumbuhkan keberanian untuk mengoreksi. Demokrasi bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan, tetapi cermin dalan nurani bangsa yang mencintai keadilan dan menghormati perbedaan.Dimana perbedaan sebagai keniscayaan untuk memperkokoh kebersamaan dan persatuan.
Agenda Reformasi Demokrasi
Reformasi demokrasi berarti menyusun ulang fondasi yang mulai rapuh, memperkuat Mahkamah Konstitusi agar tidak tunduk pada tekanan politik, menata sistem pemilu agar tidak lagi menjadi pasar transaksional, membuka ruang partisipasi rakyat di luar masa kampanye, dan melindungi hak warga negara bukan hanya dalam teks hukum, tetapi dalam praktik nyata.
Demokrasi yang berpijak pada akar budaya bangsa dan kesepakatan berbangsa yang tertuang Pancasila menuntut musyawarah, gotong royong, dan rasa adil. Dia adalah keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak individu dan harmoni sosial — namun tantangan terbesar kita bukan di lembaga negara, melainkan di dalam diri sendiri. Budaya politik yang dangkal membuat rakyat cepat lupa dan mudah menyerah. Media sosial menambah bising tanpa arah, dan elit politik mempermainkan narasi kebenaran seolah-olah milik mereka.
Padahal demokrasi sejati hanya bisa tumbuh jika rakyatnya berani berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menolak tunduk pada kebodohan yang terorganisir dan keangkuhan kekuasaan. Reformasi demokrasi kali ini harus menjadi koreksi moral bangsa. Dia bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijaga agar tidak merusak. Dia bukan tentang mengganti undang-undang, melainkan mengganti cara berpikir, dari menuntut hak menjadi berbagi tanggung jawab, dari menunggu perubahan menjadi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri yang dipelihara menjadi tradisi.
Demokrasi sejatinya bukan panggung yang kita saksikan, tetapi rumah yang kita rawat bersama. Dia akan runtuh bila hanya dijaga oleh politisi, dan akan hidup bila dijaga oleh rakyat yang sadar akan nilainya. Kini, setelah 25 tahun reformasi, mungkin inilah waktunya kita berhenti berdebat soal bentuk, dan mulai bekerja untuk jiwa, menata ulang hubungan antara kekuasaan dan keadilan, antara negara dan rakyat, antara suara dan nurani.
Karena demokrasi yang sehat tidak lahir dari janji, tetapi dari kejujuran. Dia tidak tumbuh di gedung tinggi, tetapi di hati yang mau mendengar. Dan mungkin, seperti kata Hatta dulu, demokrasi sejati hanya akan hidup bila rakyatnya mencintai kebenaran lebih dari kemenangan. Wallahu a‘lam bi shawab.
* Konsultan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencinta Ilmu Pengetahuan
Editor: Jufri Alkatiri