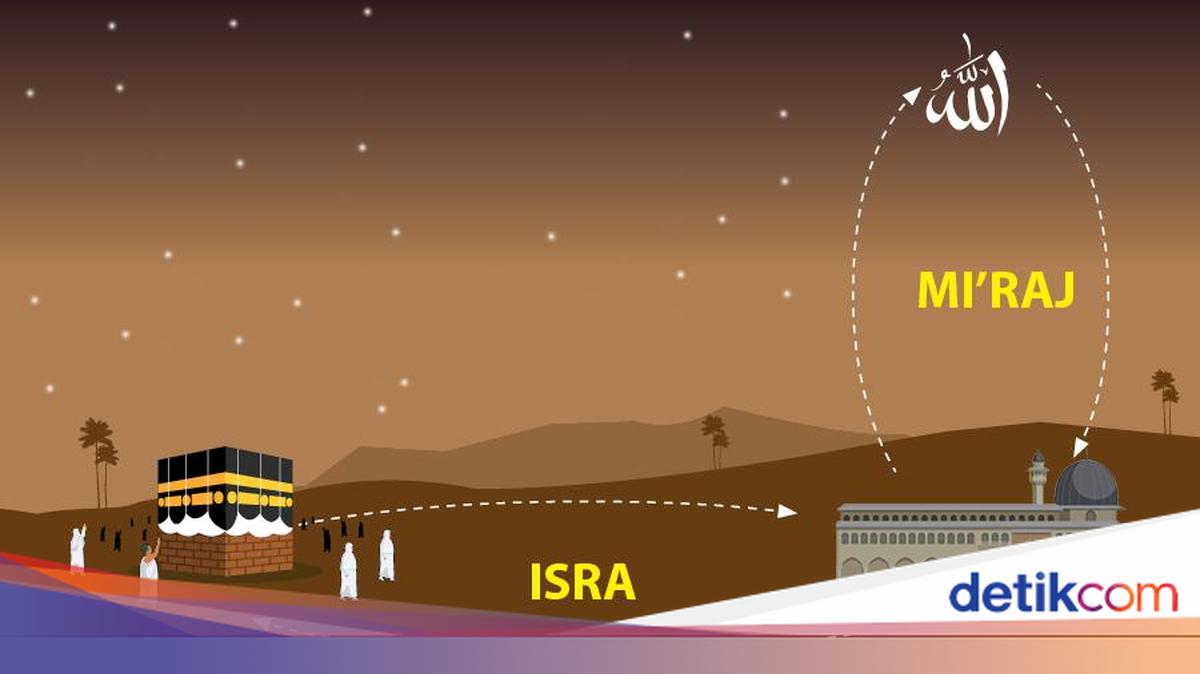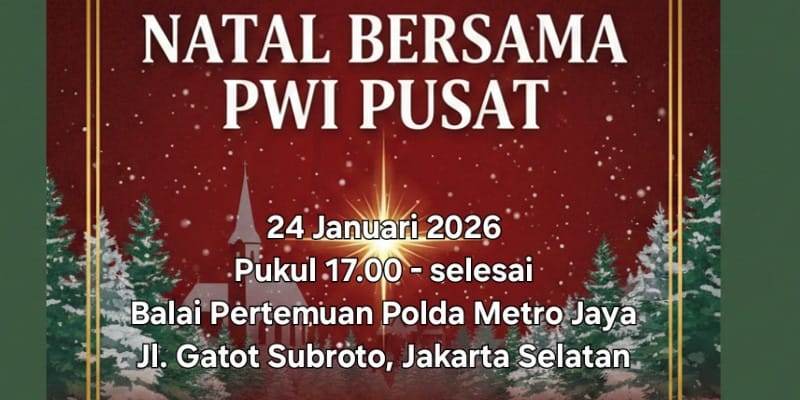Oleh : Prof Dr. Murodi al-Batawi, M.Si*
Pengantar
Dakwah Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman awal penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, serta peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam hingga upaya dakwah pada masa kontemporer — Indonesia telah menjadi contoh keberhasilan dakwah dalam membangun masyarakat yang beragam, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam dan hasil proses akulturasi budaya lokal sebagai local Wisdom, dengan ajaran dan nilai Islam. Tulisan ini akan mengulas mengenai perjalanan dakwah Islam di Indonesia (Nusantara), dari perspektif historis, menelusuri dinamika dan tantangan yang dihadapi sepanjang sejarah, serta implikasinya bagi masa depan dakwah di Indonesia. Tetapi dalam pertemuaan kali ini, penulis hanya berbicara soal Dakwah Islam pada Fase Pertama pertama dan media yang digunakan oleh para Da’i dalam penyebaran Islam di Indonesia.
Sejarah Awal kedatngan dan Dakwah Islam di Indonesia
Banyak teori yang menjelaskan mengenai kedatangan Islam di Nusantara (Indonesia), baik dari sisi waktu, pembawa, tempa, dan cara-cara atau metode yang digunakan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia telah terjadi sejak masa-masa awal perkembangan Islam di Timur Tengah di sekitar abad ke-7 M/abad ke-1 H, dan langsung dari Arab atau Persia. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru terjadi pada abad ke-11 M/ 5 H. Bahkan ada yang berpendapat Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M dan berasal dari Gujarat atau India.
Teori-teori tersebut memiliki landasan dan argumentasi masing-masing, sehingga antara satu teori dengan teori lainnya sebenarnya tidak bertentangan, melainkan menjadi pelengkap dari berbagai teori yang ada. Di antara para ahli yang mengatakan bahwa agama Islam telah datang ke Indonesia (Nusantara) sejak masa-masa awal perkembangannya di Timur Tengah. Mereka antara lain adalah Thomas W. Arnold, (The Preaching of Islam) Azyumardi Azra,(Jaringan Ulama), Hamka (Sejarah Umat Islam), Uka Tjandrasasmita, (Arkeologi Umat Islam Indonesia), A. Hasymi (Sejarah Kebudayaan Islam), dan lain-lain.
Para ahli ini mengatakan bahwa berdasarkan data yang dicatat oleh seorang pendeta Buddha Cina bernama I-Tsing, yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India dengan menggunakan kapal Posse dan singgah di Bhoga (diduga Palembang, Sumatra Selatan) bahwa di sekitar tahun 674 M di bagian Barat Sumatera terdapat perkampungan komunitas Arab atau Persia Muslim, yang di sebutnya sebagai komunitas Ta-Shih dan Po-sse. Mereka umumnya adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Karena hubungan itu dianggap saling menguntungkan, maka Sriwijaya memberikan daerah khusus bagi pedagang tersebut. Selain data tersebut, Azyumardi menemukan adanya indikator lain berupa kata bersila. Kata ini menunjukkan bahwa tradisi itu bukan berasal dari tradisi keraton, tetapi berasal dari tradisi Arab atau Persia yang egaliter. Sebab, kalau kita lihat dari tradisi keraton, bilamana seseorang ingin bertemu dengan raja, maka orang tersebut harus merangkak ke depan dan ketika berhadapan dengan raja, dia harus bersujud. Dalam tradisi Arab Islam, sujud hanya diperbolehkan di hadapan Allah, bukan dihadapan makhluknya. Berdasarkan teori itu, dapat dipahami bahwa sebenarnya agama Islam telah datang ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 M atau abad ke-1 H. Agama Islam ini langsung dibawa oleh para saudagar dan muballigh yang berasal dari negeri Arab atau Persia.
Pendapat kedua mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru ter jadi sekitar abad ke-11 M/5 H. Data ini didasari atas temuan arkeologis berupa batu nisan. Bukti arkeologis tersebut kebanyakan ditemukan di daerah jalur perdagangan internasional serta jalur persimpangan.
Batu nisan tertua yang ditemukan di Indonesia berupa batu nisan kuburan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tanggal 7 Rajab 475 H/Desember 1082 M. Bentuk nisan dan tulisannya sama dengan batu nisan Ahmad bin Abu Ibrahim bin Arradh Rahdar alias Abu Kamil (w. Kamis Ma lam, 29 Safar 431 H/1039 M) yang ditemukan di Phanrang, Vietnam. Pada kedua batu nisan tersebut terdapat kaligrafi Arab dengan jenis huruf Kufi bercorak Timur Tengah, yaitu dengan tanda hiasan bentuk kali atau lengkungan pada bagian ujung yang tegak. Gaya huruf Kufi seperti itu berkembang di Persia pada akhir abad ke-10 M.7 Berdasarkan data arkeologis ini, maka dapat diperkirakan bahwa di pesisir Utara Jawa Timur, khususnya di Leran, Gresik, telah terdapat sekelompok komunitas Muslim yang berasal dari Timur Tengah. Dengan kata lain, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Timur Tengah yang dibawa oleh para saudagar dan muballigh Arab atau Persia Muslim. (Uka, Arkeologihlm.12. Azra, Jaringan, hlm. 7).
Sementara itu, terdapat teori lain yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara (Indonesia) sekitar abad ke-13 M dan berasal dari Gujarat, India. Teori ini didasari atas data-data arkeologis berupa batu nisan pada makam raja Malikus Saleh yang ditemukan di kerajaan Islam Samudera Pasai (D.I.Aceh). Batu nisan ini bertuliskan angka tahun 686 H/1297 M.
Berdasarkan hasil penelitian arkeologis, batu nisan ini berasal dari Gujarat, India, dan jenis batu ini sering digunakan oleh pemeluk Hindu Gujarat untuk membangun kuil-kuil mereka, selain sebagai barang dagangan. Hubungan dagang antara Samudera Pasai terus berlanjut, hingga kedua bangsa ini memeluk Islam.
Teori ini diperkuat oleh pendapat Christian Snouck Hurgronje. Snouck mengatakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 M dan berasal dari Gujarat, India. Teori ini didasari atas hasil analisisnya mengenai adanya unsur-unsur lokal berupa animisme dan dinamisme (sebenarnya bukan animisme dan dinmisme, tetapi penduduk Jawa non penguasa, menganut kepercayaan Kanayan, yaitu kepercayaan pada hal-hal ghaib, sesuatu yang tidak tampak, selain mereka. Dalam tradisi agama Hindu Budha, terdapat kasta, mereka bukan pemeluk agama Hindu Budha) yang terdapat dalam ajaran Islam pada masa itu.
Menurutnya, ajaran Islam yang diterima oleh pemeluknya di Indonesia, telah tercemar oleh ajaran mistisisme. Lebih jauh Snouck menggambarkan hal tersebut dengan aliran air sungai yang mengalir. Indonesia digambarkannya sebagai hilir, tempat air sungai berhenti. Sementara Arab, Timur Tengah di gambarkannya dengan hulu sungai. Kalau agama Islam datang dari Arab, maka ajaran yang diterima masyarakat Indonesia juga masih murni. Tetapi kenyataannya, ajaran Islam yang dianut masyarakat Muslim Indonesia pada masa itu telah tercemar oleh tradisi lokal berupa ajaran animisme dan dinamisme yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhamad di Makkah dan Madinah.
Meskipun teori ini tidak begitu kuat, banyak ahli atau sejarawan Indonesia yang berpedoman pada teori ini. Hal itu didasari atas kenyataan sejarah bahwa masih banyak sejarawan Indonesia yang mampu mengungkap data-data penting yang diambil dari manuskrip yang banyak terdapat di Indonesia. Meskipun begitu, teori ini menjadi pelengkap dari beberapa teori yang telah di kemukakan para ahli sejarah Indonesia.
Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa Islam datang ke Indonesia melalui beberapa periode. Periode pertama (abad ke-7 hingga abad ke-12 M), merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas Muslim, terutama para pedagang Muslim. Karena itu, penyebaran agama Islam (Dakwah) juga masih sangat terbatas. Para penyebar agama Islam ini berasal dari negeri-negeri Islam, baik di Timur Tengah maupun di India. Pada umumnya mereka adalah para saudagar kaya yang juga bertindak sebagai juru dakwah (Da’i) . Sementara periode kedua (abad ke-13 hingga abad ke-16 M), merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam awal.
Karena itu pula, pada periode ini penyebaran agama Islam telah meluas, bahkan sudah membentuk kekuatan sosial politik yang mengambil bentuk kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam Peurlak (Aceh Timur) dengan raja Muslim pertama, Sultan Muhamad Amir Syah (1225-1263 M), Kerajaan Islam Demak (1500-1546 M), Pajang (1546-1582 M), Mataram (15 82-1788 M), Cirebon (1452 M), Banten (1526 -1811 M), Kerajaan Islam Sukadana (1590 M), Kerajaan Islam Banjar (1550 -1860 M), Kerajaan Islam Gowa (1519-1669 M), dan lain-lain. (bersambung)
*Profesor Sejarah dan Peradaban serta Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Edito: Jufri Alkatiri