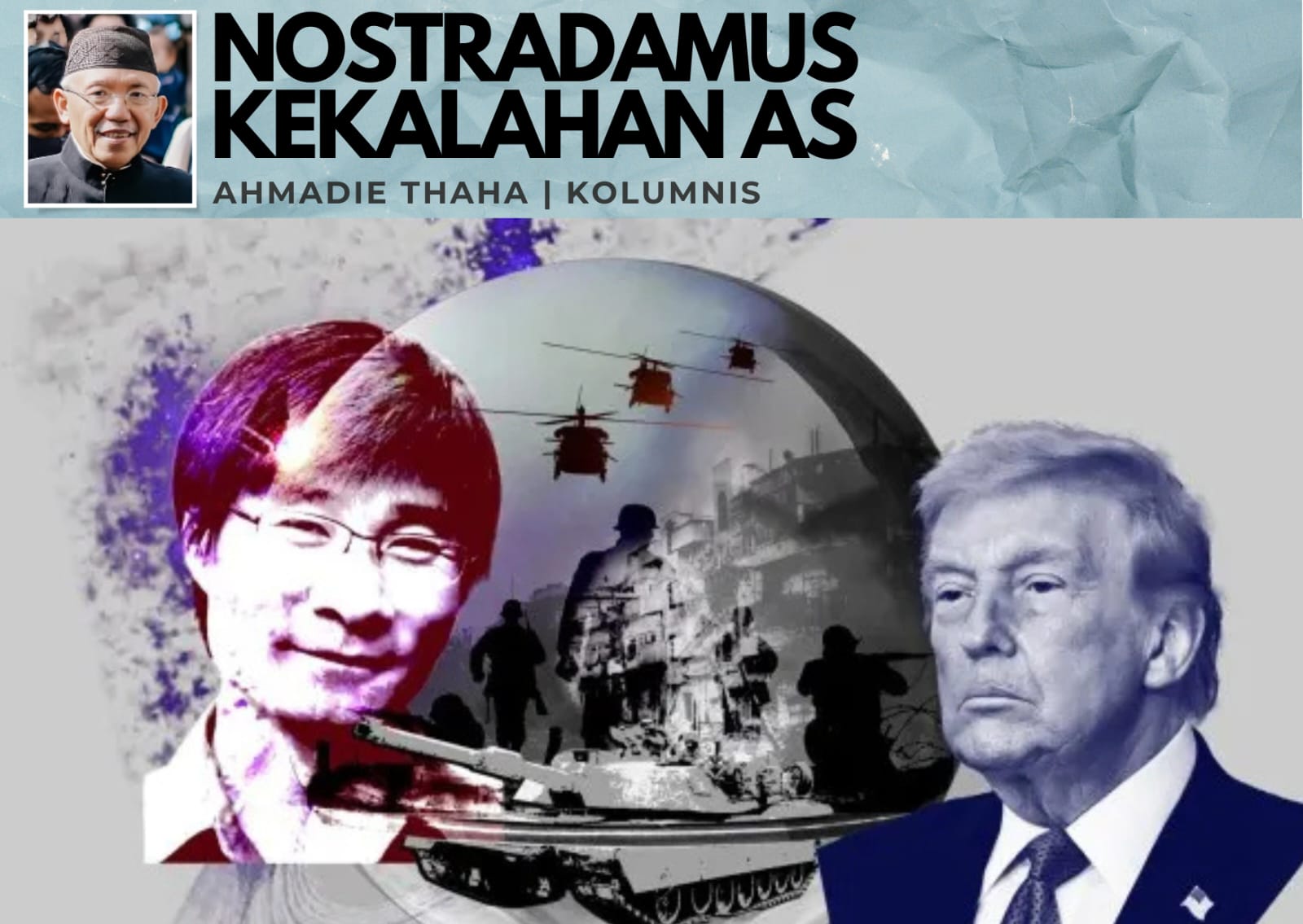Oleh: Benz Jono Hartono*
Di salah satu negeri tropis yang gemar bersorak tetapi jarang bercermin, pendidikan dianggap suci—tetapi ijazah lebih dihormati ketimbang ilmu. Di sana, selembar kertas berstempel universitas bisa menentukan nasib reputasi seorang pemimpin. Ironisnya, justru di era ketika satelit bisa memotret wajah dari langit dan algoritma bisa membaca isi kepala, rakyat negeri itu sibuk membuktikan apakah sang pemimpin benar-benar pernah duduk di bangku kuliah.
Negeri itu ramai oleh debat kertas dan tanda tangan. Para penganut “iman digital” berseteru di media sosial, menghitung jenis font, meneliti goresan tinta, seolah mereka para ahli Paleografi yang sedang memeriksa manuskrip kuno. Di sisi lain, aparatnya sibuk mencari kebenaran formal: apakah kertas itu asli, apakah capnya sah, apakah tanda tangan rektor masih hidup. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, intelijen dari negeri lain tersenyum tenang—karena mereka tahu, bangsa yang sibuk membuktikan ijazah pemimpinnya sudah tidak sempat memperkuat pertahanannya.
Ijazah sebagai Simbol Keabsahan dan Alat Perang Reputasi
Dalam politik moderen, ijazah bukan sekadar bukti pendidikan—dia adalah simbol legitimasi moral. Sebab rakyat di negeri tropis itu percaya, pemimpin harus “pantas”, bukan hanya “mampu”. Maka, selembar kertas dari universitas lokal lebih dihargai daripada seribu keputusan bijak di lapangan. Begitu kertas itu dipertanyakan, reputasi pun terbelah: separuh rakyat berteriak “palsu!”, separuh lainnya membalas “fitnah!”. Negeri itu seperti kapal tanpa nakhoda moral, terombang-ambing oleh badai unggahan di media sosial.
Namun, jika diamati dari ketinggian geopolitik, drama ini lebih dari sekadar pertikaian domestik. Dia adalah pintu terbuka bagi “angin dari timur”—intelijen dari negeri tirai bambu—yang pandai meniupkan kabar, menanamkan persepsi, dan membelokkan arah kepercayaan. Sebab dalam dunia intelijen, perang tidak lagi dimenangkan dengan peluru, melainkan dengan keraguan. Dan keraguan adalah senjata paling halus yang pernah diciptakan manusia.
Bayang-Bayang dari Timur Strategi Intelijen dalam Era Narasi
Negeri tirai bambu, dengan mata-mata yang berlapis sabar dan sabda yang dibungkus kerjasama ekonomi, telah lama paham bahwa pengaruh tidak perlu datang lewat invasi. Cukup lewat “koneksi”, “investasi”, dan “cerita”. Mereka punya lembaga intelijen sipil yang tidak sekadar mengumpulkan rahasia, tetapi menanam benih pengaruh. Dia bekerja dalam diam, lewat proyek, jaringan digital, dan kadang melalui berita yang setengah benar, setengah bohong—campuran sempurna untuk mengguncang logika publik.
Di era di mana fakta dan opini berjalan beriringan seperti sepasang kekasih mabuk, dinas itu menari di antara algoritma. Mereka memahami satu hal sederhana: rakyat moderen lebih percaya video pendek ketimbang buku tebal. Maka, cukup dengan beberapa potongan gambar, beberapa akun anonim, dan ribuan komentar palsu, sebuah bangsa bisa diarahkan untuk meragukan pemimpinnya sendiri.
Dalam konteks itu, negeri tropis menjadi laboratorium empuk —dengan sistem politik yang penuh kompromi, elite yang haus validasi, dan rakyat yang senang bersuara tanpa membaca, setiap isu bisa tumbuh menjadi badai nasional. Termasuk soal ijazah.
Pendidikan, Politik, dan Kolonialisme Gaya Baru — yang lebih ironis, negeri tropis itu sejatinya punya sejarah panjang dijajah, ditipu, dan dipelajari. Tapi setelah merdeka, ia tetap menjadi obyek pelajaran—kali ini bukan oleh penjajah berseragam, melainkan oleh algoritma global dan lembaga intelijen yang berkedok diplomasi.
Pendidikan nasionalnya berbicara tentang “kemandirian”, tetapi kurikulumnya masih mengukur manusia dengan nilai dan sertifikat. Maka, tidak heran bila rakyatnya menilai pemimpin dari ijazah, bukan dari kebijakan. Dan di saat rakyat memperdebatkan keaslian kertas, lembaga-lembaga asing memperdebatkan keaslian kedaulatan.
Sementara para intelektual sibuk menulis opini tentang “nasionalisme digital”, para agen dari negeri tirai bambu sudah menanam kabel, memasang server, dan membaca percakapan publik lewat perangkat yang kita beli dengan sukacita lewat e-commerce. Tidak ada yang lebih indah bagi intelijen asing selain bangsa yang rela menyerahkan datanya demi potongan harga.
Operasi Pengaruh dari Jalur Sutra ke Jalur Narasi
Dulu, negeri tirai bambu membangun Jalur Sutra untuk berdagang rempah dan sutra. Kini mereka membangun jalur narasi: jaringan media, akun global, aplikasi, dan kerjasama ekonomi yang membawa pesan halus—bahwa masa depan dunia ada di bawah pengaruh mereka.
Mereka tidak perlu memata-matai dengan kamera tersembunyi, cukup biarkan bangsa lain berbicara, berdebat, dan saling mencurigai di platform mereka sendiri. Itulah bentuk penjajahan paling canggih: membuat bangsa lain percaya bahwa mereka bebas, padahal sedang diarahkan. Dan negeri tropis itu, dengan isu ijazah yang tidak kunjung selesai, menjadi panggung sempurna bagi operasi pengaruh semacam itu. Karena setiap kali rakyatnya sibuk memaki pemimpinnya sendiri, para mata-mata di luar negeri hanya perlu duduk, mencatat, dan menunggu data mengalir ke server mereka.
Intelijen dalam Bayangan Pendidikan
Pendidikan seharusnya melahirkan kecerdasan kolektif tapi di negeri tropis itu, dia justru menciptakan kesenjangan intelektual. Mereka yang berijazah tinggi sibuk mempertahankan gelar, sementara yang tidak berijazah sibuk membuktikan pemimpinnya palsu. Intelijen asing tidak perlu lagi menyusup ke kampus atau kementerian. Mereka cukup memanfaatkan kelemahan mental bangsa: rasa minder terhadap asing dan rasa bangga terhadap simbol. Dua racun yang sempurna untuk mengendalikan sebuah negeri tanpa perang. Dan ketika lembaga keamanan sibuk memantau “ancaman fisik”, ancaman terbesar datang dari ruang digital yang mereka abaikan. Di situlah “bayang-bayang dari timur” menanam pengaruhnya: membentuk opini, memecah kelompok, dan menciptakan ketidakpercayaan sistemik.
Dari Ijazah ke Ideologi Ketika Bangsa Kehilangan Fokus
Ijazah sang pemimpin akhirnya menjadi simbol yang lebih besar dari sekadar dokumen. Dia adalah cermin bangsa—betapa mudahnya kita mengalihkan perhatian dari hal besar ke hal kecil. Ketika negara-negara lain berdebat soal kecerdasan buatan, kita masih berdebat soal keaslian tanda tangan. Ketika dunia bicara tentang kedaulatan data, kita masih sibuk mempermasalahkan format ijazah. Inilah tragedi intelektual bangsa yang terlalu lama hidup di antara dua penjajahan: penjajahan fisik masa lalu, dan penjajahan narasi masa kini.
Mereka mengira intelijen hanya urusan mata-mata bersetelan gelap. Padahal intelijen hari ini adalah algoritma, opini, dan trending topik. Negeri tirai bambu paham betul: jika kau ingin menundukkan bangsa lain, cukup buat mereka kehilangan fokus.
Kedaulatan Antara Paranoia dan Naifisme
Sementara itu, para elit negeri tropis berjalan di antara dua ekstrem: paranoia dan naifisme. Sebagian melihat bayangan di setiap pojok dan menuduh semua kritik sebagai agen asing. Sebagian lain menganggap semua bentuk kerjasama sebagai cinta damai global, seolah dunia tidak punya kepentingan tersembunyi. Padahal, dunia intelijen bukan tentang benar atau salah. Dia tentang siapa yang lebih dulu tahu dan siapa yang lebih lama percaya. Dan di titik ini, negeri tropis itu kalah di dua-duanya.
Ketika rakyatnya masih sibuk menghitung huruf di ijazah, para analis asing sudah menghitung probabilitas politik, dan para investor menyiapkan skenario masa depan. Ketika pemimpinnya membantah tuduhan palsu, para agen di luar negeri belajar pola reaksi sosialnya. Karena bagi mereka, setiap skandal domestik adalah laboratorium psikologi bangsa.
Ijazah, Intelijen, dan Iman Kolektif — ada pepatah lama di negeri itu: “Bangsa besar adalah bangsa yang menghormati gurunya.”Sayang,mereka lupa menambahkan: “…bukan hanya gurunya, tetapi juga pelajarannya.” Bangsa itu menghormati simbol ilmu, tetapi tidak lagi menghormati proses berpikir. Mereka mengira kecerdasan lahir dari sertifikat, padahal kecerdasan lahir dari kesadaran. Mereka bangga menjadi konsumen teknologi, tetapi jarang bertanya: siapa yang membaca data kita di balik layar? Dan begitulah, ketika rakyat negeri tropis terbelah antara pembela dan penuduh, sang intelijen dari timur hanya mengamati—dengan tenang, dengan sabar, dengan senyum penuh makna. Sebab musuh yang terbaik adalah bangsa yang sedang sibuk menertawakan dirinya sendiri.
Mencari Ijazah Nalar Nasional
Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang selembar ijazah, bukan tentang pemimpin tertentu, bukan pula tentang negeri tirai bambu. Ini tentang bangsa yang belum lulus dari ujian sejarahnya sendiri. Bangsa yang belum menulis ulang kurikulumnya tentang kemandirian berpikir dan kesadaran geopolitik. Mungkin yang kita butuhkan bukan verifikasi ijazah pemimpin, tetapi ijazah nalar nasional—sebuah sertifikat bahwa rakyatnya telah dewasa dalam memahami permainan global.
Bahwa mereka tahu kapan berita adalah fakta, kapan kabar adalah propaganda, dan kapan diam adalah bentuk kebijaksanaan. Karena selama bangsa ini masih berebut membuktikan siapa yang palsu dan siapa yang asli, dunia luar akan terus menikmati tontonan gratis tentang bangsa besar yang lupa memeriksa dirinya sendiri. Di balik layar, “angin dari timur” itu akan terus berhembus—tidak keras, tidak kasar, tetapi cukup dingin untuk membuat akal sehat bangsa perlahan membeku.
*Hiawatha Institute dan Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat
Editor: Jufri Alkatiri